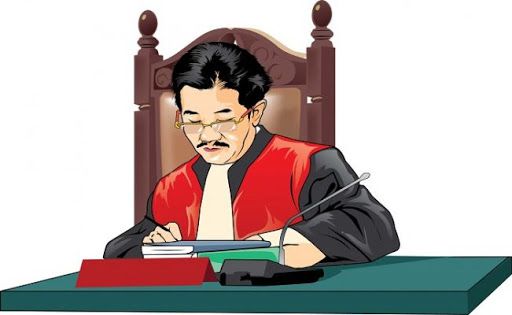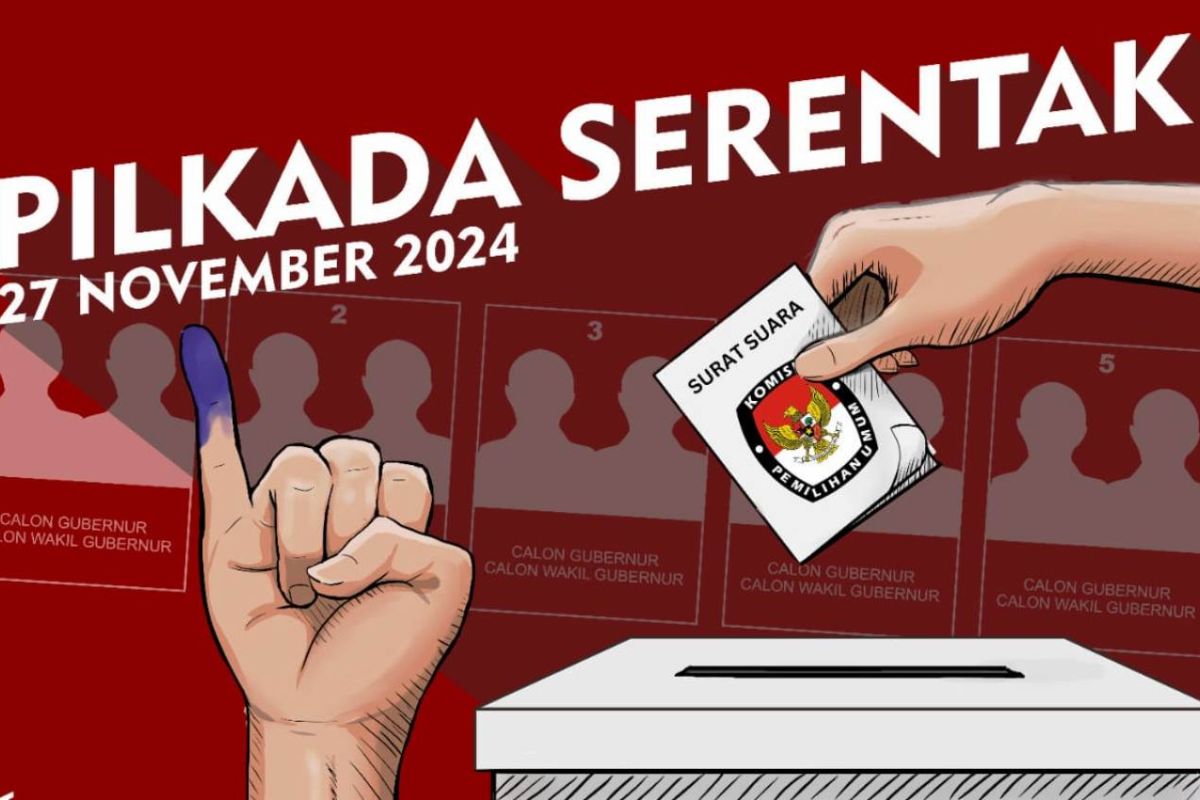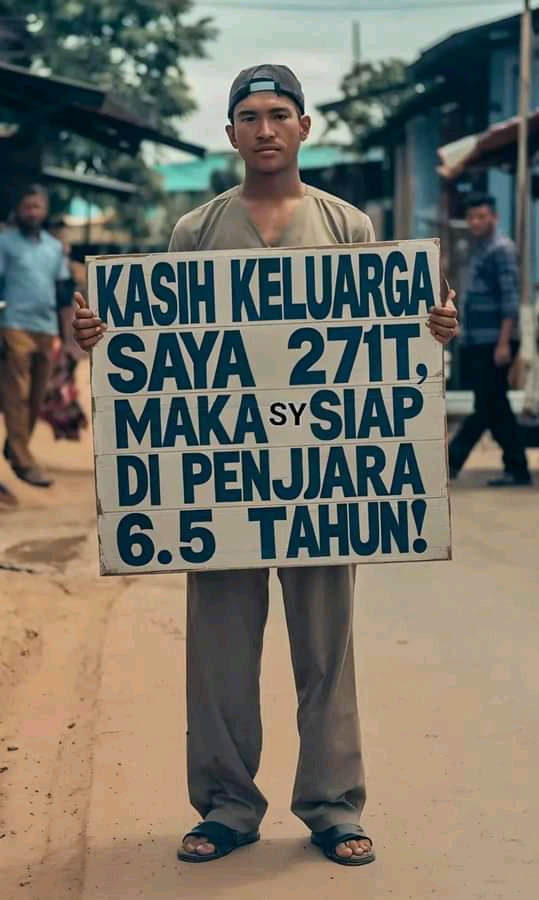Tradisi memanggil hakim dengan sebutan “Yang Mulia” di ruang sidang kembali menuai sorotan tajam. Sejumlah pakar hukum dan tokoh nasional menilai, sapaan tersebut merupakan warisan budaya feodalisme yang berpotensi menimbulkan kesewenang-wenangan dan mengikis prinsip kesetaraan di depan hukum.
Mantan Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD secara tegas menyebutkan bahwa penggunaan sebutan “Yang Mulia” bagi hakim adalah bentuk feodalisme yang tidak relevan lagi di era modern. Menurut Mahfud, sapaan tersebut dapat menimbulkan jarak antara hakim dan masyarakat, bahkan berpotensi menumbuhkan sikap sewenang-wenang di kalangan aparat peradilan. “Sebutan ‘Yang Mulia’ itu feodal dan bisa menimbulkan kesewenang-wenangan. Hakim itu pelayan keadilan, bukan penguasa yang harus diagung-agungkan,” tegas Mahfud MD dalam sebuah pernyataan yang dikutip Tribunnews (6/11/2024).
Kritik serupa juga disampaikan dalam artikel Marinews Mahkamah Agung, yang menyoroti bahaya laten budaya feodalisme di lembaga peradilan. Budaya feodal dinilai membuka ruang bagi praktik patronase, nepotisme, dan monopoli kekuasaan, sehingga mengancam integritas serta independensi lembaga peradilan. “Feodalisme menanamkan mentalitas hierarkis dan menciptakan kesenjangan antara penguasa dan masyarakat. Dalam konteks peradilan, hal ini bisa menimbulkan ketidaksetaraan di depan hukum dan memperkuat praktik korupsi serta intervensi kekuasaan,” tulis Marinews Mahkamah Agung.
Dalam konteks hukum modern, prinsip utama yang harus dipegang adalah kesetaraan di depan hukum (equality before the law) dan supremasi hukum (supremacy of law). Kedua prinsip ini menuntut agar setiap warga negara tanpa terkecuali dipandang setara di hadapan hukum dan tidak ada pihak yang mendapat perlakuan istimewa hanya karena jabatan atau statusnya. Sebutan “Yang Mulia” bagi hakim dapat menciptakan jarak hierarkis antara hakim dan masyarakat, sehingga berpotensi mengikis prinsip kesetaraan tersebut.
Selain itu, independensi dan imparialitas hakim juga menjadi ciri penting hukum modern. Hakim diharapkan memutus perkara secara objektif, bebas dari pengaruh kekuasaan, dan tidak memihak. Namun, penggunaan istilah yang menempatkan hakim di posisi “istimewa” justru dapat menimbulkan kesan bahwa hakim berada di atas hukum, bukan sebagai pelayan hukum yang netral. Hal ini bertentangan dengan prinsip rule of law yang menekankan bahwa hukum adalah kekuasaan tertinggi, bukan individu atau jabatan tertentu.
Meski demikian, tradisi memanggil hakim dengan sebutan “Yang Mulia” masih terus dipertahankan di banyak ruang sidang di Indonesia. Dalam laporan Klasika Kompas, disebutkan bahwa tidak ada aturan hukum yang secara tegas mewajibkan penggunaan sapaan tersebut. Namun, sejumlah peraturan tata tertib persidangan memang mengatur kewajiban untuk menghormati hakim, salah satunya dengan berdiri dan membungkukkan badan saat hakim memasuki atau meninggalkan ruang sidang. Penyebutan “Yang Mulia” pun dianggap sebagai bentuk penghormatan dan harapan agar hakim dapat bersikap adil dan bijaksana dalam memutus perkara.
Sumber :
https://klasika.kompas.id/baca/mengapa-hakim-dipanggil-yang-mulia/

 Nadia Nurhalija, S.H
Nadia Nurhalija, S.H