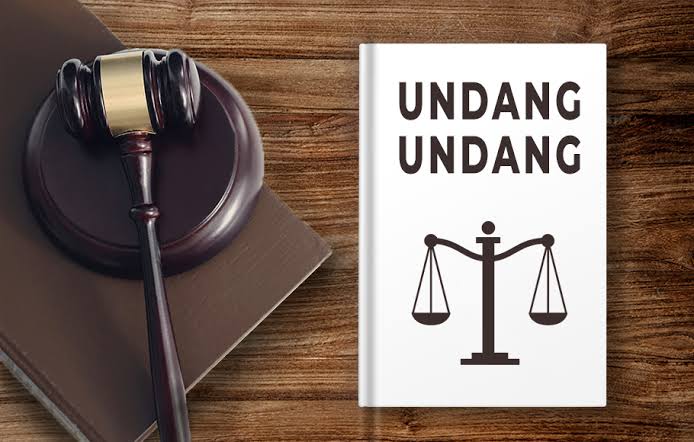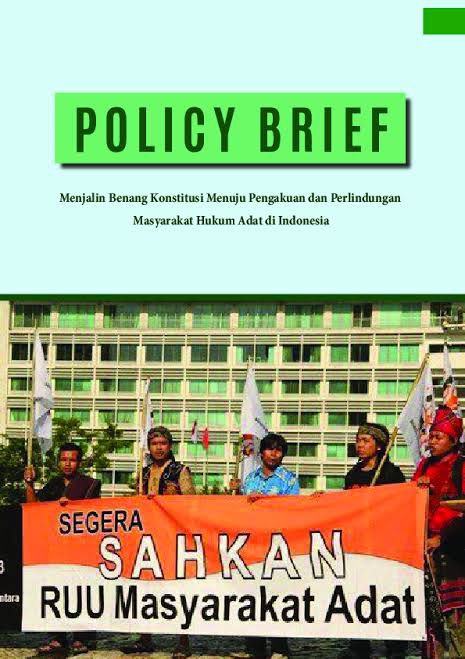Integritas sistem peradilan kembali menjadi sorotan seiring terungkapnya skandal suap yang melibatkan hakim. Kasus terbaru ini mirip dengan insiden sebelumnya di mana hakim diduga menerima uang sebagai imbalan atas putusan yang menguntungkan. Kejaksaan Agung telah menahan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan menetapkan tiga hakim lagi sebagai tersangka dalam kasus suap terkait kasus korupsi ekspor minyak goreng.
Para hakim ini didakwa menerima total Rp60 miliar dari tiga korporasi kelapa sawit sebagai imbalan atas pembebasan terdakwa. Skandal ini mencapai titik kritis ketika, pada 19 Maret 2025, majelis hakim yang terdiri dari Juyamto, Ali Muhtarom, dan Agam Syarif memutuskan memenangkan korporasi tersebut, meskipun jaksa menuntut ganti rugi yang cukup besar. Wilmar Group diharuskan membayar Rp11,8 triliun, Permata Hijau Group Rp937 miliar, dan Musim Mas Group Rp4,8 triliun. Namun, para hakim menyatakan bahwa tindakan korporasi tersebut bukan merupakan tindak pidana.
Menanggapi tuduhan tersebut, Mahkamah Agung telah menangguhkan sementara para hakim dan panitera yang terlibat dalam kasus tersebut. Mereka akan tetap ditangguhkan hingga keputusan hukum final tercapai, dan penangguhan permanen dapat dilakukan jika mereka terbukti bersalah.
Para pakar hukum telah menyatakan kekhawatiran bahwa penyuapan dan korupsi di kalangan hakim akan terus berlanjut kecuali ada sistem pengawasan yang kuat dan hukuman yang lebih berat bagi mereka yang terbukti bersalah. Mereka menganjurkan pendekatan ganda terhadap pengawasan—baik internal maupun eksternal—di mana publik terlibat dalam pemantauan perilaku peradilan. Transparansi dalam data dan proses sangat penting untuk pengawasan publik yang efektif.
Diskusi seputar integritas peradilan semakin hangat dengan komitmen Presiden Prabowo baru-baru ini untuk menaikkan gaji hakim, yang bertujuan untuk mengurangi godaan suap. Ia menekankan perlunya hakim menerima kompensasi yang memadai untuk menegakkan martabat mereka dan melawan korupsi. Namun, para kritikus berpendapat bahwa sekadar menaikkan gaji mungkin tidak mengatasi akar penyebab korupsi peradilan, karena banyak hakim telah menerima tunjangan yang cukup besar.
Misalnya, hakim di tingkat pertama dan banding bisa mendapatkan tunjangan antara 15 hingga 56 juta rupiah, sementara hakim di Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi bisa mendapatkan hingga 77 juta rupiah. Hal ini menimbulkan pertanyaan apakah insentif finansial saja bisa efektif mencegah praktik korupsi.
Saat negara bergulat dengan masalah yang terus berlanjut ini, seruan untuk reformasi menyeluruh terhadap sistem peradilan semakin menguat. Integritas hakim, yang sering disebut sebagai “tangan Tuhan” dalam menegakkan keadilan, menjadi hal yang terpenting. Masyarakat dan pakar hukum sama-sama mengamati dengan saksama bagaimana skandal ini terungkap dan tindakan apa yang akan diambil untuk memulihkan kepercayaan terhadap sistem peradilan.
Saat penyelidikan terus berlanjut, harapannya tetap bahwa sistem peradilan dapat muncul lebih kuat dan lebih transparan, memastikan keadilan ditegakkan tanpa bayang-bayang korupsi.

 Titin Umairah, S.H
Titin Umairah, S.H