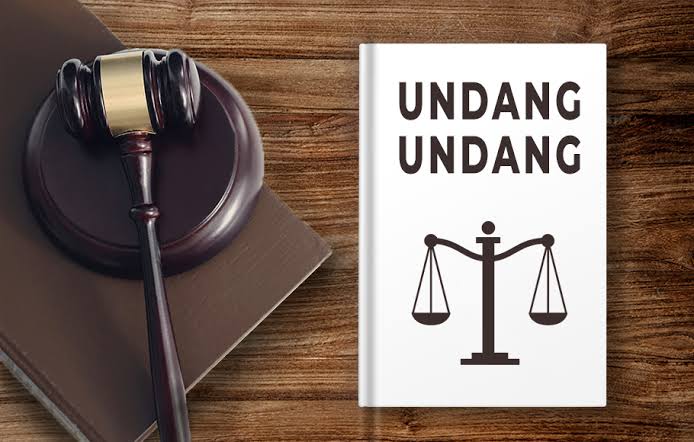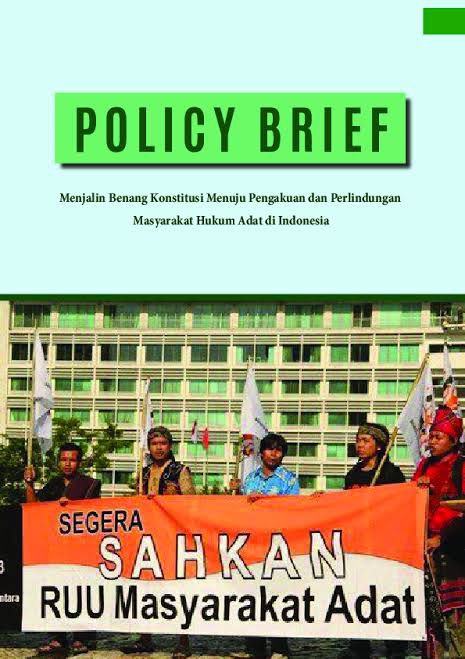Sejak dilantik, kabinet Prabowo Subianto seperti pasar pagi: ramai, riuh, dan penuh suara yang tak selalu nyambung. Bedanya, di pasar pagi orang berebut pembeli. Di kabinet, para menteri tampaknya berebut panggung.
Sri Mulyani bilang negara tak mampu memberi gaji besar bagi guru dan dosen. Nusron Wahid, Menteri ATR/BPN, melontarkan candaan soal tanah milik negara. Satu membikin hati pendidik ciut, satu lagi membuat tata kelola pertanahan terdengar seperti bahan guyon.
Presiden? Diam. Tidak ada teguran, tidak ada klarifikasi, tidak ada sinyal bahwa ia memegang kendali. Di podium kekuasaan, candaan bisa lebih mematikan daripada kebijakan yang keliru. Sebab, yang tertawa mungkin hanya segelintir orang, tapi yang resah adalah seluruh negeri.
Nusron mengira guyonannya soal tanah negara akan mengundang senyum. Yang datang justru kecurigaan: apakah pengelolaan aset negara sebebas itu? Sri Mulyani mungkin sekadar menjelaskan kondisi fiskal. Tapi bagi para guru dan dosen, ucapannya adalah pengakuan bahwa mereka memang tidak diutamakan.
Dalam politik, persepsi sering kali lebih kuat dari kenyataan. Dan di era media sosial, satu kalimat bisa menenggelamkan ratusan program pemerintah.
Presiden Punya Gigi, Tapi Tak Menggigit
UUD 1945 memberi presiden gigi yang tajam: hak mengangkat dan memberhentikan menteri. Dalam tradisi presidensial, teguran publik, pembatasan kewenangan, atau reshuffle adalah alat untuk menjaga disiplin kabinet.
Ketika presiden memilih untuk tidak menggigit, publik akan bertanya-tanya: apakah ia takut kehilangan dukungan koalisi, atau justru menikmati kebisingan ini sebagai strategi?
Keduanya sama-sama berbahaya. Koalisi yang dibiarkan mengatur lidah menteri akan melahirkan kabinet tanpa komando. Strategi gaduh, jika memang disengaja, akan membuat publik lelah lebih cepat dari masa jabatan.
Dalam pemerintahan yang menghargai etika jabatan, ucapan Nusron dan Sri Mulyani sudah cukup untuk memicu minimal teguran tertulis. Bahkan, reshuffle dini bisa jadi pelajaran.
Pilihan sanksi ada di tangan presiden: mulai dari peringatan resmi, pembatasan wewenang, evaluasi terbuka, hingga pencopotan. Tidak ada yang melanggar hukum. Yang menghalangi hanya kalkulasi politik dan kalkulasi politik jarang berpihak pada integritas.
Kursi menteri bukan kursi komedian. Mikrofon di tangan pejabat publik bukan alat untuk uji materi lawakan. Setiap kata mereka adalah sinyal kebijakan dan wajah negara.
Jika presiden terus membiarkan panggung ini jadi ajang improvisasi bebas, rakyat akan tahu bahwa masalahnya bukan pada menteri yang cerewet, tapi pada presiden yang membiarkan.
Kapal besar ini sedang berlayar di laut penuh badai. Awak kapal sibuk bercanda, dan nahkodanya memilih tersenyum di dek. Sampai kapan penumpang akan percaya bahwa kapal ini masih punya tujuan? Kata sakti “maaf” menjadi senjata ampuh para menteri untuk mengakhirinya. Benar-benar negara yang lucu!

 Desi Sommaliagustina
Desi Sommaliagustina