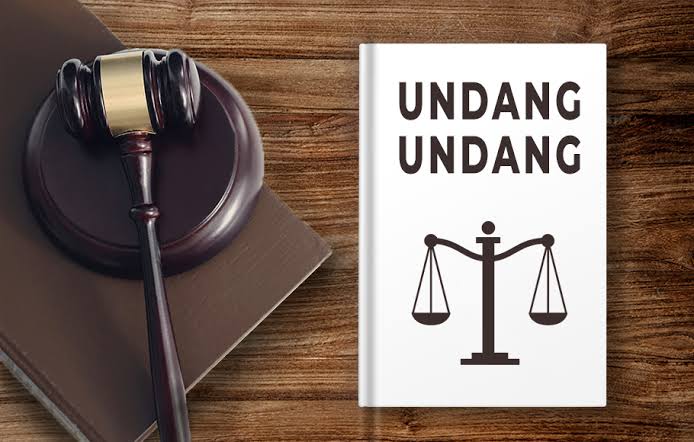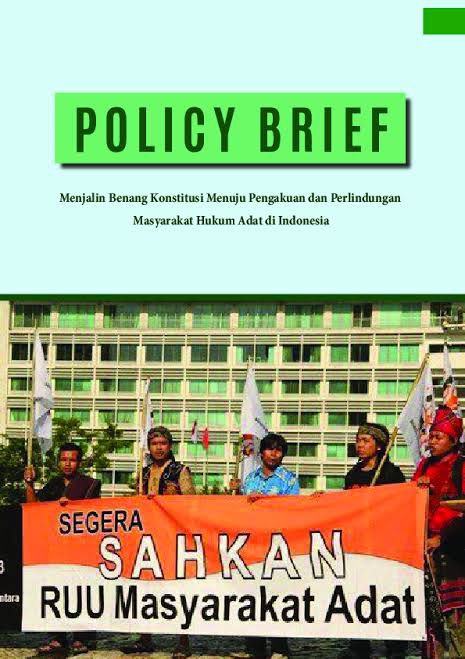Perang dagang Amerika Serikat dan China kembali bergulir dalam intensitas tinggi. Presiden Donald Trump mengumumkan penerapan tarif tambahan hingga 25 persen terhadap produk-produk asal China, termasuk baja, perangkat elektronik, dan barang konsumsi strategis. China, melalui Kementerian Perdagangannya, merespons dengan tarif balasan, mengisyaratkan bahwa konflik dagang lintas Pasifik ini belum akan mereda.
Yang mengejutkan bukan hanya tindakan, melainkan pernyataan politik yang menyertainya. “Jika Amerika ingin perang—perang tarif, dagang, atau bahkan teknologi kami siap hingga titik akhir,” ujar Kedutaan Besar China di Washington, dikutip oleh Kompas TV (9 April 2025).
Pernyataan itu mencerminkan posisi politik-ekonomi China yang kian percaya diri. Negeri itu tidak lagi berdiri sebagai negara berkembang pencari konsesi, melainkan sebagai kekuatan penuh yang menolak tunduk pada logika unilateralisme ala Washington.
Retorika Keras, Dunia yang Renta dan WTO: Masih Relevan?
Peta ekonomi global hari ini jauh berbeda dari satu dekade lalu. Pandemi, konflik geopolitik, dan perubahan iklim telah menjadikan ekonomi global rapuh. Dalam konteks seperti ini, penggunaan tarif sebagai senjata justru memperbesar ketidakpastian.
Alih-alih menjadi solusi, tarif justru menciptakan ketegangan lanjutan, terutama di kawasan yang bergantung pada ekspor-impor seperti Asia Tenggara. Menurut Henry Gao, profesor hukum perdagangan internasional di Singapore Management University, “China telah membangun ekosistem perdagangan alternatif melalui Belt and Road Initiative dan memperkuat pasar domestik Asia.” (South China Morning Post, 6 April 2025).
Di sisi lain, AS terlihat menarik diri dari multilateralisme, memilih jalan proteksionisme. Ini berpotensi mendelegitimasi forum seperti World Trade Organization (WTO) yang selama ini menjadi garda penyelesaian sengketa dagang.
Krisis kepercayaan terhadap WTO makin menganga setelah AS menolak mengangkat hakim di Badan Banding WTO. Akibatnya, mekanisme penyelesaian sengketa menjadi timpang. “WTO makin tidak mampu menjawab kebutuhan negara anggota dalam menyelesaikan konflik tarif yang kian kompleks,” ujar ekonom dan mantan Menteri Perdagangan, Mari Elka Pangestu, kepada The Jakarta Post (9 April 2025).
Pasal XXIII GATT sejatinya mengatur bahwa penyelesaian sengketa dagang dilakukan secara adil melalui perundingan atau adjudikasi. Namun saat dua negara besar menolak tunduk pada aturan yang sama, maka ketegangan berubah menjadi kompetisi kekuasaan ekonomi. Aturan ditarik-ulur, hukum internasional menjadi subordinat dari strategi geopolitik.
Indonesia dan negara berkembang lainnya terdampak secara tidak langsung. Melemahnya nilai tukar rupiah, kenaikan harga bahan baku, dan gangguan ekspor adalah konsekuensi logis dari konflik tarif global. Ketergantungan pada pasokan bahan baku dari China serta orientasi ekspor ke pasar AS menjadi titik rawan.
ASEAN seharusnya bersatu merespons. Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP) menjadi platform penting untuk menata ulang posisi tawar kawasan dalam menghadapi dua raksasa ekonomi dunia. Sayangnya, hingga kini, ASEAN masih cenderung reaktif ketimbang proaktif.
China terlihat mengusung semangat nasionalisme ekonomi. Namun, ini bukan nasionalisme tertutup. China justru memperluas pengaruhnya melalui investasi global dan penguasaan teknologi strategis. Xi Jinping dalam pidatonya di Forum Ekonomi Boao menegaskan: “Tidak ada satu negara pun yang berhak menghambat jalan modernisasi kami.” (Xinhua, 4 April 2025).
China menanam investasi di Afrika, Asia Tengah, hingga Amerika Latin, membangun jaringan pasokan global yang tahan guncangan tarif. Sementara itu, AS tampak sibuk menutup diri dari ancaman luar, dengan argumen melindungi sektor domestik. Padahal dalam ekonomi terbuka, keterhubungan antar-negara justru menjadi penyangga stabilitas.
Indonesia tidak boleh hanya menjadi penonton atau korban. Diperlukan strategi perdagangan yang tangguh: mulai dari penyusunan ulang rantai pasok, penajaman arah diplomasi dagang, hingga penyelarasan hukum perdagangan luar negeri.
Menteri Perdagangan RI semestinya tampil aktif mendorong kerja sama dengan negara-negara di luar orbit AS-China, seperti India, Uni Eropa, hingga Timur Tengah. Di sisi domestik, peningkatan kapasitas produksi nasional harus dibarengi dengan reformasi sistem logistik dan insentif ekspor.
Netralitas dalam geopolitik bukan berarti diam. Netralitas yang tak disertai strategi akan berujung pada ketertinggalan. Sebagai anggota G20, Indonesia memiliki posisi untuk menyuarakan pentingnya kepatuhan terhadap hukum dagang internasional dan penghormatan terhadap mekanisme multilateral.
Pada akhirnya tarif dagang, jika disalahgunakan, tidak ubahnya senjata pemaksa. Di balik dalih melindungi kepentingan nasional, sesungguhnya ada bentuk kekerasan ekonomi yang dilegalkan. Dampaknya bisa melampaui sektor perdagangan: memperlebar ketimpangan, menimbulkan ketidakstabilan sosial, hingga mengganggu ekosistem produksi global.
Indonesia harus menolak logika kekerasan ini. Kita butuh keberanian untuk bersuara, kecermatan dalam membaca arah dunia, dan keteguhan untuk tetap berpijak pada prinsip keadilan dalam perdagangan.
Seperti diingatkan oleh Mochtar Kusumatmadja: hukum adalah alat rekayasa sosial. Maka hukum perdagangan internasional sekalipun di tengah turbulensi perang tarif masih bisa dan harus diperjuangkan sebagai alat untuk menjamin keadilan global.

 Desi Sommaliagustina
Desi Sommaliagustina