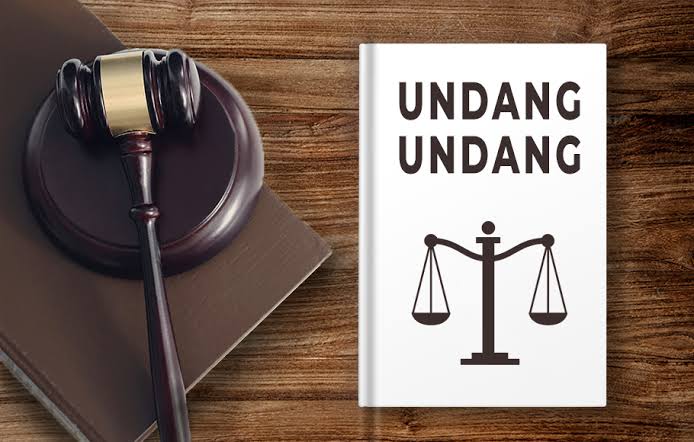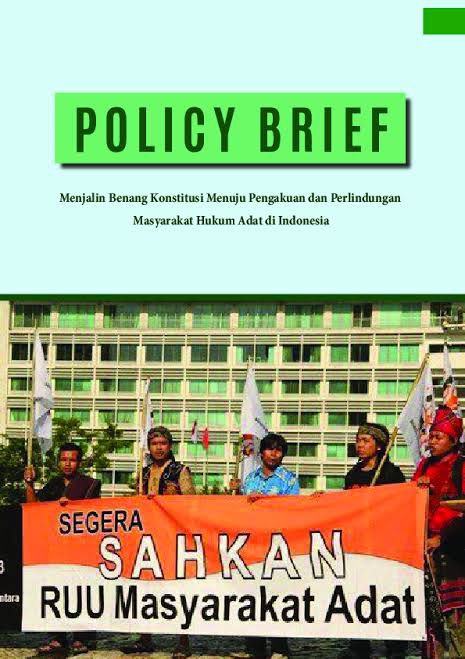Gelombang protes besar-besaran di Kabupaten Pati pada 13 Agustus 2025 menandai sebuah babak baru dalam hubungan antara rakyat dan pemimpinnya. Tuntutan “Bupati Sudewo Mundur” bukanlah seruan emosional sesaat. Ia lahir dari akumulasi kekecewaan yang membentuk gunung es ketidakpercayaan, dengan puncaknya adalah kebijakan kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) hingga 250 persen, angka yang mencengangkan dan belum pernah terjadi sebelumnya di Pati.
Kebijakan ini tidak disampaikan dengan komunikasi publik yang matang, apalagi kajian dampak sosial. Dalam kondisi ekonomi rakyat yang masih terseok pasca-pandemi dan di tengah kenaikan harga kebutuhan pokok, keputusan itu dirasa sebagai bentuk pajak kezaliman. Pajak, yang seharusnya menjadi instrumen keadilan fiskal, berubah menjadi beban pemiskinan struktural.
Namun, protes rakyat tidak berhenti pada soal pajak. Kekecewaan mereka merentang dari kebijakan pendidikan lima hari sekolah, renovasi Alun-Alun senilai miliaran rupiah, pembangunan videotron yang dianggap mubazir, hingga pemecatan pegawai RSUD Pati tanpa pesangon. Semua itu membentuk narasi ketidakpekaan terhadap penderitaan rakyat.
Politik Sensasi dan “Goyang Erotis” hingga Korupsi DJKA
Puncak ironi dari daftar panjang kontroversi ini adalah terselipnya acara hiburan yang dilabeli publik sebagai “goyang erotis” dalam agenda resmi. Bagi sebagian orang, ini mungkin hanya hiburan. Namun, dalam perspektif etika jabatan publik, ini adalah sinyal serius: ketika prioritas pemimpin bergeser dari substansi ke sensasi. Di tengah rakyat yang gelisah, menghadirkan tontonan vulgar sama saja mengirim pesan bahwa kemiskinan dan keresahan hanyalah latar panggung bagi politik citra.
Seolah tak cukup dengan kontroversi di level kebijakan daerah, kini muncul kembali dosa lama Sudewo. Ia dikaitkan dengan dugaan korupsi proyek Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) saat masih menjadi anggota Komisi V DPR RI. KPK telah mengantongi bukti berupa uang tunai miliaran rupiah yang disita dari rumahnya. Walaupun proses hukum belum memutuskan bersalah, fakta bahwa bayang-bayang ini kembali muncul di tengah krisis legitimasi adalah pukulan telak bagi citra kepemimpinan.
Kasus ini juga mengingatkan bahwa integritas seorang kepala daerah tidak bisa diukur hanya dari kinerjanya di daerah. Jejak rekam nasional ikut menentukan moral politiknya. Jika tuduhan ini terbukti, publik berhak menilai bahwa krisis di Pati bukan sekadar hasil salah urus kebijakan, tetapi juga buah dari kepemimpinan yang cacat secara etis sejak awal.
DPRD dan Hak Angket: Instrumen Demokrasi Lokal
Respon politik pun menguat. DPRD Pati telah mengaktifkan hak angket untuk menginvestigasi kebijakan-kebijakan Sudewo. Langkah ini patut diapresiasi, karena menjadi bukti bahwa mekanisme kontrol dalam otonomi daerah masih berjalan. Hak angket bukan sekadar prosedur; ia adalah instrumen demokrasi yang memastikan kekuasaan tidak melenceng tanpa koreksi.
Namun, publik harus waspada. Hak angket sering kali berujung pada kompromi politik yang tidak transparan. Di sinilah tekanan rakyat harus terus dipelihara agar DPRD tidak menjadikan angket sekadar alat tawar-menawar, tetapi sebagai langkah penegakan akuntabilitas yang sesungguhnya.
Kasus Pati ini memperlihatkan dua hal penting. Pertama, otonomi daerah tidak otomatis menghasilkan kepemimpinan yang dekat dengan rakyat. Tanpa integritas dan komitmen pelayanan publik, otonomi justru bisa berubah menjadi panggung kepentingan pribadi. Kedua, relasi antara pusat dan daerah menjadi rapuh ketika kepala daerah membawa beban kasus hukum dari masa lalu.
Fenomena ini mengingatkan kita pada teori moral hazard dalam politik. Ketika seorang pejabat pernah terlibat dalam pusaran dugaan korupsi, kecenderungan untuk mengulang perilaku serupa tetap tinggi, terutama jika tidak ada sanksi yang tegas. Publik Pati kini membayar harga dari kelalaian sistem seleksi politik yang lebih mengutamakan popularitas dan jaringan kekuasaan ketimbang rekam jejak integritas.
Jalan Pulang: Transparansi dan Penegakan Hukum
Jika Sudewo ingin menyelamatkan sisa masa jabatannya, dua langkah harus dilakukan. Pertama, meninjau ulang kebijakan-kebijakan kontroversial khususnya soal pajak melalui dialog publik yang jujur. Kedua, bersikap terbuka terhadap proses hukum DJKA dan tidak menggunakan jabatan bupati sebagai tameng.
Namun, jika dua langkah itu pun diabaikan, maka jalan paling terhormat adalah mengundurkan diri. Demokrasi tidak akan sehat jika kepala daerah terus bertahan hanya demi kekuasaan, sementara rakyat telah kehilangan kepercayaan.
Bupati Pati Sudewo kini berada di persimpangan sejarah politiknya. Ia bisa memilih menjadi pemimpin yang berani mereformasi diri, atau tetap bertahan di jalan kontroversi hingga terlempar oleh tekanan rakyat dan hukum. Apa pun pilihannya, pelajaran untuk kita semua jelas: demokrasi lokal hanya akan berarti jika rakyat terus mengawasi, dan hukum benar-benar ditegakkan tanpa pandang bulu.

 Desi Sommaliagustina
Desi Sommaliagustina