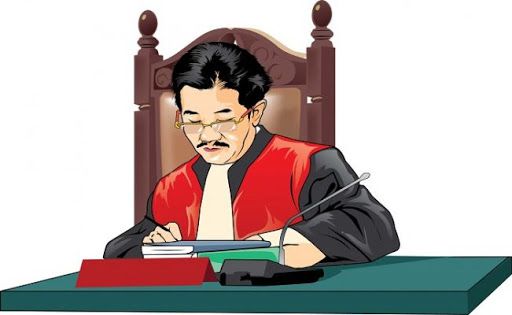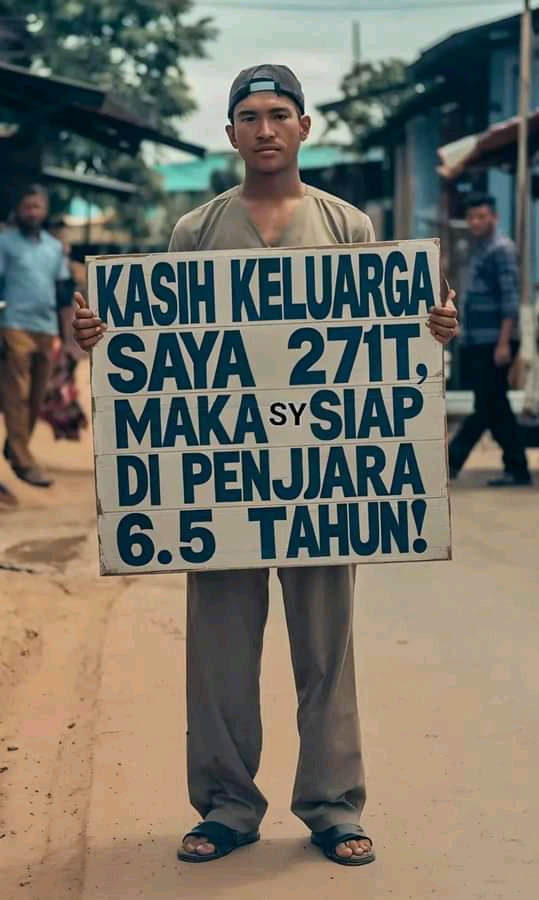Presiden Prabowo Subianto baru saja mengumumkan daftar tokoh yang akan mewakili Indonesia dalam menghadiri pemakaman Paus Fransiskus di Vatikan. Di antara nama-nama itu, tercantum tokoh yang tak bisa dianggap biasa: Presiden ke-7 Republik Indonesia, Joko Widodo. Bersama dia, turut pula Wakil Menteri Keuangan Thomas Djiwandono, Ignasius Jonan, dan Natalius Pigai.
Pernyataan resmi dari Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyebutkan bahwa ini adalah keputusan Presiden Prabowo “atas nama pemerintah Indonesia”. Publik tentu tak bisa begitu saja menelan fakta ini sebagai sekadar urusan protokoler.
Dalam politik, simbolisme adalah segalanya. Dan dalam kasus ini, simbol itu terlalu terang untuk tidak dilihat: mantan presiden, yang sebelumnya digambarkan sudah menepi, justru diberi peran utama dalam panggung internasional yang penuh sorotan. Masihkah kita ingin menyangkal adanya dua matahari dalam konstelasi kekuasaan Indonesia hari ini?
Istilah “matahari kembar” pernah bergema di era Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) kala Megawati Soekarnoputri, meski sudah tidak menjabat sebagai presiden, tetap memiliki pengaruh besar terhadap arah kebijakan, terutama melalui Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Konstelasi saat ini terasa lebih kompleks. Jokowi bukan hanya mantan presiden, melainkan juga arsitek kemenangan Prabowo dalam Pemilu 2024, dan masih menjadi pusat loyalitas publik dalam skala masif.
Sebagaimana dinyatakan oleh Bivitri Susanti, “ketika mantan presiden diberi panggung oleh presiden yang sedang menjabat, itu bukan semata etika, tapi konfigurasi kekuasaan yang masih dinegosiasikan.”
Dengan menunjuk Jokowi sebagai kepala utusan, Presiden Prabowo tampaknya tidak hanya memberi penghargaan kepada pendahulunya, tapi juga mau tak mau mengakui bahwa pengaruh politik Jokowi masih diperlukan. Apakah ini bentuk resiprositas? Ataukah ini sinyal bahwa Prabowo belum merasa sepenuhnya memegang kendali tunggal?
Pengiriman utusan ke acara pemakaman pemimpin tertinggi Gereja Katolik sedunia bukanlah urusan administratif biasa. Ia merupakan bagian dari diplomasi simbolik yang sarat makna. Dalam hubungan internasional, peristiwa seperti ini menjadi ajang untuk menunjukkan siapa yang dihormati, siapa yang dipercaya, dan siapa yang masih memegang pengaruh.
Sebagaimana dikatakan oleh Joseph Nye dalam kerangka soft power, “diplomacy is the art of letting someone else have your way”. Dalam konteks ini, pengutusan Jokowi adalah seni menyampaikan pesan diplomatik dalam diam. Pesan bahwa Indonesia menghormati Vatikan, namun juga pesan domestik: bahwa Jokowi masih dianggap wajah resmi yang kredibel dalam mewakili bangsa di panggung dunia. Dan itu artinya: Jokowi belum benar-benar pensiun dari pentas kekuasaan.
Langkah ini bisa dibaca sebagai bentuk rekonsiliasi sosial politik yang inklusif. Namun, publik tentu bertanya: apakah ini bagian dari kebijakan afirmatif substansial atau sekadar gestur simbolik? Jika benar ingin mendorong pluralisme, seharusnya langkah serupa juga diterapkan dalam pengambilan kebijakan di dalam negeri, bukan sekadar ketika hendak tampil di panggung luar negeri.
Secara hukum, pengutusan mantan presiden dalam delegasi resmi tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Bahkan dalam Pasal 13 Undang-Undang No. 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri disebutkan bahwa “Presiden dapat menunjuk wakil untuk melaksanakan tugas tertentu dalam hubungan luar negeri atas nama negara.” Dalam tradisi diplomatik, utusan untuk acara kenegaraan dengan muatan religius seperti ini biasanya melibatkan figur resmi yang menjabat atau, jika tidak, figur yang secara etiket masih merepresentasikan kekuasaan penuh.
Ketika Presiden yang sedang menjabat menunjuk pendahulunya sebagai kepala delegasi, maka yang terjadi bukan hanya praktik protokoler, tapi juga manuver politik. Ia mengaburkan batas antara status resmi dan kekuatan informal. Sebagaimana dicatat oleh Hikmahanto Juwana, “politik luar negeri Indonesia sering kali menjadi perpanjangan dari narasi dalam negeri. Siapa yang dikirim ke luar negeri adalah refleksi siapa yang dipercaya oleh dalam negeri.”
Menarik untuk mencermati bagaimana Indonesia memperlakukan para mantan pemimpinnya. Dalam sejarah republik ini, tak semua mantan presiden mendapat ruang kehormatan serupa. Soeharto, misalnya, meski berkuasa selama tiga dekade, tersingkir dalam diam. B.J. Habibie dihormati, tetapi jarang diberi tugas kenegaraan oleh penerusnya. Megawati lebih sering berfungsi sebagai figur partai daripada utusan negara. Hanya Jokowi yang diberi panggung kenegaraan pasca-jabatan dalam skala global seperti ini.
Ini memperkuat narasi bahwa Jokowi bukan sekadar mantan presiden. Ia adalah arsitek transisi kekuasaan. Ia adalah matahari yang belum padam. Dan, oleh karena itu, tak bisa diabaikan dalam peta kekuasaan nasional maupun internasional.
Publik tentu bebas menafsirkan langkah Prabowo ini dari berbagai sudut pandang. Ada yang melihatnya sebagai bentuk penghormatan politik yang elegan. Ada pula yang menilainya sebagai manuver diplomatik yang cerdas. Tak sedikit yang membaca ini sebagai isyarat bahwa kekuasaan di Indonesia masih terbagi dalam dua kutub.
Kita boleh menyebut ini penghormatan. Tapi jangan salah paham. Ini juga pengakuan. Pengakuan bahwa dalam tata surya politik Indonesia hari ini, satu matahari belum cukup. Dan meskipun hanya satu yang duduk di kursi RI-1, sinar yang lain tetap menyinari langit politik, entah dari depan layar, atau dari balik bayang-bayang Istana.

 Desi Sommaliagustina
Desi Sommaliagustina