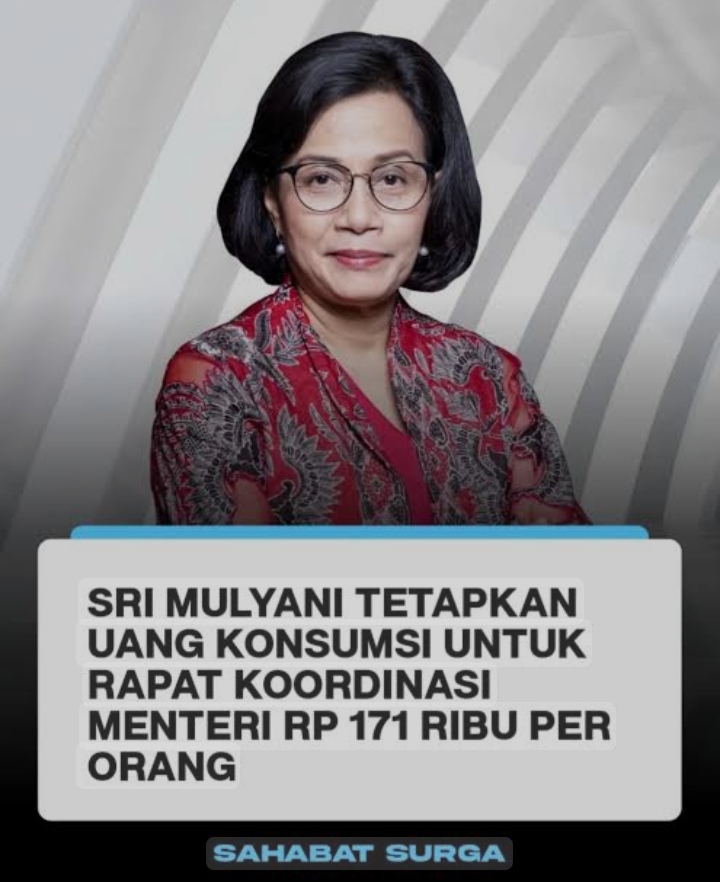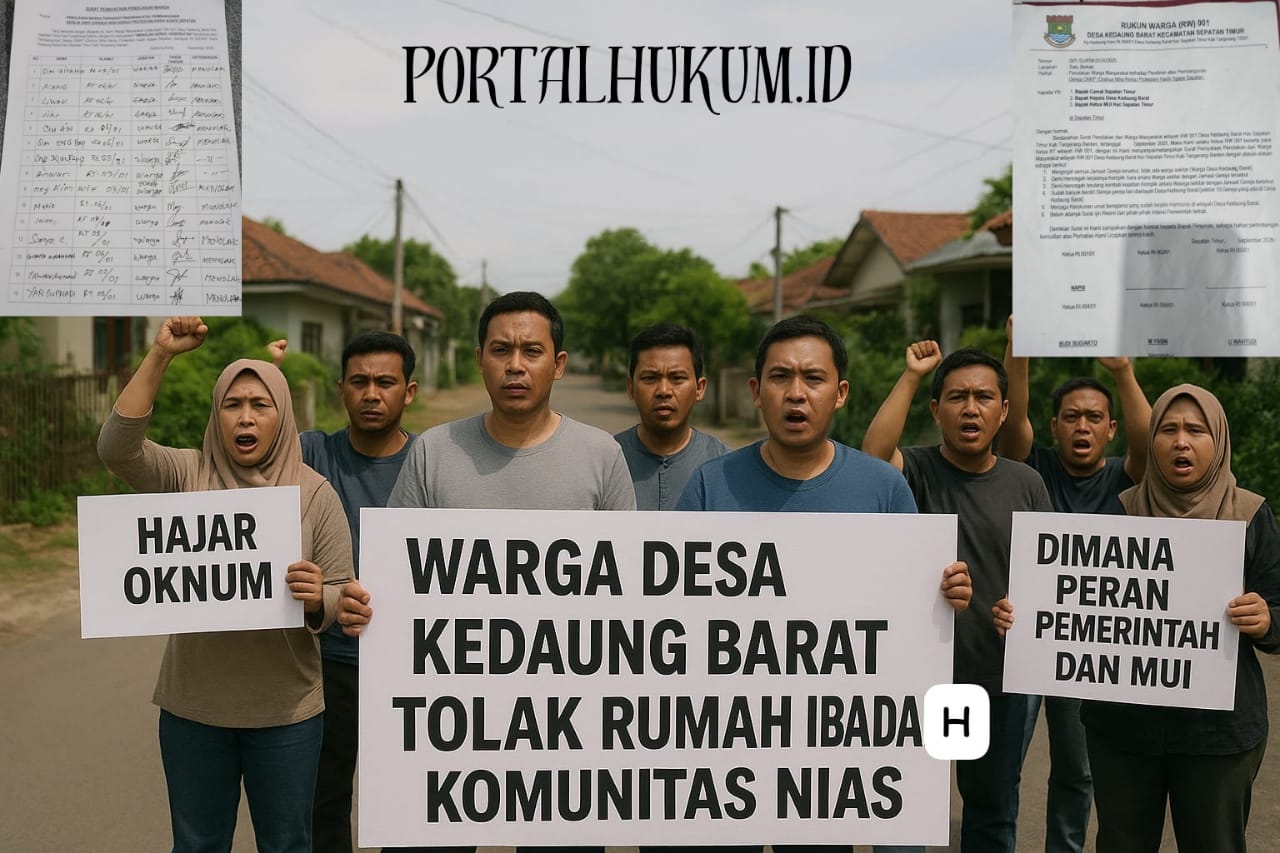Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) baru-baru ini menyerahkan berkas usulan 40 nama calon pahlawan nasional kepada Menteri Kebudayaan, yang juga Ketua Dewan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan. Dari sekian nama itu, dua sosok langsung mengundang perdebatan publik: Marsinah, buruh perempuan yang dibunuh karena memperjuangkan keadilan upah, dan Soeharto, Presiden ke-2 Republik Indonesia yang berkuasa selama lebih dari tiga dekade.
Keduanya sama-sama tercatat dalam sejarah bangsa, tetapi berada di dua kutub yang berlawanan. Marsinah adalah suara dari bawah yang menuntut hak; Soeharto adalah simbol kekuasaan dari atas yang membungkam hak itu.
Menempatkan mereka dalam satu daftar penghargaan adalah bentuk kebingungan moral negara — seperti menyejajarkan korban dan penguasa dalam altar yang sama.
Jejak Luka dan Kuasa
Soeharto bukan nama kecil dalam sejarah Indonesia. Ia dianggap sebagai arsitek stabilitas politik dan pertumbuhan ekonomi di era Orde Baru. Tetapi di balik gemerlap pembangunan dan slogan “stabilitas nasional”, ada deretan luka yang belum disembuhkan: pembatasan kebebasan berpendapat, korupsi, kolusi, nepotisme, serta pelanggaran hak asasi manusia di berbagai daerah.
Laporan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM, 1998) menyebutkan sederet peristiwa kelam yang terjadi di bawah kekuasaannya: penembakan misterius (Petrus), Tanjung Priok 1984, Talangsari 1989, Timor-Timor 1991, hingga penculikan aktivis menjelang kejatuhan Orde Baru. Semua itu menunjukkan pola kekuasaan yang menekan, bukan memerdekakan.
Dalam situasi seperti ini, mengusulkan Soeharto sebagai pahlawan nasional bukanlah penghormatan terhadap sejarah, tetapi penghinaan terhadap mereka yang menjadi korban kekuasaannya.
Di sisi lain, Marsinah tidak punya pangkat, partai, atau jabatan. Ia hanyalah seorang buruh perempuan di PT Catur Putra Surya, Porong, Sidoarjo, yang memperjuangkan hak upah layak bagi rekan-rekannya pada Mei 1993.
Setelah memimpin aksi mogok kerja, Marsinah hilang. Tiga hari kemudian, jasadnya ditemukan di sebuah gubuk di Nganjuk — penuh luka dan tanda penyiksaan.
Penyelidikan polisi saat itu tidak pernah benar-benar menyingkap kebenaran. Delapan orang ditetapkan sebagai terdakwa, namun kemudian dibebaskan karena terbukti tidak bersalah. Kasus Marsinah pun terkubur bersama rezim yang menindasnya.
Namun bagi gerakan buruh, nama Marsinah hidup selamanya. Ia adalah simbol perlawanan terhadap ketidakadilan, dan bukti bahwa suara kecil pun bisa mengguncang struktur besar ketimpangan. Human Rights Watch (1994) bahkan menyebut kasus Marsinah sebagai potret telanjang represi negara terhadap kebebasan berserikat di Indonesia.
Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2010 tentang Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan menyatakan bahwa pahlawan nasional adalah mereka yang berjasa luar biasa bagi bangsa dan tidak pernah melakukan perbuatan yang menodai nilai kemanusiaan.
Jika kriteria itu dijadikan patokan, maka Marsinah jelas memenuhi syarat moral kepahlawanan. Ia berjuang tanpa pamrih, mengorbankan diri demi keadilan sosial bagi sesama buruh. Ia tidak pernah mengkhianati rakyat.
Sebaliknya, Soeharto, dengan segala pelanggaran yang belum terselesaikan, sulit dilepaskan dari bayang-bayang penodaan terhadap nilai kemanusiaan itu sendiri.
Bangsa ini seolah lupa bahwa kepahlawanan bukan soal kekuasaan, tetapi soal keberanian menegakkan kebenaran.
Politik Ingatan yang Terbalik
Fenomena nostalgia terhadap masa Orde Baru kerap muncul dalam bentuk ucapan, “Zaman Pak Harto enak, semua murah dan aman.” Kalimat ini menunjukkan betapa pendeknya ingatan kolektif bangsa. Kita mudah mengingat harga beras, tetapi melupakan harga kebebasan. Kita mengagungkan stabilitas, tapi menutup mata terhadap represi.
Sementara Marsinah, simbol keberanian rakyat kecil, tenggelam dalam senyap. Tidak ada hari nasional untuk mengenangnya, tidak ada patung atau jalan besar yang memakai namanya. Ia hanya hidup dalam ingatan buruh dan aktivis yang masih percaya bahwa keadilan bukanlah mitos.
Inilah bentuk politik ingatan yang terbalik — ketika bangsa lebih mudah memaafkan kekuasaan daripada mengakui penderitaan korban. Kepahlawanan sejati seharusnya berpihak pada sila kelima Pancasila: Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Marsinah memperjuangkan keadilan itu dalam bentuk paling konkret — menuntut hak upah layak, hak yang dijamin oleh Undang-Undang Ketenagakerjaan dan prinsip kemanusiaan universal.
Ia tidak melawan negara, tetapi memperjuangkan agar negara hadir untuk rakyatnya. Karena itu, perjuangan Marsinah bukan hanya kisah buruh, tetapi kisah bangsa: tentang bagaimana kita memperlakukan suara yang lemah.
Marsinah adalah Kita
Ketika nama Marsinah dan Soeharto muncul bersamaan dalam daftar calon pahlawan nasional, yang sedang diuji bukanlah keduanya, tetapi nurani bangsa ini. Apakah kita akan menghargai keberanian moral, atau justru meromantisasi kekuasaan yang melahirkan korban?
Menjadikan Marsinah sebagai pahlawan nasional adalah langkah simbolik untuk mengakui sejarah rakyat kecil sebagai bagian sah dari perjalanan bangsa. Sebaliknya, mengangkat Soeharto akan menandakan bahwa negara masih enggan berdamai dengan kebenaran.
Marsinah bukan sekadar nama dalam sejarah perburuhan. Ia adalah cermin bagi seluruh rakyat Indonesia — bahwa perjuangan tidak harus berlabel politik, dan keberanian tidak memerlukan kekuasaan. Ia adalah wajah kejujuran di tengah korupsi moral penguasa. Ia mengingatkan kita bahwa kebebasan, kesejahteraan, dan keadilan tidak datang dari atas, tetapi diperjuangkan dari bawah.
Dan pada akhirnya, jika bangsa ini harus memilih siapa yang pantas diberi gelar pahlawan nasional, maka jawabannya bukan soal nostalgia, melainkan nurani. Karena pahlawan sejati tidak membungkam rakyat, tetapi menghidupkan suara mereka. Maka, sekali lagi: Marsinah, bukan Soeharto!

 Desi Sommaliagustina
Desi Sommaliagustina