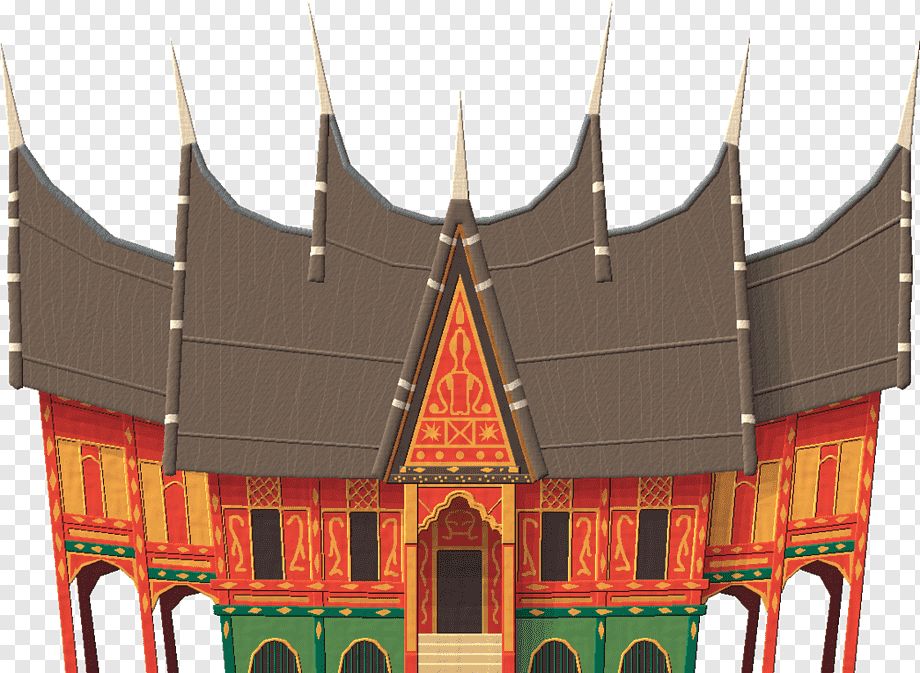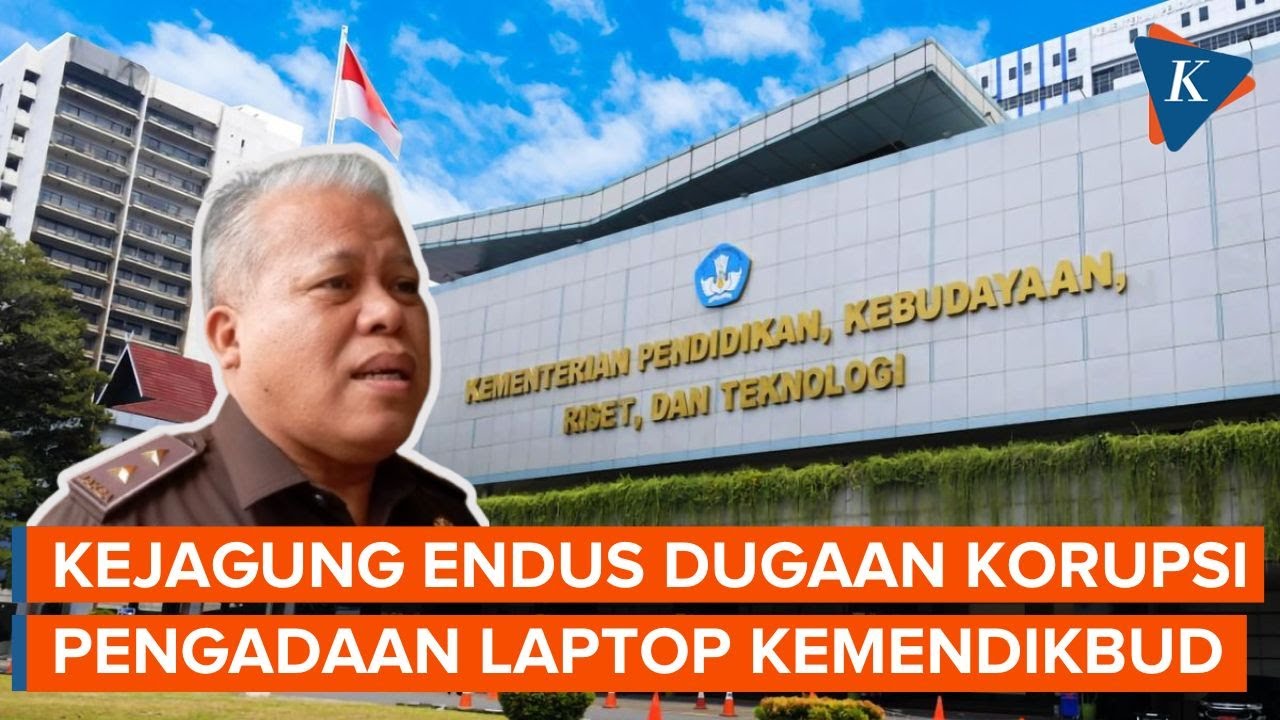Di Minangkabau, harta pusako bukan sekadar tanah atau rumah gadang. Ia adalah jantung kehidupan sosial, simbol kesinambungan adat, dan manifestasi ikatan kekerabatan matrilineal yang diwariskan turun-temurun. Filosofi adat yang termaktub dalam pepatah adat basandi syarak, syarak basandi Kitabullah mengajarkan bahwa harta pusako adalah harta kolektif, milik kaum, bukan milik pribadi.
Namun, realitas hari ini menunjukkan pergeseran yang mengkhawatirkan. Pusako yang dahulu menjadi perekat kaum, kini sering berubah menjadi obyek sengketa. Sawah ladang yang seharusnya tak tergoyahkan, kini bisa berpindah tangan lewat selembar sertifikat. Rumah gadang yang semestinya berdiri megah menjaga marwah kaum, kini banyak yang terbengkalai karena konflik pewarisan.
Apakah pusako masih pusako? Ataukah ia hanya tinggal nama, tanpa makna?
Dari Kolektif ke Individual
Dalam hukum adat Minangkabau, dikenal dua kategori pusako: pusako tinggi dan pusako rendah. Pusako tinggi adalah harta warisan turun-temurun dari nenek moyang, seperti sawah, ladang, dan rumah gadang. Statusnya tak boleh diperjualbelikan. Sedangkan pusako rendah adalah harta yang diperoleh dari hasil usaha pribadi seseorang, yang dapat diwariskan sesuai dengan hukum waris Islam.
Pembedaan ini menegaskan bahwa pusako tinggi adalah “harta sakral” yang menjadi milik kaum secara kolektif. Dalam prinsip adat, mamak hanya bertindak sebagai pengelola, bukan pemilik mutlak.
Namun, dalam praktiknya, nilai kolektif ini kian terkikis. Tekanan ekonomi, urbanisasi, dan penetrasi hukum nasional membuat pusako kehilangan kesakralannya. Banyak mamak atau kemenakan tergoda untuk menjual pusako tinggi dengan dalih kebutuhan hidup. Negara, melalui Badan Pertanahan Nasional (BPN), ikut mendorong individualisasi kepemilikan dengan menerbitkan sertifikat hak milik. Dari sinilah pusako mulai goyah, berubah menjadi obyek transaksi pasar.
Secara konstitusional, negara sebenarnya mengakui keberadaan hukum adat. Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 menegaskan bahwa “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup…”.
Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) 1960 pun membuka ruang bagi pengakuan tanah ulayat. Namun, dalam praktiknya, implementasi hukum agraria lebih berpihak pada kepastian hukum individual. Sertifikat tanah memiliki kekuatan hukum lebih dibanding klaim adat.
Akibatnya, pusako sering kali kalah di pengadilan. Dalam banyak kasus, hakim lebih mudah mengakui bukti berupa sertifikat resmi daripada keterangan adat. Di sinilah terjadi benturan tajam: adat memandang pusako sebagai milik kaum yang tak bisa dipindahtangankan, sementara hukum positif menganggap tanah yang bersertifikat sebagai milik sah pemegangnya.
Krisis Sosial: Sengketa yang Mengoyak Kaum
Fenomena ini melahirkan krisis sosial yang nyata. Sengketa pusako menjadi perkara yang menumpuk di pengadilan negeri Sumatera Barat. Data Pengadilan Tinggi Padang menunjukkan bahwa kasus sengketa tanah, termasuk pusako, menduduki peringkat tertinggi dari tahun ke tahun.
Konflik sering terjadi antar-kemenakan, antar-kaum, bahkan antar-suku. Tidak jarang, tanah pusako dijadikan jaminan hutang oleh mamak tanpa musyawarah. Ketika gagal membayar, tanah jatuh ke tangan orang luar. Kaum pun tercerai-berai.
Rumah gadang, simbol kebanggaan adat, banyak yang kosong dan lapuk. Kaum enggan merawat karena tidak ada lagi rasa memiliki bersama. Adat yang semestinya menjadi pagar sosial justru ditinggalkan. Fenomena ini disebut oleh para sosiolog sebagai atomisasi adat: dari ikatan komunal yang kuat menjadi individualisme yang rapuh.
Pepatah lama “basamo mangko manjadi, bakato mangko mufakat” kini bergeser menjadi “bakato mahukum bako, kamanakan mahukum kamanakan”.
Jika ditelisik lebih dalam, hilangnya pusako bukan sekadar soal tanah. Ia adalah pertarungan identitas Minangkabau di tengah modernisasi. Apakah orang Minang masih memegang teguh adat, ataukah mereka rela melepasnya demi kebutuhan praktis?
Dalam wawancara lapangan, banyak anak muda Minang yang menganggap pusako hanya sekadar “tanah keluarga” yang bisa dijual jika butuh uang. Mereka lebih mengenal konsep kepemilikan individual ala hukum nasional daripada prinsip kolektif adat.
Inilah tantangan besar. Jika pusako hilang, maka identitas matrilineal Minangkabau ikut pudar. Kaum akan kehilangan ikatan sosialnya. Adat yang selama ini menjadi tameng, tinggal sebatas romantisme sejarah.
Lalu, apa yang bisa dilakukan? Haruskah adat menyerah pada hukum positif? Ataukah hukum positif yang harus tunduk pada adat?
Menurut hemat saya, jalan tengah harus ditempuh. Adat tidak boleh ditinggalkan, tetapi juga tidak bisa dipertahankan secara kaku. Diperlukan reformulasi agar pusako tetap hidup di era modern.
Beberapa langkah konkret bisa ditempuh: pertama, penguatan regulasi daerah. Pemerintah daerah Sumatera Barat perlu melahirkan Peraturan Daerah (Perda) yang secara tegas melindungi tanah ulayat dan pusako tinggi. Pengakuan normatif dalam UUPA harus diturunkan ke level implementasi lokal.
Kedua, pengelolaan kolektif modern. Pusako bisa dikelola seperti koperasi kaum. Tanah tidak dijual, tetapi hasilnya dimanfaatkan bersama untuk pendidikan, kesehatan, atau kebutuhan ekonomi anggota kaum.
Ketiga, edukasi generasi muda. Anak muda Minang perlu diberi pemahaman bahwa pusako adalah identitas, bukan sekadar aset ekonomi. Kurikulum lokal bisa memasukkan materi tentang hukum adat dan pusako.
Keempat, sinkronisasi hukum adat dan hukum nasional. Pengadilan harus memberi ruang lebih besar pada nilai-nilai adat dalam menyelesaikan sengketa pusako. Hakim tidak hanya berpatokan pada sertifikat, tetapi juga harus mempertimbangkan fakta sosial dan adat.
Saat ini dimana posisi harta Pusako? Harta pusako di ranah Minang kini berada di ujung tanduk. Jika tidak segera dijaga, pusako akan benar-benar hilang, bukan hanya sebagai tanah atau rumah gadang, tetapi juga sebagai roh kebersamaan Minangkabau.
Adat Minang selalu hidup dalam pepatah. Salah satunya berbunyi: “Pusako tinggi indak dapek dimakan api, indak lapuak dek hujan.” Namun pepatah itu kini dipertanyakan. Api individualisme dan hujan kapitalisme mampu melapukkan pusako.
Dalam hukum dikenal adagium ubi societas ibi ius, di mana ada masyarakat, di situ ada hukum. Jika masyarakat Minangkabau masih ingin mempertahankan jati dirinya, maka hukum pusako harus dijaga, diperkuat, dan diadaptasi dengan zaman. Jika tidak, pusako tinggal legenda. Rumah gadang tinggal cerita. Dan ranah Minang kehilangan denyutnya.

 Desi Sommaliagustina
Desi Sommaliagustina