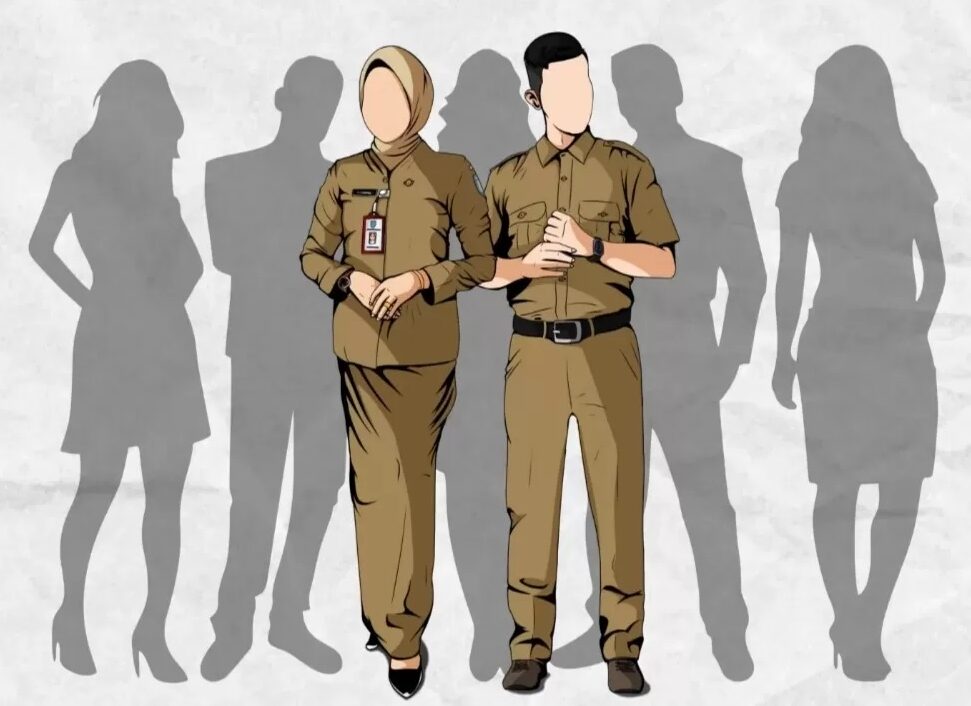Dalam pidato-pidato resminya belakangan ini, Presiden Prabowo Subianto menyampaikan keyakinan optimistis: “Hampir semua lembaga meramalkan ekonomi Indonesia akan masuk lima besar dunia.” Pernyataan ini sontak menjadi sorotan. Bagi sebagian, ini menjadi sumber harapan. Bagi sebagian lainnya, termasuk kalangan akademisi dan praktisi kebijakan, ini justru menimbulkan kekhawatiran akan lahirnya narasi pembangunan yang jauh dari realitas sosial-ekonomi masyarakat.
Tidak ada yang keliru dengan harapan akan masa depan cerah. Namun, mengutip optimisme tanpa data kontekstual, tanpa menjelaskan prasyarat struktural, justru bisa menyesatkan. Jika Indonesia benar akan masuk 5 besar ekonomi dunia, pertanyaannya: berdasarkan indikator apa? Dalam jangka waktu berapa lama? Apa asumsi yang digunakan?
Lembaga seperti IMF dan PwC memang pernah memproyeksikan Indonesia sebagai bagian dari ekonomi terbesar dunia berdasarkan PDB PPP (Purchasing Power Parity), bukan PDB nominal. Namun, peringkat ini bersifat proyeksi jangka panjang, bukan kepastian, dan sangat tergantung pada reformasi struktural yang dalam: pendidikan, reformasi birokrasi, perlindungan hukum, pemberantasan korupsi, dan redistribusi kesejahteraan.
Mengklaim Indonesia akan masuk 5 besar ekonomi dunia terasa ganjil saat kita berhadapan dengan realitas: harga pangan melonjak, daya beli stagnan, ketimpangan antarwilayah masih mencolok, dan indeks kualitas pendidikan rendah. Data BPS menunjukkan bahwa angka kemiskinan ekstrem masih menyentuh jutaan jiwa. Dunia pendidikan kita terjebak dalam birokratisasi dan komersialisasi yang membunuh kreativitas dan akses.
Apa arti menjadi “ekonomi terbesar” jika rakyat masih tercekik oleh utang konsumtif, lapangan kerja informal merajalela, dan harga beras terus melambung?
Pertumbuhan ekonomi Indonesia saat ini—meski stabil di angka 5%—terjadi dalam konteks kenaikan utang luar negeri dan pembengkakan belanja negara. Data Kementerian Keuangan menunjukkan total utang pemerintah per April 2025 telah menembus lebih dari Rp8.000 triliun. Jika pertumbuhan ekonomi dibangun di atas fondasi utang, maka kita sebetulnya sedang menulis mimpi di atas kertas kosong.
Tak hanya itu, sebagian besar pertumbuhan masih terkonsentrasi pada sektor ekstraktif, seperti batu bara dan kelapa sawit. Ketahanan ekonomi semacam ini sangat rentan terhadap fluktuasi harga global dan tekanan geopolitik internasional.
Laporan Bank Dunia dan OECD mengindikasikan bahwa meskipun PDB Indonesia tumbuh, indeks Gini dan ketimpangan antarwilayah belum banyak berubah. Jakarta dan sekitarnya terus tumbuh, sementara Papua, NTT, dan sebagian wilayah Kalimantan tertinggal jauh.
Apakah pembangunan yang menomorsatukan megaproyek dan infrastruktur tanpa peningkatan kualitas hidup rakyat layak disebut “menuju 5 besar dunia”? Jika pembangunan tidak inklusif, maka sesungguhnya itu adalah pertumbuhan yang menindas.
Pernyataan bombastis tentang masa depan ekonomi cenderung menciptakan narasi populisme ekonomi yang menutupi persoalan struktural. Publik dipaksa percaya bahwa Indonesia hebat dan sedang menuju kejayaan, sementara di lapangan, petani gagal panen karena pupuk langka, nelayan kehilangan akses laut karena ekspansi tambang, dan mahasiswa tak mampu membayar UKT.
Populisme semacam ini berbahaya karena menjauhkan negara dari kritik dan evaluasi. Ketika pemimpin mulai lebih suka memproduksi mimpi daripada menyelesaikan masalah, maka publik kehilangan arah untuk melakukan kontrol terhadap kekuasaan.
Indonesia bisa saja masuk 5 besar ekonomi dunia, tetapi dengan syarat: ada perombakan besar-besaran dalam tata kelola pemerintahan, pendidikan, dan sistem hukum. Tanpa itu, pernyataan Prabowo hanya akan menjadi retorika kosong di tengah penderitaan rakyat yang nyata.
Ekonomi bukan sekadar angka-angka yang dipublikasikan lembaga internasional. Ekonomi adalah tentang nasi di meja rakyat, pekerjaan yang layak, sekolah yang terjangkau, dan hidup yang bermartabat. Dan hari ini, kita belum ke sana!

 Desi Sommaliagustina
Desi Sommaliagustina