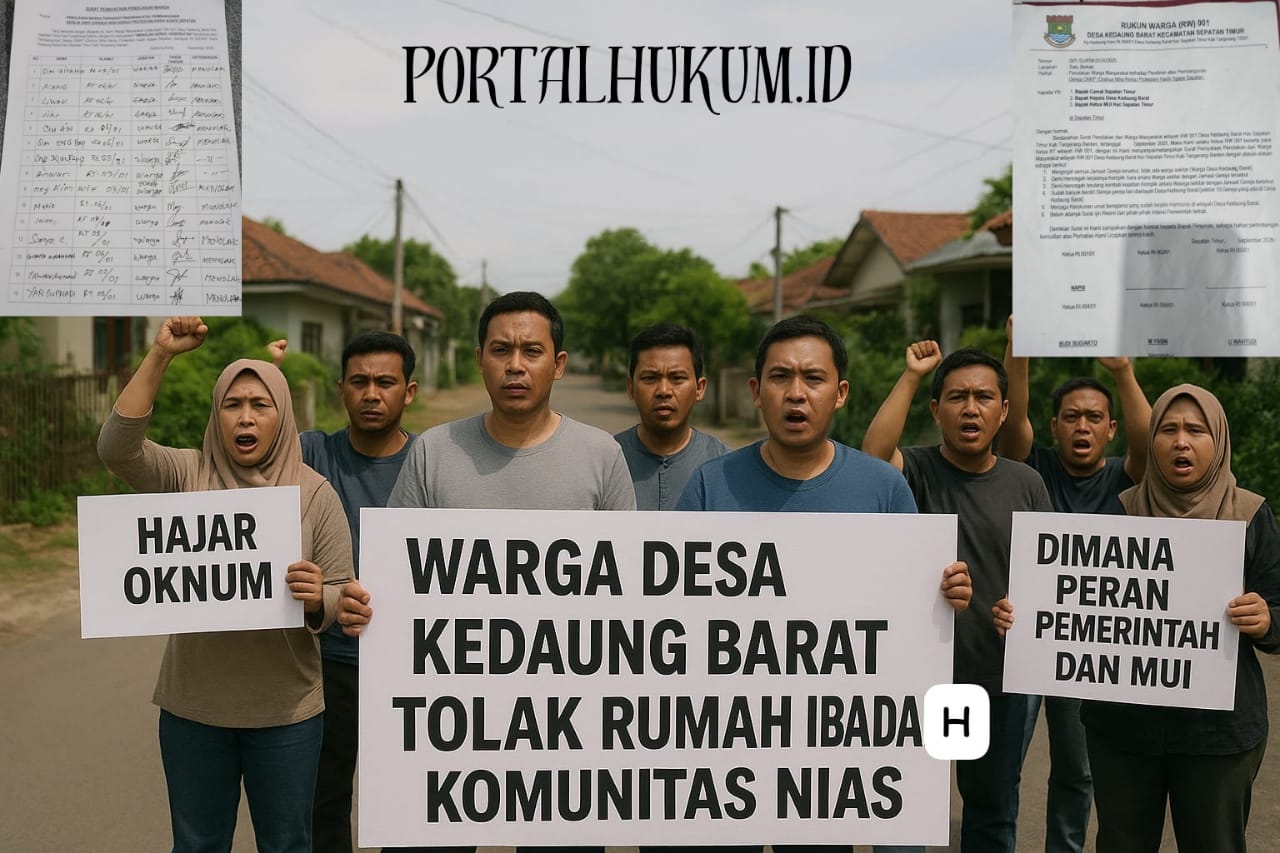Di negeri ini, gelar “Profesor” seolah menjadi simbol paling tinggi dari pencapaian intelektual. Ia bukan hanya penanda keahlian akademik, tetapi juga lambang kehormatan sosial dan prestise birokratis. Namun, di balik kilau gelar itu, terselip kenyataan getir yang mencoreng dunia pendidikan tinggi:fenomena profesor tanpa integritas dan lebih parah lagi, praktik jual beli gelar akademik yang kini kian marak.
Gelar yang seharusnya diperoleh dengan dedikasi dan kejujuran ilmiah, kini bisa “diproduksi” melalui jalur cepat, bahkan dengan transaksi uang dan koneksi. Muncul profesor yang bukan karena karya ilmiahnya, melainkan karena kedekatan dengan pejabat kampus atau kekuatan finansial yang mampu membeli legitimasi akademik. Fenomena ini bukan sekadar persoalan etika, tetapi pelanggaran hukum dan pengkhianatan terhadap hakikat ilmu pengetahuan itu sendiri.
Profesor Tanpa Integritas
Menjadi profesor seharusnya berarti mencapai puncak keilmuan dan moralitas. Namun, kini banyak yang hanya mengejar gelar tanpa menegakkan nilai. Di sejumlah universitas negeri maupun swasta, publik dikejutkan dengan terkuaknya plagiarisme, manipulasi karya ilmiah, dan penyalahgunaan jabatan akademik. Beberapa kasus bahkan menunjukkan bahwa proses kenaikan jabatan fungsional dilakukan secara instan dengan publikasi di jurnal abal-abal atau laporan penelitian pesanan.
Padahal, Pasal 7 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi dengan jelas mewajibkan dosen untuk melaksanakan etika akademik dan bertanggung jawab atas hasil karyanya. Artinya, integritas ilmiah bukan pilihan moral, tetapi kewajiban hukum. Pelanggaran terhadap prinsip ini semestinya dapat berujung pada pencabutan jabatan akademik dan sanksi administratif yang tegas.
Namun kenyataannya, hukum pendidikan tinggi di Indonesia masih tumpul terhadap pelanggaran etik. Kampus lebih sibuk menjaga citra lembaga daripada menegakkan kejujuran ilmiah. Banyak pelanggaran diselesaikan secara internal dan diam-diam tanpa publikasi, tanpa sanksi yang berarti. Bahkan, tidak jarang pelaku justru dipromosikan ke posisi strategis.
Fenomena yang paling mencemaskan adalah munculnya praktik jual beli gelar akademik, termasuk gelar profesor kehormatan (honoris causa) yang diberikan tanpa landasan karya atau kontribusi ilmiah yang nyata. Beberapa perguruan tinggi negeri hingga swasta menjadikan gelar kehormatan sebagai alat promosi atau bahkan sumber pendapatan.
Sudah menjadi rahasia umum bahwa ada pihak-pihak yang mendapatkan gelar akademik atau profesor melalui jalur finansial. Di dunia maya, kita bahkan menemukan lembaga tidak resmi yang menawarkan “paket doktor dan profesor” dengan harga puluhan hingga ratusan juta rupiah. Prosesnya cepat, legalitasnya dipertanyakan, tetapi hasilnya: sertifikat dan toga kebesaran yang tampak sah di mata awam.
Fenomena ini mencederai hukum dan moral akademik secara serius. Permendikbudristek Nomor 92 Tahun 2014 tentang Guru Besar dan Jabatan Akademik Dosen telah menegaskan bahwa pengangkatan profesor harus melalui seleksi ketat berdasarkan karya ilmiah, pengalaman tridharma, dan pengabdian akademik. Artinya, setiap proses transaksional di luar mekanisme resmi merupakan pelanggaran hukum administrasi dan etik akademik.
Lebih jauh, praktik jual beli gelar dapat dikategorikan sebagai pemalsuan dokumen akademik yang melanggar Pasal 263 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tentang pemalsuan surat. Jika lembaga pendidikan terlibat dalam praktik tersebut, maka secara hukum, mereka turut serta dalam kejahatan yang menipu publik dan merusak tatanan keilmuan nasional.
Guru Besar Berpangkat, Tapi Tak Berjiwa
Gelar profesor seharusnya menjadi simbol tanggung jawab moral, bukan sekadar pangkat administratif. Namun, kini banyak “guru besar berpangkat” yang hanya sibuk mengamankan tunjangan profesi, mengejar posisi struktural, atau terlibat dalam proyek pemerintah. Mereka lebih sering tampil di acara seremoni daripada di forum akademik. Mereka lebih cepat menanggapi isu politik daripada memperjuangkan kebenaran ilmiah.
Ironisnya, ketika bangsa menghadapi persoalan hukum, ekonomi, dan moral yang rumit, suara profesor justru lenyap. Mereka memilih diam, padahal tanggung jawab moral keprofesoran adalah menyuarakan kebenaran meski melawan arus kekuasaan. Sebagaimana pernah dikatakan oleh ilmuwan Jerman Max Weber, “Ilmu tanpa tanggung jawab moral hanyalah alat kekuasaan.” Dan di Indonesia, alat kekuasaan itu kini kerap berseragam toga.
Akar persoalan tidak berhenti pada individu profesor yang korup moral, tetapi juga pada sistem yang gagal menegakkan etika akademik. Senat universitas dan dewan etik kampus sering kali tidak independen, bahkan melindungi pelaku. Banyak kasus plagiarisme atau suap jabatan akademik yang diredam karena pelakunya adalah orang dalam: dekan, rektor, anggota senat, atau pejabat struktural .
Kampus yang seharusnya menjadi tempat berpikir bebas dan jujur justru berubah menjadi arena politik internal yang transaksional. Maka tak heran, publik makin sinis terhadap gelar akademik. Banyak yang berkata sinis: “Profesor di Indonesia tak selalu pintar, tapi pasti berpengaruh.”
Sementara itu, Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi (Kemdikti Saintek) belum memiliki sistem pengawasan etik nasional yang kuat. Lembaga seperti Komite Etik Penelitian dan Akademik Nasional masih bersifat administratif, bukan investigatif. Padahal, di banyak negara, seperti Inggris atau Australia, pelanggaran etik akademik dapat berujung pada pencabutan gelar secara permanen dan publikasi resmi atas pelanggaran tersebut.
Sudah saatnya pemerintah memperkuat aspek hukum dalam dunia akademik. Ada tiga langkah penting yang perlu segera dilakukan: Pertama, mendirikan Badan Etik Akademik Nasional yang independen dan memiliki kewenangan hukum untuk memeriksa serta memberi sanksi terhadap pelanggaran etik akademik lintas universitas.
Kedua, revisi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi harus memasukkan norma eksplisit tentang pelanggaran integritas ilmiah, termasuk mekanisme pencabutan gelar dan jabatan akademik. Ketiga, menerapkan transparansi publik dalam setiap proses kenaikan jabatan akademik, termasuk publikasi karya ilmiah, riwayat penelitian, dan evaluasi etik, agar masyarakat dapat ikut mengawasi.
Di samping regulasi, kampus perlu menumbuhkan budaya akademik yang menolak transaksi dan menumbuhkan keberanian moral. Kampus tidak boleh lagi menjadi “pabrik gelar,” tetapi harus kembali menjadi benteng moral bangsa.
Menjaga Martabat Ilmu
Gelar profesor bukan hadiah, melainkan amanah. Ia adalah tanggung jawab untuk menjaga kebenaran, bukan alat untuk memperindah kartu nama atau mempertebal dompet. Jika gelar profesor dapat diperjualbelikan, maka nilai keilmuan telah jatuh menjadi komoditas murahan. Kita sedang menyaksikan komersialisasi pengetahuan, di mana moralitas digantikan oleh harga, dan integritas digantikan oleh koneksi.
Bangsa ini tidak akan maju hanya dengan banyak profesor, tetapi dengan profesor yang jujur dan berani. Profesor yang tak berintegritas hanyalah simbol kosong; ia berpangkat tinggi, tetapi bermartabat rendah. Ilmu tanpa kejujuran hanya akan melahirkan kebodohan yang berlapis kehormatan palsu.
Oleh karena itu, sudah saatnya kampus dan pemerintah membongkar praktik jual beli gelar dan menegakkan integritas akademik sebagai hukum tertinggi dalam pendidikan tinggi. Sebab, bila profesor saja bisa dibeli, maka ilmu pun kehilangan suaranya, dan bangsa ini kehilangan arah moralnya.
Profesor sejati bukan diukur dari pangkat, tetapi dari keberanian menegakkan kebenaran. Guru besar sejati bukan yang dipanggil “profesor,” tetapi yang hidup dengan integritas ilmiah. Karena di ujungnya, sejarah tidak akan mengingat berapa banyak gelar yang dimiliki seseorang, melainkan seberapa jujur ia menjaga ilmu dan nurani.

 Desi Sommaliagustina
Desi Sommaliagustina