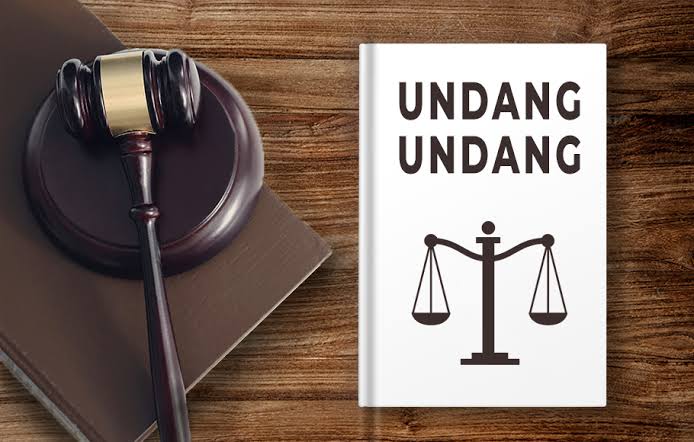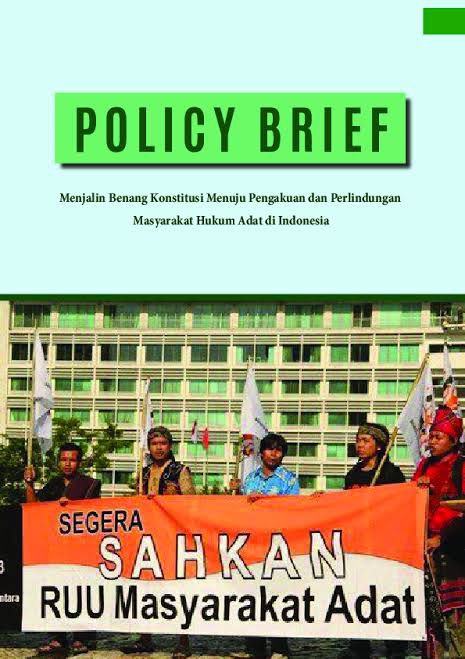Hukum dibuat untuk melindungi, bukan mencurigai. Jika Perpol ini dibiarkan, bukan ketertiban yang lahir, melainkan ketakutan.
Dewan Pers menyerukan peninjauan ulang Peraturan Kepolisian Nomor 3 Tahun 2025 tentang Pengawasan Fungsional terhadap Orang. Seruan itu bukan sekadar formalitas kelembagaan, melainkan sinyal bahaya. Regulasi ini bisa menjadi lubang hitam bagi kebebasan sipil jika tak segera dikoreksi.
Dalam Perpol 3/2025, kepolisian diberi wewenang mengawasi individu yang “patut diduga” mengganggu keamanan dan ketertiban. Tak ada tolok ukur objektif yang membatasi siapa yang bisa masuk kategori itu. Maka, pengawasan bisa jatuh pada siapa saja: aktivis, jurnalis, akademisi, bahkan warga biasa yang sekadar bersuara di media sosial.
Kita tahu, di negeri ini, “patut diduga” sering kali lebih kuat daripada bukti. Padahal, negara hukum tak berdiri di atas dugaan, melainkan pada asas legalitas dan akuntabilitas. Pengawasan terhadap warga negara tak bisa dijalankan diam-diam, tanpa pengawasan independen, tanpa batas waktu, dan tanpa jalan keberatan hukum.
Perpol ini membuka ruang represi yang halus tapi efektif. Tidak dengan membungkam secara frontal, melainkan dengan menciptakan rasa diawasi terus-menerus. Ini bentuk baru dari kontrol sosial yang dapat melumpuhkan keberanian sipil. Ketika rakyat merasa terus dipantau, demokrasi pelan-pelan lumpuh dari dalam.
Sejak kapan kepolisian menjadi lembaga intelijen sipil? Apa dasar legitimasi yuridisnya? Apakah ini bentuk baru dari perluasan kuasa negara yang tak dibicarakan di ruang publik?
Jika tak dikoreksi, Perpol 3/2025 bisa menjadi senjata legal untuk membungkam kritik. Polisi, dalam hal ini, bisa menjadi hakim di luar pengadilan. Maka, peninjauan ulang bukan saja perlu, tetapi mendesak. Prosesnya harus melibatkan lembaga independen, masyarakat sipil, dan para ahli hukum. Kita sedang bicara soal hak warga negara, bukan sekadar urusan internal institusi. Mau sampai kapan seperti ini?!

 Desi Sommaliagustina
Desi Sommaliagustina