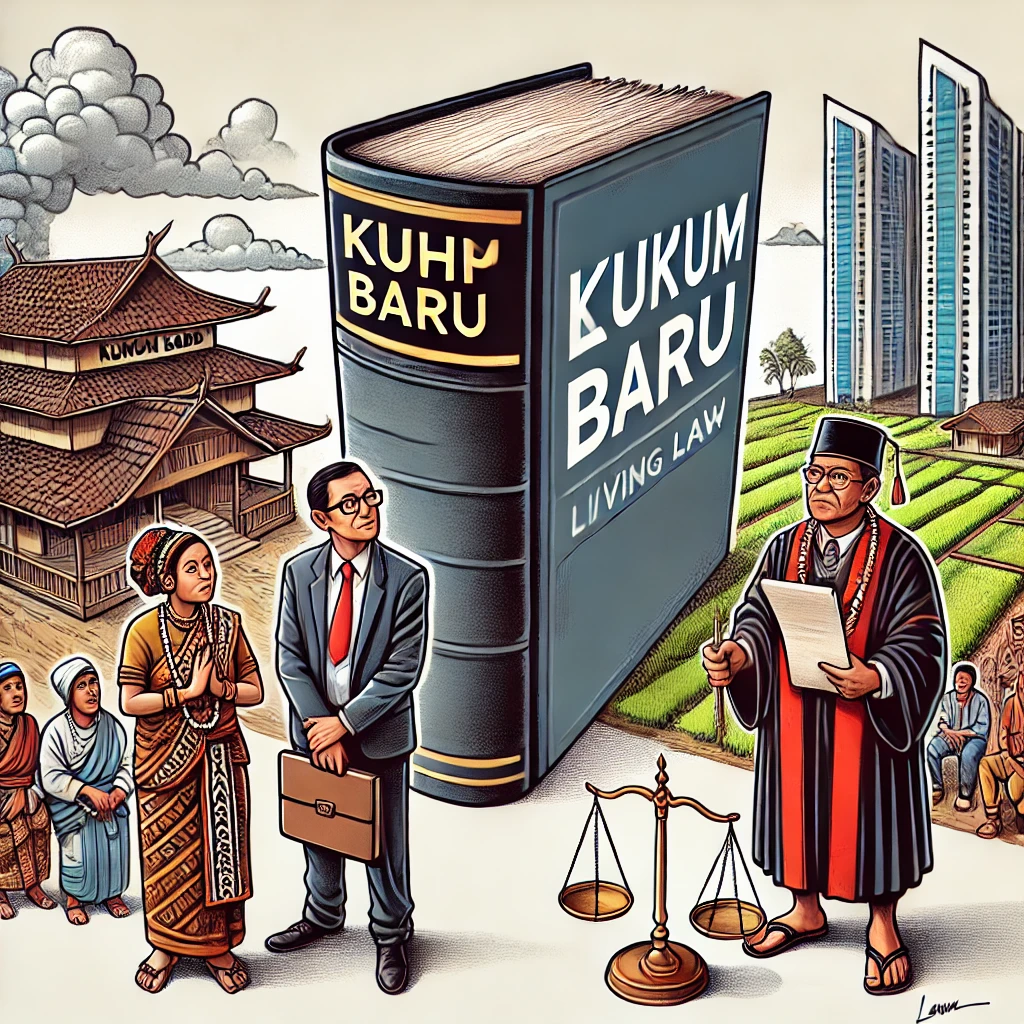Kabar perceraian pasangan selebritas Baim Wong dan Paula Verhoeven kembali menghidupkan perbincangan publik mengenai hukum keluarga di Indonesia. Tidak hanya soal hak asuh anak dan pembagian harta bersama, munculnya label “istri durhaka” yang diduga diucapkan oleh majelis hakim dalam persidangan juga menambah kompleksitas kasus ini.
Pernyataan tersebut menuai kritik karena dinilai bias gender dan mengesampingkan prinsip imparsialitas yang seharusnya menjadi pegangan seorang hakim. Persoalan ini memperlihatkan betapa pentingnya menjaga marwah pengadilan dalam perkara yang sudah sensitif secara emosional, apalagi melibatkan tokoh publik.
Dalam kerangka hukum Indonesia, perceraian diatur dengan prinsip kehati-hatian. Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan, dengan didasarkan pada alasan-alasan yang sah dan dibuktikan di pengadilan.
Hakim dalam perkara perceraian tidak sekadar menjadi “pemutus sengketa”, tetapi juga “pelindung hak-hak hukum para pihak dan anak-anak”. Sebagaimana diatur dalam Pasal 41 UU Perkawinan, meskipun terjadi perceraian, hak dan kewajiban orangtua terhadap anak tetap harus dijalankan.
Dalam konteks ini, hakim berkewajiban menjaga netralitas, menghormati harkat martabat para pihak, serta tidak menunjukkan keberpihakan baik secara langsung maupun melalui pernyataan-pernyataan yang mengandung penilaian moral.
Label ‘Istri Durhaka’: Bias Gender dalam Dunia Peradilan?
Pernyataan “istri durhaka” yang diduga dilontarkan oleh hakim dalam kasus perceraian Baim dan Paula, jika benar, patut dikritisi dari perspektif hukum modern.
Secara etik, Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum menekankan pentingnya menghindari segala bentuk stereotip gender. Hakim dilarang membuat asumsi atau pernyataan yang mendiskreditkan salah satu pihak berdasarkan peran tradisional laki-laki atau perempuan.
Lebih jauh, Komentar Umum No. 28 dari Komite HAM PBB mengenai Pasal 3 Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik (yang juga diakui Indonesia) mewajibkan pengadilan untuk memperlakukan semua pihak tanpa diskriminasi berdasarkan gender.
Dengan demikian, penggunaan label “istri durhaka” tidak hanya menimbulkan ketidaknyamanan di ruang sidang, tetapi juga berpotensi melanggar prinsip persamaan di hadapan hukum (equality before the law), sebagaimana dijamin dalam Pasal 27 ayat (1) UUD 1945. Secara prinsip, semua pihak dalam persidangan memiliki hak atas proses hukum yang adil (fair trial), termasuk hak untuk didengar secara objektif dan tanpa prasangka.
Apabila seorang hakim sudah membentuk opini yang bersifat moralistik terhadap salah satu pihak sebelum semua bukti dan keterangan disampaikan, maka prinsip audi alteram partem — mendengarkan kedua belah pihak secara adil — terancam dilanggar.
Dalam preseden hukum, Mahkamah Agung melalui Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2018 menekankan bahwa seorang hakim harus menjaga sikap, perilaku, dan tutur kata yang sopan dan netral, khususnya dalam perkara keluarga yang sensitif.
Bila persepsi ketidaknetralan ini dibiarkan, bukan hanya rasa keadilan pihak yang berperkara yang terganggu, tetapi juga kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan itu sendiri.
Hak Anak di Tengah Perceraian Hingga Pembagian Harta
Di tengah polemik ini, yang paling rentan tetaplah anak-anak. Menurut prinsip the best interest of the child sebagaimana diatur dalam Konvensi Hak Anak (diratifikasi Indonesia lewat Keppres Nomor 36 Tahun 1990), keputusan pengadilan dalam perceraian harus mengutamakan kesejahteraan fisik, mental, dan emosional anak.
Dalam praktiknya, Kompilasi Hukum Islam (Pasal 105) dan Pasal 41 UU Perkawinan menempatkan tanggung jawab pemeliharaan anak di pundak kedua orangtua, sekalipun setelah perceraian. Pengadilan harus memastikan bahwa ketegangan emosional dalam sidang, termasuk labelisasi yang merendahkan salah satu pihak, tidak berdampak pada psikologi anak yang menjadi bagian dari perkara.
Tidak kalah penting, perkara ini akan menyentuh isu pembagian harta bersama. Dalam UU Perkawinan, prinsipnya semua harta yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama, kecuali ditentukan lain dalam perjanjian pranikah. Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam menegaskan bahwa bila terjadi perceraian, masing-masing pihak berhak memperoleh setengah dari harta bersama.
Dalam kasus Baim dan Paula, nilai kekayaan yang diperebutkan tidak kecil, mengingat keduanya aktif dalam bisnis digital, endorsement, dan usaha lainnya. Penyelesaian harta ini, idealnya, dilakukan secara adil dan transparan, bukan berdasarkan asumsi moral atas siapa yang lebih bersalah dalam perceraian.
Sesuai Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi, sebelum memasuki pemeriksaan pokok perkara, wajib ditempuh upaya mediasi. Dalam konteks perceraian Baim dan Paula, keberhasilan mediasi akan sangat menguntungkan, bukan hanya bagi kedua pihak, tetapi terutama bagi anak-anak mereka. Mediasi memberikan ruang bagi penyelesaian yang lebih manusiawi, jauh dari hiruk pikuk sorotan media.
Perceraian Baim Wong dan Paula Verhoeven memperlihatkan bahwa perkara keluarga bukanlah sekadar urusan dua individu, melainkan menyangkut prinsip-prinsip keadilan, kesetaraan, dan perlindungan hak anak yang harus dijaga dengan serius.
Pengadilan harus menjadi tempat yang netral dan berwibawa, bukan arena di mana stereotip gender diproduksi ulang. Sebagaimana diingatkan dalam Bangalore Principles of Judicial Conduct, hakim harus mengedepankan integritas, netralitas, dan kesopanan dalam semua tindak-tanduknya.
Ini bukan hanya demi para pihak, tetapi demi menjaga kepercayaan publik terhadap hukum itu sendiri. Kasus ini mengajarkan bahwa keadilan dalam perkara keluarga menuntut lebih dari sekadar menerapkan hukum secara mekanis: ia menuntut empati, kesetaraan, dan penghormatan terhadap martabat manusia.
Apakah langkah hukum yang diambil Paula Verhoeven untuk melaporkan hakim ke komisi yudisial terkait label “istri durhaka” tersebut, sudah benar? Jawabannya tentunya sudah benar. Karena pernyataan yang dilontarkan hakim tidak hanya menimbulkan ketidaknyamanan di ruang sidang, tetapi juga berpotensi melanggar prinsip persamaan di hadapan hukum (equality before the law).
Sebagaimana dijamin dalam Pasal 27 ayat (1) UUD 1945, melanggar kode etik ke profesionalan hakim hingga berdampak pada psikologi anak yang menjadi bagian dari perkara (jejak digital) ini.
Pada akhirnya, sebagai penutup “belajar dari rumah tangga orang lain bukan berarti ikut campur. Dalam hukum keluarga, suami dan istri itu ibarat sepasang sepatu: bentuknya beda, jalannya harus sama. Setiap kisah mengajarkan hikmah. Setiap perjalanan mengajarkan perbaikan. Hukum pun hidup dari kisah nyata manusia. Jangan tutup mata, jangan tutup telinga. Belajarlah, ambillah hikmah, tanpa menghakimi!”

 Desi Sommaliagustina
Desi Sommaliagustina