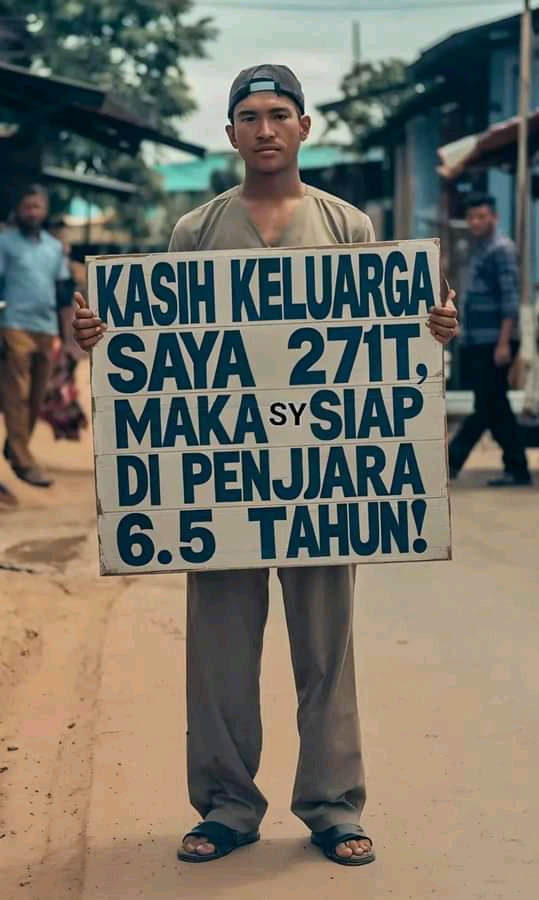Sekilas, proyek pembangunan “Sekolah Rakyat” oleh pemerintah pusat tampak membawa harapan. Ketika proyek ini justru mengorbankan ruang belajar anak-anak dengan disabilitas, pertanyaan etis dan hukum pun muncul. Di balik jargon pembangunan pendidikan inklusif, kita menyaksikan kenyataan pahit: SLBN A Pajajaran Bandung—lembaga pendidikan khusus mengalami penggusuran sebagian bangunan vitalnya, yaitu gedung C dan D yang digunakan oleh siswa SD, SMP, dan siswa dengan disabilitas ganda.
Dengan pembongkaran ini, ruang kelas yang tersedia menyusut dari 37 menjadi hanya tiga. Imbasnya, proses belajar mengajar terganggu. Kelas digabung tanpa memperhatikan jenis disabilitas siswa, menyebabkan kesenjangan dalam metode pembelajaran. Apakah ini wajah pendidikan inklusif yang dijanjikan negara?
Pasal 31 ayat (1) UUD 1945 menyatakan bahwa setiap warga negara berhak mendapat pendidikan. Hak ini diperluas dalam Pasal 42 ayat (2) UU Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas yang menyebutkan bahwa negara wajib menyediakan aksesibilitas dalam pendidikan, termasuk sarana dan prasarana yang ramah disabilitas. Dalam konteks ini, penggusuran ruang belajar siswa dengan kebutuhan khusus tanpa alternatif setara merupakan pelanggaran nyata terhadap hak konstitusional mereka.
Sementara itu, ratifikasi Indonesia terhadap Konvensi Hak-Hak Penyandang Disabilitas (CRPD) melalui UU No. 19 Tahun 2011 memperkuat kewajiban negara untuk menjamin ketersediaan, keterjangkauan, dan keberterimaan layanan pendidikan bagi penyandang disabilitas. Dalam instrumen hukum ini, prinsip non-diskriminasi dan partisipasi bermakna (meaningful participation) menjadi fondasi penting.
Namun dalam kasus SLBN Pajajaran, asas partisipatif itu diabaikan. Komite sekolah, guru, orang tua, dan siswa tidak dilibatkan secara bermakna dalam perencanaan pembongkaran. Ini bertentangan dengan prinsip partisipasi dalam penyusunan kebijakan publik sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 96 UU No. 12 Tahun 2011.
Alih-alih melindungi yang lemah, negara justru mencederai mereka. Proyek pembangunan sekolah rakyat, meskipun tampak progresif, dilakukan tanpa kajian mendalam atas dampaknya terhadap siswa disabilitas. Aspek keadilan sosial sebagaimana tercantum dalam Pancasila pun diabaikan. Padahal, dalam hukum administrasi negara, asas perlindungan terhadap kelompok rentan harus menjadi prioritas.
Pemerintah melalui Kemensos membantah melakukan penggusuran, dan menyatakan bahwa ini adalah bagian dari penataan ulang fungsi bangunan di kompleks Wyata Guna. Akan tetapi, fakta lapangan menunjukkan penurunan signifikan kualitas pembelajaran. Jika benar pemerintah mengedepankan inklusivitas, mengapa tidak dilakukan pemindahan yang memperhatikan kenyamanan dan keberlanjutan kegiatan belajar?
Peristiwa ini menandakan adanya kekerasan struktural yang dilanggengkan oleh kebijakan pembangunan. Kekerasan itu tidak harus dalam bentuk fisik. Ia hadir dalam bentuk penggusuran, pemaksaan, dan marginalisasi yang berdampak langsung terhadap proses tumbuh kembang anak disabilitas.
Di tengah gembar-gembor program inklusi dan kurikulum merdeka, justru negara mempersempit ruang belajar siswa tunanetra. Ini menciptakan ketidakadilan yang mendalam, bahkan dapat dikategorikan sebagai bentuk diskriminasi sistemik. Padahal, dalam asas umum pemerintahan yang baik (AUPB), negara seharusnya menjamin rasa keadilan, kepastian hukum, dan tidak menyalahgunakan wewenang.
Pemerintah, baik pusat maupun daerah, harus segera mengevaluasi proses penggusuran ini. Komnas Disabilitas dan Komnas HAM harus turun tangan, menyelidiki pelanggaran hak atas pendidikan dan partisipasi dalam perumusan kebijakan. Jika proyek sekolah rakyat tetap dilanjutkan, maka negara wajib menjamin bahwa relokasi SLBN dilakukan ke lokasi yang setara atau lebih baik, dengan pelibatan semua pemangku kepentingan.
Kita tidak bisa lagi menerima pendekatan pembangunan yang top-down dan elitis. Apalagi jika yang dikorbankan adalah masa depan anak-anak penyandang disabilitas. Negara tidak boleh terus-menerus menjadikan kelompok rentan sebagai harga yang harus dibayar atas proyek mercusuar. Bila Indonesia sungguh ingin menjadi negara inklusif, maka pembangunan harus dimulai dari mendengarkan mereka yang paling tak bersuara.

 Desi Sommaliagustina
Desi Sommaliagustina