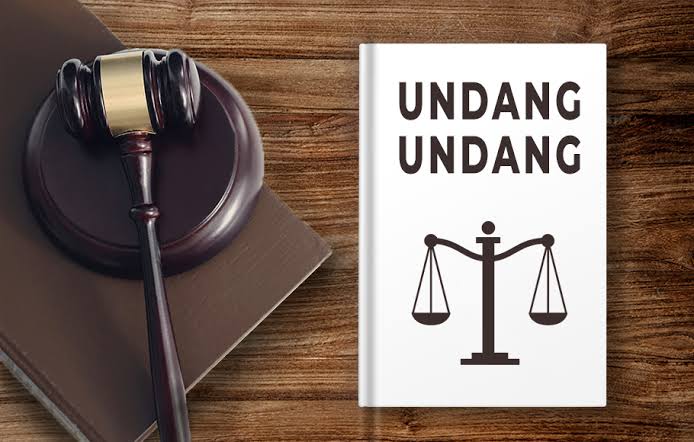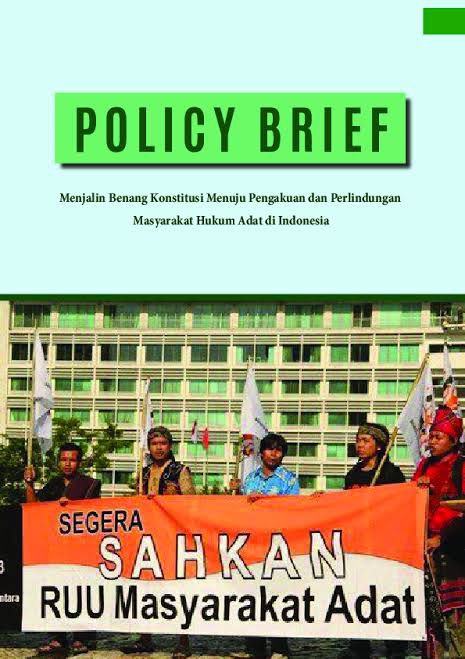Warga Perumahan Athaya, RT. 05 RW. VIII, Dusun IV Desa Tanah Merah, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar, Riau, saat ini tengah bergulat dengan kenyataan pahit. Di tengah upaya membangun kehidupan keluarga yang layak dan damai, mereka justru dihadapkan pada permasalahan lingkungan yang tidak kunjung mendapat perhatian serius: bau busuk dan limbah dari peternakan atau kandang babi yang berdiri hanya beberapa meter dari permukiman warga.
Masalah ini telah berlangsung lama, tetapi eskalasinya semakin menjadi dalam beberapa waktu terakhir. Bau menyengat tercium nyaris setiap hari, terutama pagi dan sore hari. Warga mulai mengalami gangguan pernapasan, sakit kepala, dan kehilangan kualitas hidup. Anak-anak enggan bermain di luar rumah, sementara lansia kian rentan karena terpapar udara tercemar. Situasi ini bukan lagi soal ketidaknyamanan; ini adalah ancaman terhadap hak dasar manusia atas lingkungan hidup yang bersih dan sehat.
Masalah utama dari keberadaan kandang babi ini bukan hanya karena lokasi yang terlalu dekat dengan rumah penduduk. Lebih dari itu, terdapat indikasi kuat bahwa aktivitas usaha tersebut tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH), setiap kegiatan usaha yang berpotensi menimbulkan pencemaran lingkungan wajib dilengkapi dengan dokumen lingkungan, baik dalam bentuk UKL-UPL maupun AMDAL, tergantung skala usahanya.
Namun, hingga kini belum ada kejelasan apakah peternakan tersebut telah memenuhi persyaratan legalitas lingkungan. Bahkan jika pun memiliki izin, keberadaan peternakan di dalam kawasan pemukiman padat jelas bertentangan dengan prinsip penataan ruang sebagaimana diatur dalam UU Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang. Permukiman adalah zona untuk hunian, bukan untuk aktivitas usaha yang berisiko tinggi terhadap kesehatan masyarakat.
Dalam hal ini tentunya Pemerintah Desa Tanah Merah tidak boleh tinggal diam, apalagi hanya sebagai penonton, dan sekadar datang tapi hasil nol. Disinilah pemerintahan itu diuji. Permasalahan ini bukanlah hal yang baru, tentunya masyarakat bisa menilai sejauh mana kinerja pemerintahan desa dalam menyelesaikan permasalahan yang ada. Relokasi wajib dilakukan untuk menyelesaikan masalah yang telah berlangsung lama ini. Yang jadi pertanyaan apakah pemerintah desa memiliki keberanian untuk hal ini?
Relokasi Bukan Pilihan, Tapi Kewajiban
Lembaga Kebijakan Publik Indonesia (LKpIndonesia) melalui wawancara bersama Desi Sommaliagustina, selaku pakar hukum dari Universitas Dharma Andalas Padang, menilai bahwa kasus ini menunjukkan lemahnya pengawasan dan ketegasan aparat pemerintahan desa hingga kabupaten dalam menegakkan hukum.
“Negara wajib hadir dalam menjamin hak warga atas lingkungan hidup yang bersih. Jika sebuah usaha terbukti mencemari lingkungan dan berdampak pada kesehatan warga, maka relokasi bukan lagi pilihan, tapi menjadi kewajiban hukum dan moral,” ujar Desi.
Ia menambahkan bahwa warga memiliki landasan hukum yang kuat untuk mengajukan gugatan class action jika pemerintah terus abai.
“Pasal 66 UU PPLH secara eksplisit memberi hak kepada masyarakat untuk hak atas lingkungan tanpa perlu takut dituntut secara pidana maupun perdata. Ini harus dimanfaatkan oleh warga dengan pendampingan hukum yang tepat,” tambahnya.
Kisah Perum Athaya sebenarnya bukanlah kasus tunggal. Di banyak daerah, warga kecil harus berhadapan dengan industri, peternakan, atau kegiatan usaha yang menjadikan lingkungan sebagai korban. Negara seolah lebih memihak pada pemilik modal ketimbang warga yang menjadi korban langsung dari pencemaran.
Dalam konteks ini, Pemerintah Desa, Kecamatan, Pemerintah Kabupaten Kampar, Dinas Lingkungan Hidup, serta Satpol PP memiliki tanggung jawab untuk bertindak. Audit lingkungan harus segera dilakukan. Jika peternakan tersebut terbukti tidak memiliki izin, maka harus ditutup sementara hingga dipindahkan ke lokasi yang sesuai zonasi. Jika dibiarkan, maka pemerintah turut andil dalam pelanggaran hak-hak konstitusional warga.
Perlu ditekankan bahwa warga bukan anti terhadap usaha peternakan babi. Banyak warga sendiri yang memahami bahwa usaha ini menopang ekonomi sebagian masyarakat. Namun yang dituntut adalah keadilan ekologis: bahwa usaha apapun tidak boleh merugikan ruang hidup orang lain.
LKpIndonesia, juga sependapat dan menegaskan hal serupa “Konflik seperti ini tidak akan muncul jika sejak awal pemerintah menerapkan prinsip kehati-hatian dan uji risiko sosial dalam setiap izin usaha. Masalahnya bukan pada jenis usahanya, melainkan pada tata kelola dan pengabaian prinsip kehati-hatian.”
Menurut Andre Vetronius, selaku Ketua Umum LKpIndonesia sependapat dengan Desi. Satu-satunya solusi terbaik untuk kasus ini adalah relokasi kandang babi ke zona khusus peternakan yang berada jauh dari permukiman. Relokasi bukan hanya menyelamatkan warga dari polusi, tetapi juga menjaga keberlanjutan usaha peternakan itu sendiri dalam jangka panjang.
Namun relokasi harus dilakukan dengan dialog, mediasi, dan kompensasi yang adil. Pemerintah perlu hadir sebagai mediator aktif yang berpihak pada hukum dan kemanusiaan. Jangan biarkan masyarakat bergerak sendiri tanpa kepastian. Apalagi menutup mata dan telinga terkait kasus ini!
Belajar dari Daerah Lain
Banyak daerah telah berhasil menyelesaikan konflik lingkungan serupa melalui dialog intensif dan kebijakan relokasi. Misalnya, di Bantul, Yogyakarta, pemerintah daerah berhasil memindahkan peternakan ayam ke zona peternakan terpadu setelah desakan warga yang terdampak pencemaran bau.
Demikian pula di Sumedang, Jawa Barat, pemerintah membangun kawasan peternakan modern dengan sistem biosecurity dan pengolahan limbah berbasis teknologi ramah lingkungan. Langkah-langkah ini menunjukkan bahwa penyelesaian bisa dilakukan tanpa harus menciptakan konflik berkepanjangan.
Kasus Perum Athaya adalah cermin kegagalan tata kelola ruang dan pengabaian terhadap hak dasar warga. Pemerintah daerah harus segera mengambil tindakan korektif, bukan sekadar janji atau pembiaran. Ini bukan hanya soal limbah atau bau, tetapi soal martabat warga sebagai manusia yang ingin hidup tenang di rumah sendiri.
Jika negara terus bungkam, maka wajar jika warga mencari keadilan melalui jalur hukum atau tekanan publik. Dalam negara hukum yang demokratis, suara warga adalah ukuran keberpihakan pemerintah. Jika pemukiman tak lagi aman dan sehat, maka kita bukan sedang membangun masa depan, melainkan menggali jurang perpecahan ekologis.

 Andre Vetronius
Andre Vetronius