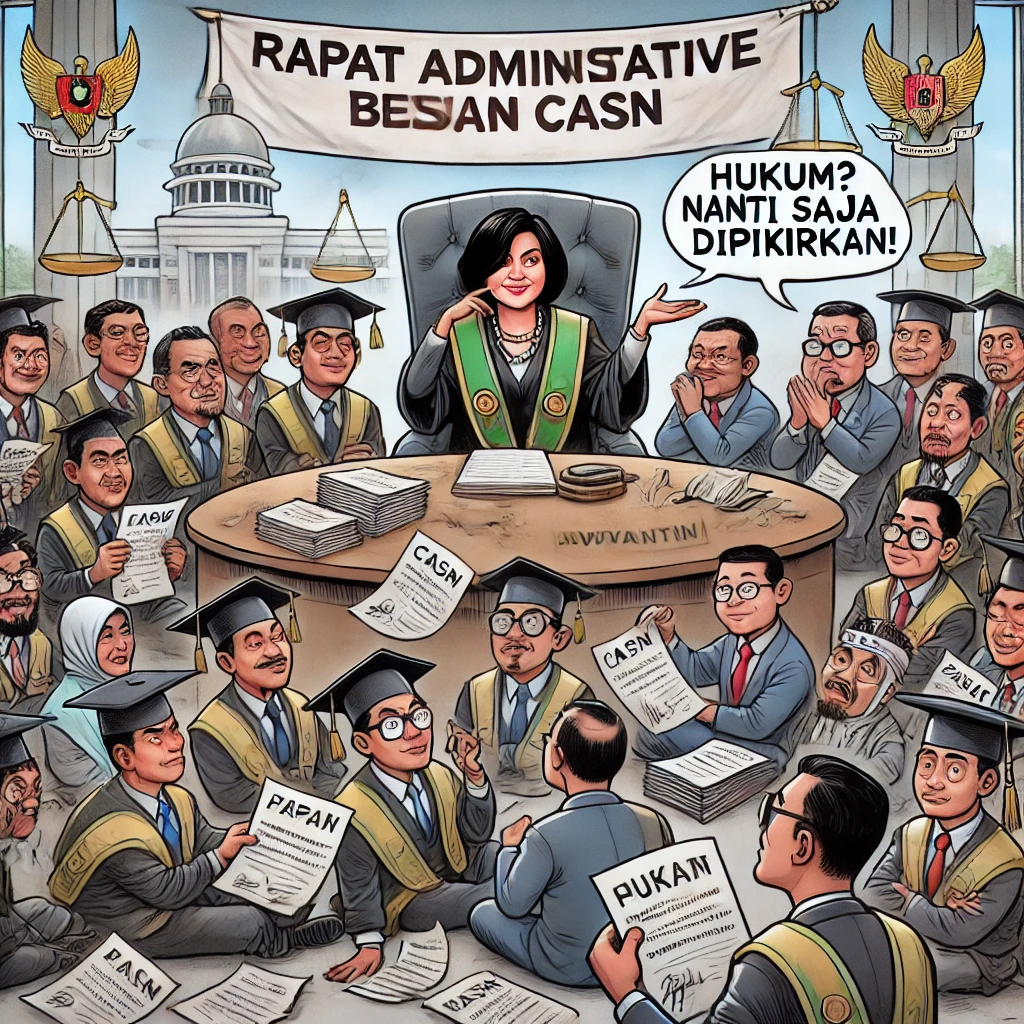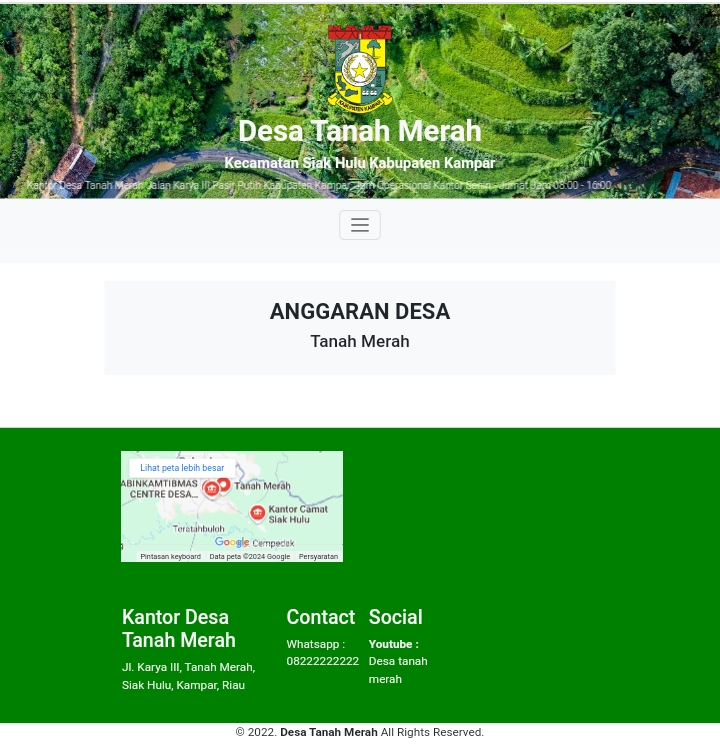Komisi Pemilihan Umum (KPU) kembali menjadi sorotan publik setelah membatalkan Keputusan KPU Nomor 731 Tahun 2025. Aturan yang sebelumnya diterbitkan ini sempat menetapkan bahwa dokumen syarat pencalonan presiden dan wakil presiden, termasuk ijazah, digolongkan sebagai informasi publik yang dikecualikan. Artinya, publik tidak dapat mengakses dokumen tersebut tanpa persetujuan dari pemilik data.
Langkah KPU menuai kritik keras. Akademisi, pegiat demokrasi, hingga kelompok masyarakat sipil menilai keputusan tersebut bertentangan dengan prinsip keterbukaan informasi publik yang diatur undang-undang. Setelah gelombang kritik kian deras, KPU akhirnya mencabut keputusan itu. Ketua KPU, Afifuddin, menyebut pencabutan dilakukan setelah rapat khusus dan koordinasi dengan sejumlah pihak, termasuk Komisi Informasi Pusat (KIP).
Sekilas, pencabutan aturan ini bisa dibaca sebagai langkah positif. KPU dianggap mau mendengar aspirasi publik. Namun, jika ditelusuri lebih jauh, fenomena ini menunjukkan pola kelembagaan yang berbahaya: KPU tampak terjebak dalam sindrom “cek ombak”. Lembaga penyelenggara pemilu seolah-olah menerbitkan aturan tanpa kajian hukum yang matang, hanya untuk melihat seberapa besar reaksi publik. Jika gelombang kritik besar, aturan buru-buru dicabut.
Antara Hak Privasi dan Hak Publik
Pertarungan argumentasi dalam kasus ini sesungguhnya berakar pada ketegangan klasik: hak privasi versus hak publik untuk tahu. KPU dalam keputusannya sempat merujuk pada UU Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP). Benar bahwa dokumen pribadi, seperti ijazah, akta kelahiran, atau nomor identitas, pada prinsipnya dilindungi kerahasiaannya. Namun, problem muncul ketika dokumen pribadi itu digunakan sebagai syarat pencalonan pejabat publik.
Dalam konteks ini, dokumen pribadi berubah fungsi. Ia bukan lagi sekadar identitas pribadi, melainkan bukti pemenuhan syarat administratif yang ditentukan oleh undang-undang. Oleh karena itu, dokumen tersebut masuk dalam kategori informasi publik yang dapat diakses, sesuai dengan UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP).
Pasal 17 UU KIP memang mengatur adanya informasi yang dikecualikan, termasuk yang menyangkut rahasia pribadi. Tetapi pasal yang sama juga menegaskan bahwa pengecualian tidak boleh menghalangi publik untuk mengetahui informasi yang menyangkut kepentingan publik luas. Mahkamah Konstitusi dalam berbagai putusan pun menekankan: keterbukaan adalah norma utama, sementara kerahasiaan hanya pengecualian yang sifatnya limitatif.
Dalam hal pencalonan presiden, ijazah, riwayat pendidikan, dan dokumen hukum lain jelas menyangkut kepentingan publik. Seorang calon presiden bukan lagi “pribadi biasa” yang hak privasinya absolut. Begitu ia mengajukan diri, maka legitimasi pencalonannya wajib diverifikasi publik.
Risiko “Cek Ombak”
Sikap KPU yang baru mencabut aturan setelah mendapat kritik publik, menimbulkan tanda tanya serius. Bagaimana mungkin sebuah lembaga konstitusional sebesar KPU tidak menyadari sejak awal bahwa keputusan itu bertentangan dengan undang-undang?
Fenomena ini menunjukkan kelemahan dalam dua hal. Pertama, lemahnya basis hukum yang menjadi landasan pengambilan keputusan. KPU seharusnya berpegang pada prinsip lex superior derogat legi inferiori—bahwa peraturan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi. Jika UU KIP mewajibkan keterbukaan, maka keputusan KPU tidak boleh menutup akses informasi.
Kedua, menurunnya kualitas kepemimpinan kelembagaan. Alih-alih menjadi wasit yang tegas dan independen, KPU tampak gamang. Pola ini berbahaya karena berpotensi mencederai kepercayaan publik. Pemilu hanya bisa berjalan dengan legitimasi penuh bila penyelenggaranya berdiri tegak di atas hukum, bukan diombang-ambing opini publik.
Ketiga, potensi politisasi keputusan. Ketika aturan diterbitkan tanpa kajian matang lalu buru-buru dicabut, publik bisa saja curiga: jangan-jangan ada kepentingan politik tertentu yang sedang diuji. Apalagi jika aturan itu terkait dengan isu sensitif seperti keabsahan ijazah calon presiden, isu yang bisa mengguncang kepercayaan publik pada demokrasi.
Transparansi dan Belajar dari Negara Lain
Apakah artinya semua dokumen harus dibuka tanpa batas? Tentu tidak. Prinsip keterbukaan informasi publik tetap mengenal batas. Misalnya, alamat rumah pribadi, nomor induk kependudukan, detail keluarga, atau informasi medis kandidat, tetap harus dilindungi.
Namun, dokumen yang menjadi syarat formal pencalonan; ijazah, surat keterangan bebas pidana, laporan harta kekayaan, riwayat pendidikan, hingga surat dukungan partai politik wajib terbuka. Keterbukaan bukan hanya untuk memenuhi rasa ingin tahu publik, tetapi juga untuk mencegah manipulasi, pemalsuan, atau penyalahgunaan wewenang.
Prinsip keterbukaan dokumen pencalonan bukan hal baru dalam demokrasi. Banyak negara telah lama mempraktikkannya. Amerika Serikat, calon presiden wajib menyerahkan dokumen pendidikan, rekam medis, laporan pajak, hingga riwayat karier. Data ini dipublikasikan secara luas, bahkan laporan pajak presiden menjadi isu kampanye yang krusial. Transparansi dipandang sebagai syarat legitimasi moral seorang pemimpin.
Filipina, Komisi Pemilihan Umum (COMELEC) membuka Certificate of Candidacy setiap kandidat kepada publik. Publik bisa mengakses data pendidikan, pengalaman, hingga catatan hukum kandidat. Transparansi ini terbukti membantu media dan masyarakat sipil melakukan verifikasi independen.
India, calon anggota parlemen dan presiden wajib menyerahkan affidavit berisi informasi detail mengenai aset, liabilitas, latar belakang kriminal, dan pendidikan. Dokumen tersebut dipublikasikan secara daring sehingga dapat diakses siapa pun.
Perbandingan ini menunjukkan, keterbukaan dokumen pencalonan adalah praktik umum di negara demokrasi. Indonesia tidak hanya tertinggal jika menutup akses, tetapi juga mempertaruhkan kualitas legitimasi pemilu.
Pemilu dan Kepercayaan Publik
Pada akhirnya, yang dipertaruhkan dalam kasus ini bukan sekadar soal ijazah. Yang dipertaruhkan adalah kepercayaan publik terhadap pemilu. Pemilu tidak hanya menentukan siapa yang akan memimpin Indonesia, tetapi juga akan menjadi tolok ukur: apakah rakyat masih percaya pada proses demokrasi. Kepercayaan publik adalah modal sosial terbesar pemilu. Sekali ia runtuh, maka legitimasi hasil pemilu pun akan tergerus.
KPU tidak boleh lagi terjebak dalam pola “cek ombak”. Keputusan penting harus lahir dari kajian hukum mendalam, koordinasi sejak awal dengan lembaga terkait, dan yang paling penting komitmen teguh pada prinsip keterbukaan. KPU bukan lembaga politik yang bisa tawar-menawar, melainkan lembaga hukum yang harus taat pada aturan main demokrasi.
Kritik publik terhadap KPU atas kasus ini harus dibaca sebagai peringatan keras. Penyelenggara pemilu tidak boleh main-main dengan prinsip keterbukaan. Publik berhak mengetahui siapa calon pemimpinnya, bagaimana rekam jejaknya, dan apakah syarat pencalonannya sah atau tidak.
Seorang calon presiden boleh saja mengklaim ijazahnya asli. Tetapi dalam negara hukum, klaim pribadi tidak cukup. Publik berhak melihat, memverifikasi, bahkan menggugat. Itulah esensi keterbukaan, dan di situlah demokrasi berdiri.
KPU tidak boleh lagi terjebak dalam sindrom “cek ombak”. Bila ingin menjaga kepercayaan rakyat, KPU harus tegak di atas hukum dan transparansi, bukan plin-plan di hadapan opini. Karena sekali kepercayaan publik runtuh, tidak ada lagi yang tersisa dari pesta demokrasi selain formalitas tanpa legitimasi.

 Desi Sommaliagustina
Desi Sommaliagustina