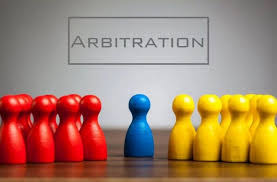Kekerasan seksual telah menjadi krisis yang sistemik, bukan lagi insiden yang sporadis. Dari ruang kelas hingga ruang kerja, dari desa terpencil hingga ibu kota negara, tubuh perempuan (dan laki-laki dalam sebagian kasus) terus menjadi arena kekerasan yang kerap dibiarkan tanpa konsekuensi yang setimpal. Padahal konstitusi Indonesia menjamin perlindungan setiap warga negara atas harkat dan martabatnya, namun dalam praktiknya perlindungan itu sering kali hanya sebatas teks dalam dokumen kenegaraan.
Kita hidup dalam masyarakat yang dalam banyak hal lebih siap menghakimi korban dibanding memperkarakan pelaku. Kekerasan seksual tak hanya melukai tubuh, ia merenggut rasa aman, harga diri, dan kepercayaan terhadap hukum. Lebih parah lagi, negara yang seharusnya menjadi pelindung sering kali justru menjadi penonton, atau bahkan pelindung pelaku.
Kekerasan seksual bukan hanya persoalan moralitas individu, melainkan cermin dari struktur sosial yang timpang dan sistem hukum yang belum berpihak. Banyak pihak menolak mengakui bahwa akar dari kekerasan seksual adalah ketimpangan kuasa dan budaya patriarki yang mengakar kuat. Di ruang-ruang pendidikan, kekuasaan dosen atas mahasiswa digunakan sebagai alat kontrol untuk menundukkan, merayu, atau bahkan mengintimidasi. Di ruang kerja, relasi atasan-bawahan membuka celah yang lebar bagi terjadinya pelecehan yang sistemik dan sulit dilaporkan.
Menurut data Komnas Perempuan, pada tahun 2023 saja, terdapat lebih dari 470 ribu kasus kekerasan terhadap perempuan, di mana kekerasan seksual menempati porsi tertinggi. Namun kita sadar, angka ini adalah fenomena gunung es. Sebagian besar korban memilih diam karena takut, malu, tidak tahu cara melapor, atau khawatir tidak dipercaya. Penanganan kasus yang lamban, aparat penegak hukum yang kurang sensitif, serta stigma dari masyarakat membuat korban lebih nyaman bersembunyi dalam trauma daripada menghadapi sistem hukum yang menguras tenaga dan emosi.
Lahirnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) merupakan capaian monumental dalam perjuangan panjang masyarakat sipil. UU ini membawa semangat baru, mengakui bentuk-bentuk kekerasan seksual yang selama ini tak dianggap sebagai kejahatan, seperti perundungan seksual, eksploitasi seksual, hingga pemaksaan kontrasepsi dan perkawinan.
Namun, setelah dua tahun berlaku, implementasinya masih jauh dari ideal. Banyak aparat penegak hukum yang belum mengikuti pelatihan khusus penanganan kekerasan seksual. Koordinasi antarinstansi, seperti lembaga pendamping korban, kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan masih belum solid. Sementara itu, sebagian pemerintah daerah belum membentuk unit layanan terpadu yang ramah korban. Dalam banyak kasus, korban kekerasan seksual justru dihadapkan pada kriminalisasi balik, reviktimisasi saat proses pemeriksaan, atau dikompromikan dalam penyelesaian adat yang melecehkan nilai keadilan.
Kampus dan Institusi: Tempat Aman yang Tidak Aman
Salah satu ironi paling nyata dari kekerasan seksual adalah betapa lazimnya ia terjadi di institusi yang mestinya menjadi tempat aman dan beradab: kampus. Dalam beberapa tahun terakhir, berbagai kasus kekerasan seksual terungkap di perguruan tinggi ternama di Indonesia, namun respons institusional kerap mengecewakan. Banyak pelaku yang hanya diberikan sanksi ringan atau “dipinggirkan” secara diam-diam. Korban, sebaliknya, harus menghadapi stigma sosial, intimidasi, bahkan kehilangan akses pendidikan.
Survei Komnas Perempuan (2022) menunjukkan bahwa hanya 30% kampus di Indonesia yang memiliki mekanisme pelaporan dan penanganan kekerasan seksual yang berjalan tidak efektif. Padahal Permendikbud No. 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi telah mewajibkan terbentuknya Satuan Tugas (Satgas) di setiap kampus.
Sayangnya, keberadaan Satgas ini kadang hanya formalitas, tanpa kewenangan yang cukup dan tidak dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan penting. Inilah yang sering terjadi, dimana regulasi lahir tapi tidak berdampak. Sebatas menghiasi kinerja pemerintahan ataupun menteri, agar terlihat bekerja. Tapi hasilnya jauh dari harapan!
Negara Harus Hadir Secara Nyata
Media sosial kadang menjadi ruang terakhir bagi korban mencari keadilan. Lewat kampanye seperti #MeToo, #PercayaiKorban, hingga #SayaJuga, banyak korban memberanikan diri bersuara. Namun ruang ini pun tak lepas dari serangan balik. Korban kerap dituduh mencemarkan nama baik, digugat balik oleh pelaku, bahkan mengalami doxing dan serangan digital. Lagi-lagi, negara belum cukup sigap memberikan perlindungan yang memadai, bahkan dalam hal penegakan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), yang sering digunakan untuk membungkam korban.
Negara tidak boleh lagi hanya hadir saat isu viral. Perlindungan korban harus menjadi bagian dari sistem yang permanen. Pertama, perlu penguatan kapasitas aparat penegak hukum agar memiliki perspektif keadilan gender dan tidak menyalahkan korban. Kedua, alokasi anggaran untuk layanan pemulihan korban harus menjadi prioritas, termasuk konseling gratis, bantuan hukum, dan rumah aman.
Ketiga, sistem hukum harus memastikan bahwa pelaku, siapa pun dia dan dari latar belakang apa pun, diproses secara adil dan terbuka. Tak ada lagi kekebalan hukum bagi pejabat, dosen, aparat, atau tokoh masyarakat. Keempat, pendidikan seksualitas yang komprehensif dan berbasis hak asasi manusia harus diperkenalkan sejak dini, bukan untuk “mendorong kenakalan”, melainkan membangun kesadaran batas-batas tubuh, consent, dan menghormati martabat orang lain.
Selain dari negara, masyarakat sipil tentunya harus mengambil peran penting dalam membangun kesadaran kolektif dan menekan negara agar bertanggung jawab. LSM, jurnalis, akademisi, dan komunitas harus bersinergi dalam memberikan edukasi, pendampingan, dan advokasi hukum. Media harus berpihak pada korban, berhenti menggunakan narasi menyudutkan, dan tidak mengaburkan identitas pelaku dengan dalih privasi.
Sementara itu, publik harus belajar percaya pada korban. Tidak semua kebenaran bisa dibuktikan secara teknis, tetapi keadilan tidak boleh berhenti pada pembuktian yang kaku. Seorang filsuf hukum pernah mengatakan, “Jika hukum gagal melindungi yang lemah, maka hukum itu hanya alat kekuasaan, bukan keadilan.”
Kekerasan seksual bukan perkara minor. Ia adalah darurat nasional. Ia tidak akan selesai dengan sekadar peringatan atau seremonial. Ia hanya akan berakhir bila negara secara sistemik dan tegas berpihak pada korban, menindak pelaku, dan mengubah kultur yang membenarkan kekerasan.
Kita tidak boleh lelah bersuara. Kita tidak boleh takut menuntut. Karena tubuh manusia bukan tempat kekerasan. Ia adalah rumah martabat, yang harus dilindungi oleh hukum dan oleh negara.

 Desi Sommaliagustina
Desi Sommaliagustina