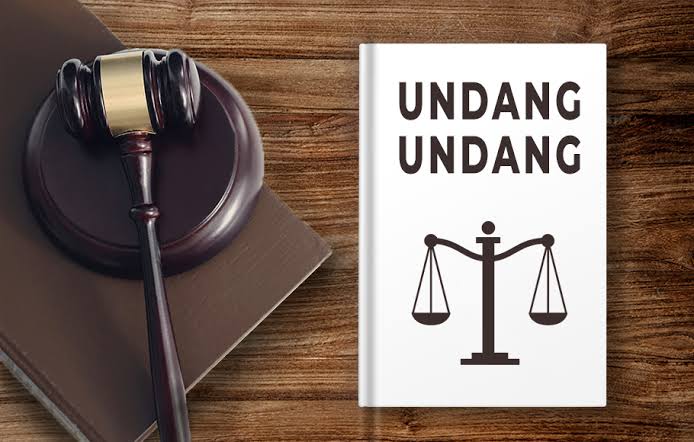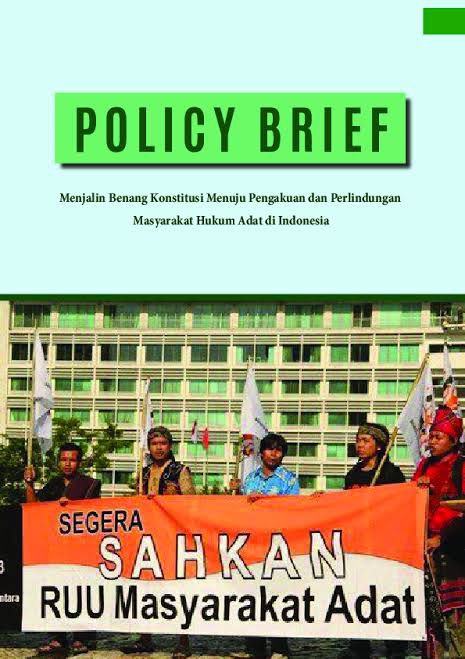Kematian Brigadir Nurhadi, anggota Bidang Profesi dan Pengamanan Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Barat, membuka kembali luka lama yang belum sembuh dalam tubuh kepolisian: kekerasan internal, keterlibatan dalam kejahatan terorganisir, dan minimnya transparansi. Ia bukan satu-satunya. Tapi menjadi pengingat betapa rapuhnya sistem pengawasan ketika integritas justru dibungkam dengan kekerasan.
Brigadir Nurhadi meninggal dunia akibat penganiayaan berat. Tiga tersangka telah ditetapkan: Komisaris Polisi (Kompol) Y dan Inspektur Dua (Ipda) H yang kini diberhentikan tidak dengan hormat, serta seorang perempuan berinisial M yang berada di lokasi kejadian dan diduga ikut terlibat. Namun hingga kini, motif di balik kejadian tragis tersebut masih dinyatakan “belum terungkap”. Sebuah pernyataan yang justru menimbulkan lebih banyak pertanyaan ketimbang jawaban.
Dalam ilmu hukum pidana, motif tidak selalu menjadi unsur delik. Namun dalam perkara yang melibatkan pembunuhan, terutama terhadap sesama aparat penegak hukum, motif adalah jendela yang membuka tabir gelap kejahatan itu sendiri. Ketika seorang anggota Propam unit yang bertugas mengawasi etika dan disiplin kepolisian dibunuh oleh rekan sejawat, maka wajar jika publik bertanya: apa yang sedang coba disembunyikan?
Jika penyidikan berhenti pada kekerasan fisik semata, tanpa menelusuri relasi kuasa, potensi konflik kepentingan, atau bahkan dugaan keterlibatan dalam kejahatan lain seperti narkotika, maka hukum hanya akan menjadi tempelan prosedural. Keadilan harus dibangun bukan hanya dari apa yang tampak, tetapi dari keberanian menyentuh apa yang disembunyikan.
Narkoba dan Jaringan dalam Seragam
Kekhawatiran ini bukan tanpa dasar. Dalam sejumlah kasus sebelumnya, keterlibatan oknum aparat kepolisian dalam jaringan narkotika sudah berkali-kali terbongkar. Dari kasus Irjen Teddy Minahasa hingga penangkapan anggota polisi berpangkat menengah yang menjadi bandar, menunjukkan bahwa sistem pengawasan internal kerap kali gagal menangkal penyalahgunaan kekuasaan di lingkaran dalam.
Jika Brigadir Nurhadi tengah menelusuri pelanggaran serius terkait penyalahgunaan narkoba di internal Polda NTB, maka tindak kekerasan yang dialaminya bisa saja merupakan bentuk pembungkaman. Perempuan berinisial M yang berada di lokasi kejadian juga tidak bisa dilepaskan dari konteks ini. Dalam banyak skema jaringan narkoba, perempuan kerap dilibatkan sebagai “kurir”, “umpan”, atau perantara. Tapi tidak sedikit pula yang menjadi bagian inti dari jaringan, termasuk dalam fungsi komunikasi dan logistik.
Penyidik mesti menguji secara obyektif apakah M berperan aktif dalam perencanaan atau pelaksanaan kekerasan, atau justru menyimpan informasi kunci terkait motif pembunuhan. Jika memang ditemukan keterkaitan dengan peredaran narkotika, maka pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dapat diterapkan secara akumulatif.
Pasal 351 ayat (3) KUHP memang relevan untuk penganiayaan yang menyebabkan kematian. Namun dalam kasus ini, semestinya penyidik tidak berhenti pada delik tersebut. Jika ditemukan bukti perencanaan, maka Pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana wajib dikenakan. Demikian pula Pasal 338 KUHP sebagai alternatif apabila unsur perencanaan tidak kuat, tetapi ada kesengajaan menghilangkan nyawa.
Selain itu, Pasal 55 dan 56 KUHP mengenai penyertaan dan pembantuan tindak pidana menjadi penting untuk membongkar kerja kolektif di balik kejahatan ini. Jika ada upaya menghilangkan barang bukti atau menghambat penyidikan, Pasal 221 KUHP dapat dikenakan. Penerapan pasal berlapis bukan bentuk kriminalisasi berlebihan, melainkan instrumen hukum yang sah untuk menjamin pertanggungjawaban yang menyeluruh.
Kritik atas Anggaran yang Membengkak
Ironisnya, kasus kekerasan dan penyalahgunaan kekuasaan dalam tubuh kepolisian ini terjadi di saat DPR RI baru saja menyetujui tambahan anggaran untuk Polri dalam jumlah besar. Dalam beberapa tahun terakhir, alokasi anggaran untuk Polri terus mengalami peningkatan signifikan, baik untuk pengadaan teknologi, pemeliharaan keamanan, hingga dukungan operasional.
Namun, pertanyaan yang menggema di publik adalah: apa hasil nyata dari anggaran yang terus membengkak ini? Ketika kepercayaan publik terhadap kepolisian justru menurun, dan aparat pengawas internal bisa dibunuh oleh rekan sejawatnya sendiri, publik wajar mempertanyakan efektivitas penggunaan anggaran yang sedemikian besar.
Tambahan anggaran yang disetujui seharusnya digunakan untuk membangun sistem pengawasan internal yang lebih kuat, memperkuat pelatihan etik, serta meningkatkan profesionalisme penyidikan. Bukan justru dipakai untuk menambah peralatan taktis tanpa perbaikan mentalitas. Uang rakyat tidak seharusnya membiayai kekerasan oleh aparat terhadap aparat.
Kasus ini menjadi ujian moral dan kelembagaan bagi Polri. Sebagai institusi penegak hukum, kepolisian tidak hanya dituntut menindak pelaku kejahatan dari luar, tetapi juga membersihkan barisan dalamnya sendiri. Pemecatan terhadap dua perwira pelaku memang langkah awal yang tegas, tetapi belum cukup. Yang ditunggu publik adalah transparansi penyidikan, pembongkaran motif, dan keteladanan dalam penindakan.
Penanganan perkara ini harus menjadi contoh bahwa Polri tidak mentoleransi kekerasan, penyalahgunaan wewenang, maupun keterlibatan dalam jaringan gelap apa pun, termasuk narkotika. Jika tidak, maka institusi ini akan terus digerogoti dari dalam oleh virus loyalitas buta dan solidaritas semu.
Menagih Tanggung Jawab Negara
Negara tidak boleh abai terhadap kasus seperti ini. Di balik seragam, para anggota kepolisian adalah warga negara yang hak hidup dan rasa amannya dilindungi konstitusi. Kematian Brigadir Nurhadi adalah alarm keras bahwa sistem perlindungan internal di tubuh kepolisian sedang bermasalah.
Penuntasan kasus ini, termasuk pembongkaran motif dan kemungkinan jejaring kejahatan, adalah bentuk tanggung jawab negara kepada keluarga korban, masyarakat luas, dan integritas institusi penegak hukum. Jangan sampai kasus ini ditangani dengan pola lama: cepat dalam administrasi, lambat dalam substansi, dan diam dalam transparansi.
Ketika seorang pengawas internal dibungkam dengan kekerasan, dan pelakunya justru sesama aparat yang dibayar oleh negara, maka yang dipertaruhkan bukan hanya nyawa satu orang, melainkan legitimasi hukum itu sendiri. Tidak cukup hanya menambahkan anggaran. Yang dibutuhkan adalah keberanian untuk memutus jaringan kekerasan, menolak kompromi dalam penegakan hukum, dan membangun ulang kepercayaan dari dasar yang paling jujur.

 Desi Sommaliagustina
Desi Sommaliagustina