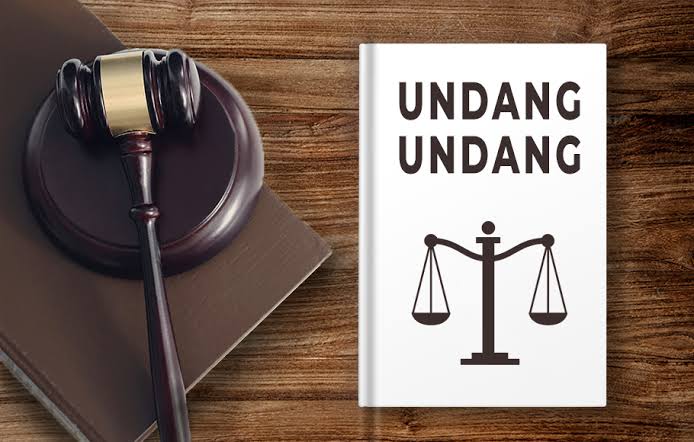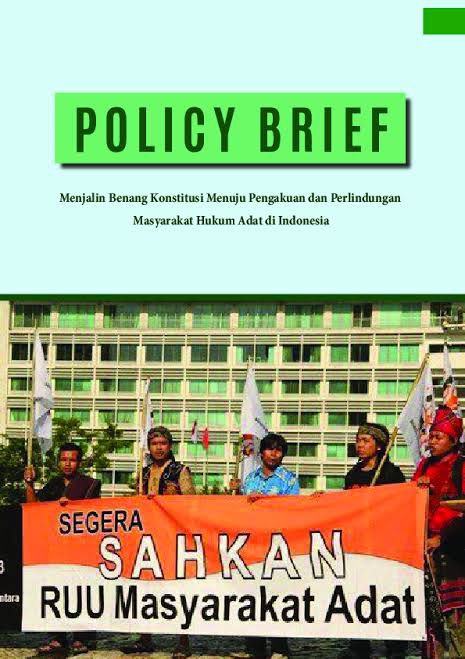Ketika hukum berhenti menjadi alat keadilan dan berubah menjadi alat penghukuman atas perbedaan pandangan dan kebijakan, maka sesungguhnya yang kita saksikan bukan lagi supremasi hukum, melainkan supremasi tafsir kekuasaan. Vonis 4,5 tahun penjara terhadap Thomas Trikasih Lembong, mantan Menteri Perdagangan, menjadi gambaran nyata betapa kaburnya garis batas antara diskresi kebijakan dan tindak pidana korupsi di Indonesia.
Hakim menjatuhkan vonis karena Tom Lembong memberikan izin impor gula kepada swasta, bukan kepada BUMN, sehingga dianggap merugikan negara sekitar Rp194 miliar. Namun, dari keseluruhan putusan, yang mencengangkan bukan hanya vonisnya, melainkan logika hukum yang dipakai: bahwa karena kebijakan itu “berorientasi kapitalistik” dan “tidak sejalan dengan semangat demokrasi ekonomi Pancasila,” maka layak dihukum sebagai tindak pidana korupsi. Padahal, hukum pidana tidak dibentuk untuk menilai ideologi, tetapi untuk mengadili perbuatan melawan hukum yang dilakukan dengan niat jahat (mens rea).
Kriminalisasi:Logika Pidana yang Menyesatkan
Apakah kebijakan impor oleh swasta itu salah? Mungkin. Apakah berdampak pada kerugian negara? Bisa jadi. Tapi apakah itu otomatis tindak pidana korupsi? Di sinilah letak kesesatan berpikir dalam putusan tersebut. Hukum pidana mensyaratkan pembuktian niat jahat dan keuntungan pribadi. Namun, hakim justru menyatakan bahwa Tom tidak menikmati hasil korupsi. Jadi, siapa yang korup? Apakah menteri yang menjalankan kewenangannya atas nama efisiensi, ataukah sistem yang membiarkan celah kebijakan dieksploitasi oleh pihak lain?
Hukum pidana bukan instrumen untuk membalas kebijakan yang tak populer atau yang tidak sesuai dengan preferensi ideologis penguasa. Jika logika ini dipertahankan, maka setiap menteri yang memilih pendekatan non-etatis bisa dianggap melawan semangat Pancasila dan dijebloskan ke penjara.
Kita tak sedang membela Tom Lembong secara pribadi. Tapi kita sedang membela prinsip dasar negara hukum: bahwa seseorang hanya dapat dihukum jika ada bukti niat jahat dan perbuatan melawan hukum. Jika tidak, maka vonis ini akan menjadi preseden yang menakutkan bagi para pengambil kebijakan.
Diskresi adalah jantung dari fungsi eksekutif. Tanpa diskresi, birokrasi akan lumpuh karena selalu menunggu kepastian hukum dalam setiap langkahnya. Namun, diskresi bukan tanpa batas. Jika terjadi penyimpangan administratif, maka mekanisme etik dan disipliner bisa diberlakukan. Tapi menjadikan penyimpangan kebijakan sebagai tindak pidana tanpa adanya niat jahat yang terbukti, adalah pelanggaran prinsip hukum pidana modern.
Menghukum seseorang karena “memperkaya orang lain” tanpa ia sendiri menikmati keuntungan itu, adalah pengaburan atas konsep dolus malus(niat jahat). Jika hal ini terus dibenarkan, maka negara akan berubah menjadi entitas yang membungkam diskursus kebijakan melalui palu hakim, bukan melalui debat publik yang sehat.
Ironisnya, dalam banyak kasus korupsi nyata yang melibatkan pejabat tinggi yang secara terang-terangan menikmati hasil korupsi, vonis yang dijatuhkan justru lebih ringan atau bahkan dibatalkan oleh Mahkamah Agung. Ini menunjukkan bahwa keadilan kita cenderung tajam ke arah yang salah, dan tumpul terhadap para perampok anggaran yang sesungguhnya.
Menggugat Jalan Keadilan dan Etika Politik yang Dipidana
Pertimbangan hakim bahwa kebijakan Tom Lembong “lebih kapitalistik dan tidak sejalan dengan semangat demokrasi ekonomi Pancasila” adalah masuk wilayah politik, bukan hukum. Pertarungan gagasan antara negara kesejahteraan (etatistik) dan ekonomi pasar (liberal) adalah wacana yang sah dalam demokrasi. Tidak ada satu tafsir tunggal tentang Pancasila yang bisa digunakan untuk menghukum pilihan kebijakan.
Jika ini dibiarkan, maka pengadilan akan menjadi forum ideologisasi hukum. Setiap menteri yang berpikiran berbeda dengan rezim penguasa dapat dijadikan pesakitan. Ini bukan demokrasi. Ini bukan negara hukum. Ini adalah otoritarianisme berjubah legalisme.
Kasus Tom Lembong menggugat kita semua: apakah kita masih percaya pada hukum sebagai pencari keadilan, ataukah kita telah menyerah pada hukum sebagai instrumen politik? Apakah kita masih ingin birokrasi berani mengambil keputusan berdasarkan data dan logika kebijakan, ataukah kita ingin mereka membisu dan menunggu karena takut dijerat hukum?
Jika kita membiarkan vonis semacam ini berlalu begitu saja, maka satu per satu pemikir kritis, birokrat progresif, dan teknokrat independen akan tersingkir. Negara akan dipenuhi oleh pejabat yang hanya bisa berkata “ya” kepada penguasa, bukan kepada kebenaran.
Sudah saatnya Mahkamah Agung mengevaluasi secara serius arah putusan semacam ini. Jika perlu, Mahkamah Konstitusi atau Dewan Etik Hakim bisa melakukan penyelidikan apakah dalam putusan ini telah terjadi pelanggaran asas-asas keadilan substantif.
Hukum untuk Siapa?
Vonis terhadap Tom Lembong menimbulkan pertanyaan besar: hukum kita sebenarnya untuk siapa? Apakah untuk melindungi kekuasaan? Ataukah untuk melayani keadilan bagi seluruh rakyat?
Jika suara intelektual seperti Lembong saja bisa dikriminalisasi, maka bayangkan nasib rakyat biasa. Apakah mereka masih bisa berharap pada hukum yang adil? Atau hukum kini hanyalah komoditas yang bisa dibeli dan diarahkan?
Kita harus menjawab pertanyaan ini dengan tegas. Jika hukum ingin tetap menjadi pilar negara, maka ia harus dikembalikan pada jalurnya: menjadi pelindung kebenaran, penjaga keadilan, dan pelayan rakyat—bukan alat represi.
Kita juga perlu bertanya, apakah kita masih berada dalam negara hukum yang rasional dan proporsional, atau telah terjebak dalam negara tafsir, di mana hukum bergantung pada selera penguasa dan keyakinan ideologis hakim? Keadilan bukanlah hasil dari siapa yang berkuasa, tapi dari keberanian menegakkan prinsip, sekalipun tidak populer.
Vonis terhadap Tom Lembong adalah lonceng peringatan. Bukan karena ia seorang mantan menteri. Tapi karena kita semua—akademisi, aktivis, birokrat, bahkan rakyat biasa—bisa jadi korban tafsir hukum yang sewenang-wenang. Dan ketika itu terjadi, siapa yang akan membela kita, jika hukum sudah lebih takut pada kuasa daripada pada kebenaran?

 Desi Sommaliagustina
Desi Sommaliagustina