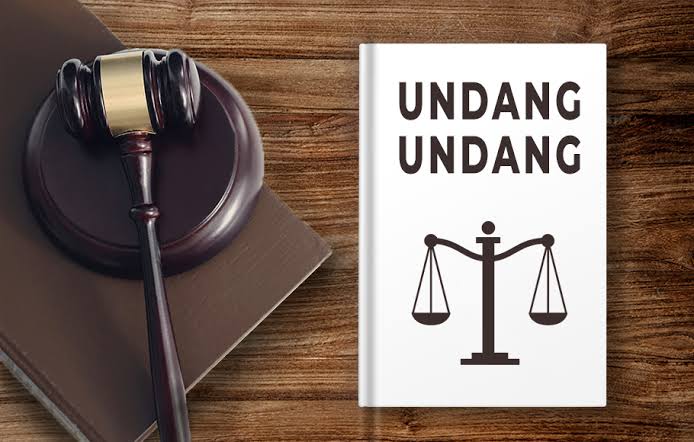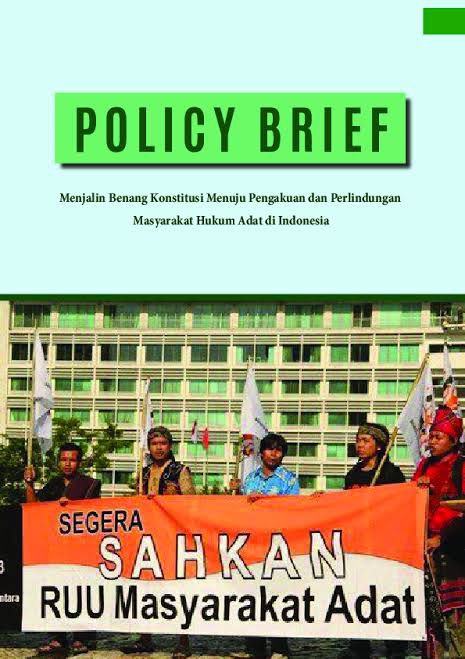Ketika Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dilahirkan, harapan besar diletakkan di pundak desa sebagai lokomotif pembangunan berbasis masyarakat. Tapi harapan itu seolah menjelma menjadi beban, ketika perangkat desa justru menjadikan badan usaha milik desa (BUMDes) sebagai sumber “uang lelah” yang tak punya dasar hukum jelas. Kasus Desa Tanah Merah di Kecamatan Siak Hulu, Kampar, Riau, menguak sisi kelam dari semangat otonomi desa yang kini menjelma menjadi arena kompromi kepentingan.
Alih-alih menjadi instrumen pemberdayaan masyarakat, BUMDes Tanah Merah justru digunakan untuk memberikan insentif kepada perangkat desa, tanpa landasan musyawarah dan tanpa transparansi publik. Dugaan praktik ini terungkap setelah beberapa warga mengeluhkan minimnya distribusi manfaat BUMDes kepada masyarakat. Permintaan audit mandiri dan pertanggungjawaban pun dijawab dengan sikap defensif oleh pihak desa. Warga tak diberi akses terhadap laporan keuangan. Laba usaha menguap entah ke mana.
Ketika Regulasi Diam
Permendesa PDTT Nomor 3 Tahun 2021 tentang BUMDes mengatur bahwa keuntungan BUMDes harus dikembalikan untuk kemanfaatan desa dan masyarakat. Tapi frasa “manfaat desa” terlalu kabur, dan sayangnya menjadi pembenaran bagi perangkat desa untuk ikut menikmati laba secara langsung. Tidak ada ketentuan eksplisit yang melarang atau membatasi pemberian insentif kepada perangkat desa dari hasil usaha BUMDes.
Dari aspek hukum tata kelola keuangan negara, praktik semacam ini menimbulkan benturan kepentingan. Dalam hukum administrasi negara, dikenal prinsip freies ermessen yang membatasi pejabat agar tidak menggunakan diskresinya untuk keuntungan pribadi. Perangkat desa adalah pejabat publik, dan mengambil keuntungan dari BUMDes tempat mereka punya kekuasaan pengawasan adalah bentuk penyalahgunaan wewenang secara sistemik.
“Ini sama saja dengan pengelola negara membayar dirinya sendiri dari laba usaha negara,” ujar pemerhati kebijakan publik, Desi Sommaliagustina, dalam sebuah diskusi tahun lalu. Ia menambahkan, “BUMDes itu untuk rakyat, bukan ATM birokrat lokal.”
Satu hal yang patut dicermati: banyak perangkat desa juga menjabat sebagai pengurus BUMDes. Dalam kasus Tanah Merah, sekretaris desa merangkap Direktur BUMDes. Situasi ini melahirkan praktik self-dealing—patut diduga perangkat menetapkan sendiri insentif yang akan mereka terima. Hingga adanya indikasi laporan fiktif dan maladministrasi yang terjadi.
Dalam laporan yang LKpIndonesia terima (2024), Dana Desa hingga Dana BUMDes banyak digunakan untuk kepentingan pribadi ataupun dipinjamkan kepada orang-orang yang tanda kutip memiliki kedekatan dengan pemerintahan desa. Yang tidak habis pikirnya BPD sendiri juga ikut melakukan pinjaman, entah apa dasar hukum mereka untuk meminjamkan dana ini?
Hal ini sudah kita sampaikan kepada Muhammad Amin, selaku Pj Kepala Desa Tanah Merah agar melakukan pengawasan hingga melakukan audit terkait hal ini belum lagi masalah maladministrasi dan laporan fiktif terkait penggunaan dana desa. Namun, sampai saat ini Pj Kepala Desa tidak merespon dan mengganggap hal ini hanyalah persoalan sepele.
LKpIndonesia sudah menghubunginya, tapi belum ada respon. “Jika dalam beberapa waktu masih juga tidak ada respon, kita akan datang langsung mempertanyakan soal ini. Jika mereka tidak mau terbuka, tidak menutup kemungkinan kita akan melakukan gugatan ke PTUN nantinya”
Bangaimana tidak, melalu data penelusuran kami dari LKpIndonesia, Pj ini pun sampai saat ini belum ada melaporkan LHKPN. Inilah cerminan pejabat publik yang tidak paham dengan tata kelola pemerintahan. Sebagai pemimpin seharusnya memberikan contoh, kalau pemimpin desanya saja seperti ini, mau dibawa kemana desa ini?
Padahal dalam hukum perusahaan, pemisahan antara pemilik, pengelola, dan pengawas adalah prinsip mendasar. Bahkan dalam perusahaan swasta pun, konflik kepentingan semacam ini harus dihindari. Tapi di desa, hal itu justru terjadi dalam struktur formal yang seolah dilegalkan.
Pasal 26 UU Desa mengatur bahwa kepala desa wajib melaksanakan prinsip tata pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Jika benar adanya perangkat desa menetapkan insentif untuk dirinya sendiri dari dana publik, maka itu bukan hanya pelanggaran etika, tapi juga dugaan pelanggaran administratif yang bisa diperiksa Inspektorat, APIP ataupun Lembaga Independen nantinya.
Logika Bisnis vs Logika Kekuasaan
BUMDes didirikan sebagai instrumen bisnis desa, bukan lembaga distribusi kesejahteraan bagi pejabatnya. Logika bisnis membutuhkan efisiensi, transparansi, dan orientasi pada pelayanan publik. Tapi saat dikelola oleh perangkat desa, logika ini sering digantikan oleh logika kekuasaan lokal.
Seorang tokoh masyarakat Tanah Merah yang enggan disebut namanya menyebut, “Tidak ada yang bisa menolak kalau kepala desa sudah bilang ‘ini untuk kesejahteraan perangkat.’ Warga takut, BPD diam.” Musyawarah desa hanya menjadi formalitas tahunan yang tak punya daya ikat, apalagi dalam urusan keuangan.
Masalah ini bukan hanya persoalan di Tanah Merah. Data Kementerian Desa menunjukkan bahwa dari 74.961 desa di Indonesia, lebih dari 40% BUMDes tidak aktif atau tidak menghasilkan laba. Dari yang aktif, sebagian besar tidak memiliki laporan keuangan publik. Ketika ada keuntungan, yang menikmati sering kali bukan warga desa biasa, melainkan perangkat yang duduk di kursi kekuasaan lokal.
Sudah saatnya tata kelola BUMDes direformasi secara menyeluruh. Pertama, perlu dikeluarkan regulasi eksplisit yang melarang pemberian insentif kepada perangkat desa dari laba BUMDes. Prinsip benturan kepentingan harus ditegakkan secara tegas dalam revisi Permendesa. BUMDes harus dikelola oleh profesional, bukan oleh perangkat yang punya konflik kepentingan.
Kedua, sistem pelaporan dan audit BUMDes harus terintegrasi secara digital, dengan pengawasan dari Badan Pemeriksa Keuangan Desa (BPKDes) dan partisipasi aktif masyarakat. Keterbukaan informasi publik harus dijamin, sebagaimana diamanatkan oleh UU Keterbukaan Informasi Publik Nomor 14 Tahun 2008.
Ketiga, sanksi administratif dan pidana perlu ditegakkan bagi kepala desa atau perangkat yang menyalahgunakan dana BUMDes untuk kepentingan pribadi. UU Tipikor secara jelas mengatur bahwa penyalahgunaan kewenangan yang merugikan keuangan negara dapat dijerat dengan pidana.
Terakhir, perlu ada sistem karier yang layak bagi perangkat desa. Insentif harus diberikan oleh negara melalui skema resmi, bukan melalui celah “bisnis desa.” Jika tidak, kita hanya sedang membangun feodalisme baru di bawah nama otonomi lokal.
Jika desa adalah masa depan Indonesia, maka kita harus memastikan masa depan itu tidak dibangun dari praktik kotor. Memberikan insentif kepada perangkat desa dari hasil usaha BUMDes tanpa transparansi adalah bentuk pengkhianatan terhadap tujuan pendirian BUMDes itu sendiri.
Kasus Tanah Merah harus menjadi alarm bagi pemerintah pusat dan daerah. Otonomi tanpa pengawasan akan melahirkan oligarki lokal yang tak kalah korup dari elit nasional. Dan jika desa gagal dikelola secara bersih, maka cita-cita membangun Indonesia dari pinggiran hanya akan menjadi slogan kosong.

 Andre Vetronius
Andre Vetronius