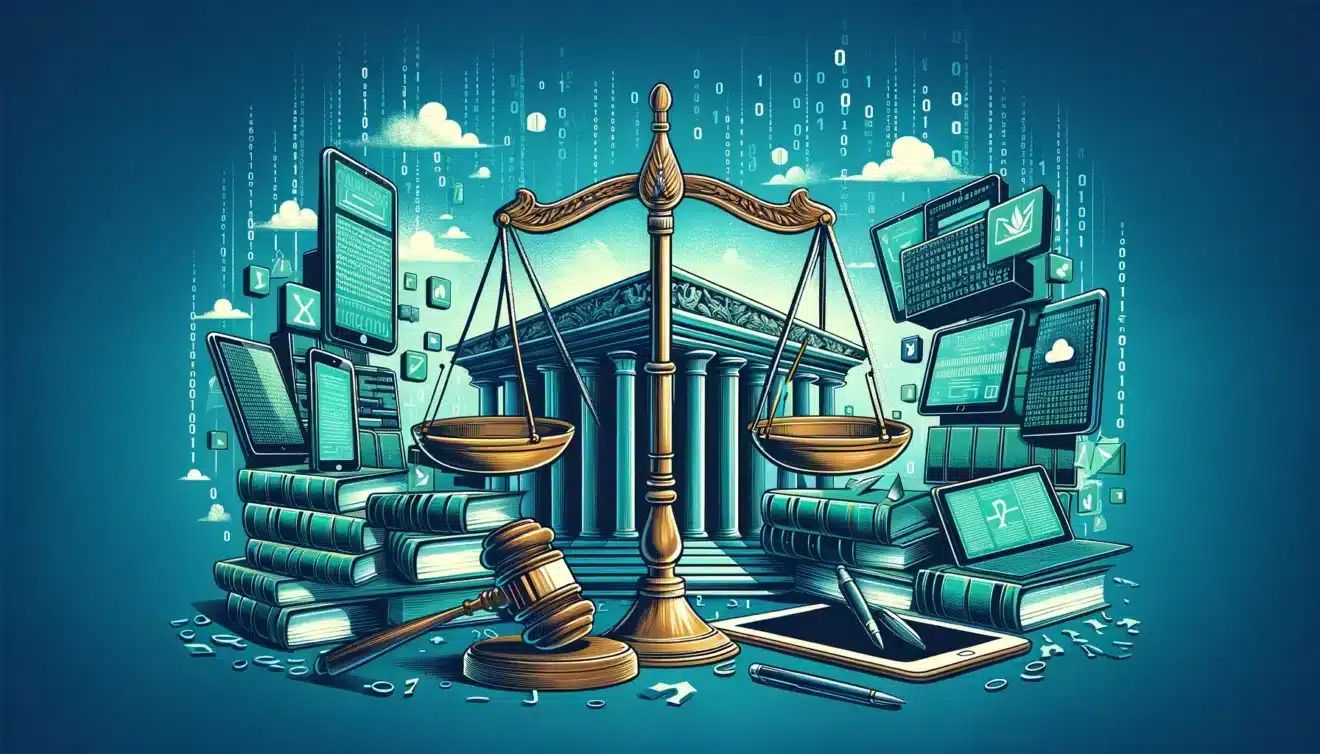Dalam sistem peradilan pidana Indonesia, perjalanan seseorang yang diduga melakukan tindak pidana tidak berhenti pada tahap penangkapan. Ada sejumlah tahapan status hukum yang harus dilalui, yaitu tersangka, terdakwa, dan terpidana. Ketiganya bukan sekadar istilah formal, melainkan representasi dari perkembangan proses hukum yang memiliki konsekuensi berbeda.
Kesalahpahaman sering muncul di ruang publik. Tak jarang masyarakat menganggap bahwa begitu seseorang berstatus tersangka, otomatis ia bersalah. Padahal, asas fundamental dalam hukum pidanaadalah presumption of innocence setiap orang dianggap tidak bersalah sampai ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Untuk itu, mari telaah secara lebih rinci perbedaan ketiga status ini.
1. Tersangka: Awal Mula Perjalanan Hukum
Definisi tersangka termuat dalam Pasal 1 angka 14 KUHAP, yaitu seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana.
Penetapan status tersangka muncul setelah aparat penegak hukum menemukan bukti awal yang cukup, misalnya keterangan saksi, dokumen, atau barang bukti lain. Namun, penting diingat: status tersangka bukan vonis bersalah. Ia masih berada di tahap penyidikan, di mana dugaan harus diuji kebenarannya.
Hak-hak tersangka yang dijamin undang-undang antara lain:
-
Didampingi penasihat hukum sejak pemeriksaan awal.
-
Tidak boleh diperlakukan secara tidak manusiawi.
-
Mendapat kesempatan untuk memberikan keterangan atau memilih diam.
Dengan kata lain, tersangka adalah gerbang awal menuju proses pidana, bukan penentu akhir.
2. Terdakwa: Proses Beralih ke Meja Hijau
Setelah penyidikan selesai dan berkas perkara dinyatakan lengkap (P-21), jaksa penuntut umum akan melimpahkan perkara ke pengadilan. Sejak saat itu, status hukum berubah menjadi terdakwa.
Menurut Pasal 1 angka 15 KUHAP, terdakwa adalah orang yang didakwa melakukan tindak pidana dan diperiksa di persidangan. Pada tahap ini, arena proses hukum berpindah dari penyidik ke pengadilan.
Hak-hak terdakwa semakin krusial, di antaranya:
-
Menyampaikan pembelaan (pledoi) melalui pengacara.
-
Menghadirkan saksi atau bukti yang meringankan.
-
Mengajukan upaya hukum apabila tidak menerima putusan (banding/kasasi).
Tahap terdakwa adalah inti dari asas fair trial (peradilan yang adil), karena di sinilah dakwaan jaksa diuji di hadapan hakim yang independen.
3. Terpidana: Saat Putusan Menjadi Final
Status terakhir adalah terpidana, yang diatur dalam Pasal 1 angka 32 KUHAP. Terpidana adalah orang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (inkracht).
Jika putusan hakim sudah final baik karena tidak diajukan banding/kasasi, maupun karena upaya hukum telah ditolak maka seseorang resmi berstatus terpidana. Pada tahap ini, fokusnya adalah pelaksanaan pidana, misalnya penjara, denda, atau pidana lain sesuai amar putusan.
Walaupun berstatus terpidana, hak-hak tertentu tetap dijamin, seperti:
-
Memperoleh remisi atau pengurangan masa pidana.
-
Mengajukan grasi kepada Presiden.
-
Menggunakan upaya luar biasa berupa Peninjauan Kembali (PK).
Hal ini menunjukkan bahwa hukum Indonesia tetap memberikan ruang bagi kemanusiaan dan perbaikan, bahkan setelah vonis dijatuhkan.
Mengapa Penting Memahami Distingsi Ini?
Perbedaan ketiga status bukan sekadar teknis hukum, melainkan bagian dari perlindungan hak asasi manusia. Salah kaprah dalam memahami istilah dapat menimbulkan stigma sosial yang merugikan, terutama bagi orang yang baru berstatus tersangka.
Asas praduga tak bersalah sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 8 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menuntut kita untuk menahan diri agar tidak menjatuhkan vonis sebelum hakim melakukannya.
Kesimpulannya :
-
Tersangka → individu yang diduga melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan.
-
Terdakwa → individu yang diajukan ke pengadilan untuk diuji dakwaannya.
-
Terpidana → individu yang dinyatakan bersalah oleh pengadilan melalui putusan yang final.
Dengan memahami alur ini, masyarakat dapat lebih arif menilai berita hukum dan tidak serta-merta menyamakan tersangka dengan pelaku kejahatan yang sudah terbukti bersalah. Hukum pidana Indonesia menegaskan bahwa setiap tahap adalah proses menuju keadilan yang harus dijalani dengan prinsip objektivitas dan perlindungan hak.
Referensi :
-
Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (UU No. 8 Tahun 1981).
-
UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
-
UUD 1945 Pasal 14 (tentang grasi).

 Imroah Qurotul Aini
Imroah Qurotul Aini