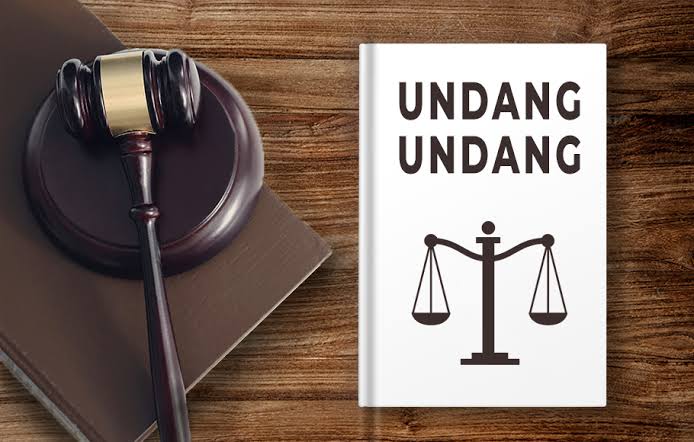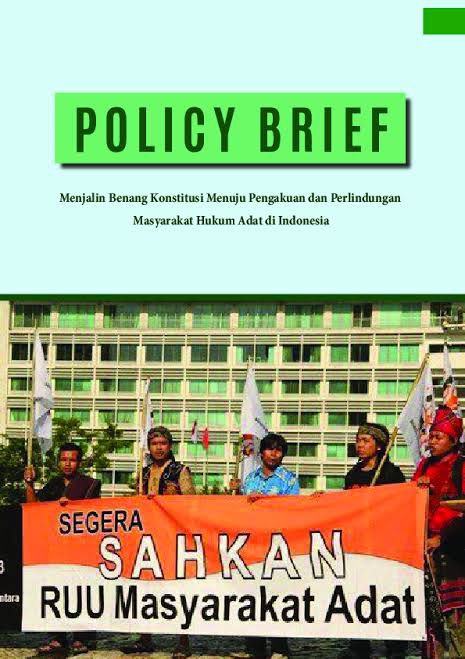Di tengah berbagai upaya pemerintah memperluas akses pendidikan yang inklusif dan bebas diskriminasi, masih ada praktik yang justru mencederai semangat itu. Salah satunya adalah kebiasaan sejumlah sekolah negeri di Padang yang menjual seragam sekolah langsung kepada orang tua murid—baik melalui koperasi sekolah maupun kerja sama terselubung dengan vendor tertentu.
Praktik ini bukan saja keliru secara etis, melainkan juga melanggar hukum. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan secara tegas melarang pendidik, tenaga kependidikan, anggota komite sekolah, maupun lembaga pendidikan menjual bahan ajar, seragam, atau atribut pendidikan lainnya secara langsung maupun tidak langsung. Larangan ini ditegaskan kembali dalam Permendikbud Nomor 50 Tahun 2022 tentang Pakaian Seragam Sekolah, yang menyatakan bahwa sekolah tidak boleh mewajibkan siswa membeli seragam baru sebagai syarat untuk bersekolah, apalagi mengarahkan pembelian ke pihak tertentu.
Namun, pada kenyataannya, sejumlah orang tua murid hingga pedagang penjual seragam sekolah di Padang melaporkan adanya pemaksaan pembelian seragam dari sekolah dengan harga dan desain yang telah ditentukan, bahkan tanpa ruang negosiasi. Tidak sedikit yang harus merogoh kocek ratusan ribu hingga jutaan rupiah hanya untuk memenuhi permintaan ini. Dalih bahwa pengadaan dilakukan oleh koperasi sekolah atau komite, sama sekali tidak membebaskan pihak sekolah dari tanggung jawab hukum. Sebab, pengelolaan koperasi dan komite berada dalam lingkup kendali institusi pendidikan itu sendiri.
Lebih jauh, praktik semacam ini berisiko memunculkan monopoli, konflik kepentingan, hingga potensi pungutan liar. Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Sumatera Barat telah menyampaikan temuan bahwa praktik tersebut kerap melibatkan kerja sama tersembunyi dengan pihak ketiga yang “menyetorkan” keuntungan kepada pihak internal sekolah. Bahkan disebutkan, nilai transaksi pengadaan seragam di satu sekolah bisa mencapai Rp600–700 juta per tahun. Jika ini bukan penyimpangan, lalu apa?
Maladministrasi dan Potensi Pidana
Dalam konteks hukum administrasi, praktik penjualan seragam oleh sekolah dapat dikategorikan sebagai bentuk maladministrasi, yakni penyimpangan prosedur dan pelanggaran kewenangan yang merugikan masyarakat. Ombudsman sebagai lembaga pengawas pelayanan publik memiliki kewenangan merekomendasikan sanksi terhadap sekolah, kepala sekolah, dan bahkan dinas pendidikan apabila terbukti lalai mengawasi pelanggaran.
Lebih serius lagi, jika ditemukan unsur pemaksaan, keuntungan pribadi, atau mark-up harga seragam, maka pelanggaran ini dapat menjalar ke ranah pidana. Ketentuan dalam UU Tipikor, khususnya Pasal 12 e dan Pasal 5 ayat (2), dapat digunakan untuk menjerat oknum yang menyalahgunakan jabatan untuk mendapatkan keuntungan dari pengadaan barang.
Pertanyaan mendasar yang harus kita ajukan: apakah pendidikan di sekolah negeri benar-benar gratis dan adil, jika masih ada praktik penjualan seragam yang memaksa dan membebani orang tua?
Keberadaan koperasi sekolah memang bertujuan mulia untuk mendukung kebutuhan peserta didik. Namun, ketika koperasi berubah menjadi alat komersialisasi yang justru menyuburkan praktik eksklusivisme dan mengabaikan hak orang tua untuk memilih alternatif yang lebih terjangkau, maka esensi keadilannya lenyap.
Dalam konteks keadilan sosial, membebani orang tua dengan pembelian seragam dari saluran tertentu berpotensi memperlebar kesenjangan. Tidak semua orang tua mampu membayar seragam yang ditentukan sekolah, terutama di tengah kondisi ekonomi yang sulit. Ini bertentangan dengan semangat konstitusi yang menjamin akses pendidikan tanpa diskriminasi ekonomi.
Penegakan Aturan dan Jalan Keluar
Langkah Wali Kota Padang dan Ombudsman Sumbar yang melakukan tindakan pelarangan melalui surat edaran terkait penjualan seragam oleh sekolah negeri merupakan langkah yang sangat tepat. Namun, surat edaran saja tidak cukup. Diperlukan pengawasan ketat dan sanksi administratif yang nyata terhadap pelanggaran yang terbukti. Di sisi lain, Dinas Pendidikan harus memberikan panduan alternatif yang mendorong kolaborasi dengan penjahit lokal, sistem subsidi silang bagi siswa tidak mampu, dan ruang partisipasi bagi orang tua dalam memilih penyedia seragam.
Yang tidak kalah penting, sekolah harus dikembalikan ke fungsi dasarnya: sebagai institusi layanan publik yang netral, terbuka, dan berorientasi pada hak anak atas pendidikan, bukan sebagai lembaga semi-komersial yang memanfaatkan kebutuhan dasar siswa untuk kepentingan segelintir pihak.
Sudah waktunya kita membenahi tata kelola pendidikan secara menyeluruh, mulai dari hal yang paling mendasar seperti pengadaan seragam. Pendidikan adalah hak, bukan ladang untuk mencari laba. Jika kita tak berani menertibkan praktik seperti ini, maka jargon “pendidikan gratis” hanya akan menjadi utopia yang terus dipertanyakan maknanya di tengah kenyataan yang pahit.

 Desi Sommaliagustina
Desi Sommaliagustina