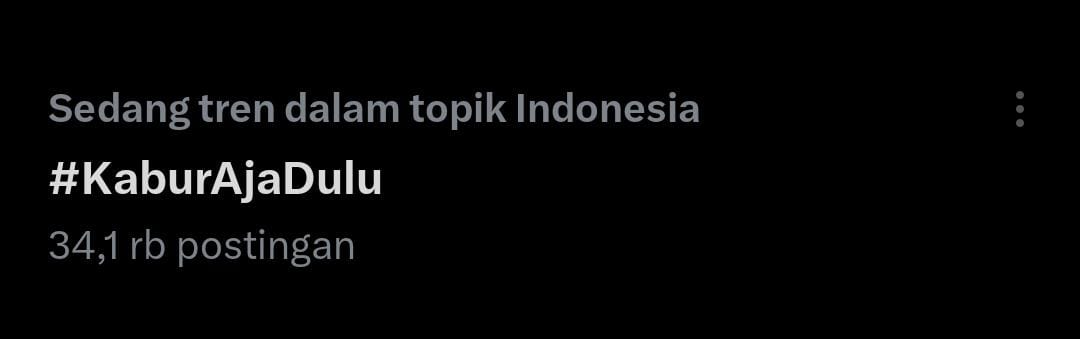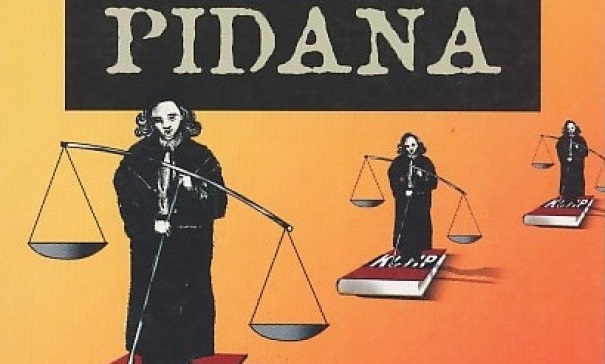Di tengah riuhnya dinamika geopolitik dan perang dagang global yang melibatkan negara-negara adidaya, Indonesia berdiri di persimpangan jalan yang menuntut kebijakan cermat dan langkah strategis. Sektor perdagangan elektronik (e-commerce), yang selama satu dekade terakhir tumbuh pesat di tanah air, kini menghadapi tantangan besar akibat turbulensi pasar global. Persaingan tidak lagi semata-mata antar pelaku usaha lokal, tetapi antara rezim hukum nasional dengan dominasi platform asing, serta antara kedaulatan negara dan ekspansi kapital digital global.
Indonesia dalam Perdagangan Digital
Perang tarif antara Amerika Serikat dan China yang tak kunjung reda sejak Donald Trump mengumumkan kenaikan tarif. Hal ini semakin diperparah dengan langkah-langkah proteksionis dari Uni Eropa, telah mengguncang sistem perdagangan dunia. Dunia kini memasuki fase deglobalisasi parsial, di mana negara-negara mulai membangun benteng tarif dan hambatan non-tarif untuk melindungi industri dalam negerinya. Di tengah kondisi ini, sektor perdagangan digital justru menjadi medan kompetisi utama, sebab ia bergerak melampaui batas-batas teritorial, bahkan melewati kontrol konvensional negara.
Indonesia sebagai pasar digital terbesar di Asia Tenggara, dengan populasi lebih dari 270 juta jiwa dan tingkat adopsi internet yang tinggi, tentu menjadi incaran kapital global. Menurut data e-Conomy SEA 2023 oleh Google, Temasek, dan Bain & Company, nilai ekonomi digital Indonesia mencapai US$82 miliar pada 2023 dan diproyeksikan menembus US$109 miliar pada 2025. Dari jumlah tersebut, e-commerce menyumbang porsi terbesar, mencapai hampir 70 persen.
Namun pertumbuhan pesat ini menyisakan kekhawatiran: apakah pertumbuhan itu dinikmati secara adil oleh pelaku usaha lokal? Apakah negara memiliki kendali penuh atas arus data, transaksi, dan distribusi keuntungan? Atau justru Indonesia hanya menjadi “lahan terbuka” bagi ekspansi raksasa platform digital seperti Amazon, Alibaba, dan TikTok yang memonopoli algoritma, logistik, dan sistem pembayaran?
Indonesia sejatinya telah memiliki kerangka hukum untuk mengatur transaksi digital, seperti UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dan PP No. 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE). Namun, regulasi ini belum cukup menjawab kompleksitas transaksi lintas batas, pelindungan konsumen digital, hingga praktik predatory pricing oleh platform asing.
Misalnya, dalam kasus TikTok Shop yang sempat ditutup sementara oleh Pemerintah Indonesia pada akhir 2023 karena dinilai mengganggu ekosistem UMKM lokal, ditemukan banyak celah hukum yang belum tertutup Platform global bisa mengakali larangan melalui afiliasi dengan e-commerce lokal, atau menggeser operasi ke yurisdiksi lain dengan tetap menarget pasar Indonesia.
Di sinilah muncul pertanyaan mendasar: apakah regulasi kita cukup kuat menegakkan prinsip equal playing field? Apakah pelaku usaha lokal dan asing tunduk pada kewajiban yang sama, termasuk soal perpajakan, pelindungan data, dan penyelesaian sengketa?
Kedaulatan Digital di Ujung Tanduk
Dalam konteks ini, kedaulatan digital menjadi isu sentral. Menurut Shoshana Zuboff dalam bukunya The Age of Surveillance Capitalism, negara-negara yang tidak mengendalikan data dan algoritma akan menjadi koloni digital dari platform raksasa. Kedaulatan bukan hanya soal batas wilayah, tapi tentang siapa yang menguasai arus informasi, pola konsumsi, dan struktur pasar.
Indonesia, seperti banyak negara berkembang lainnya, masih belum sepenuhnya berdaulat secara digital. Banyak data konsumen Indonesia disimpan di luar negeri, tunduk pada yurisdiksi asing, dan tidak dapat diakses oleh regulator nasional. Bahkan dalam sengketa konsumen atau pelanggaran iklan digital, platform asing sering kali “kebal” dari mekanisme hukum lokal.
Indonesia tak bisa berdiri sendiri menghadapi dominasi pasar digital global. Diplomasi ekonomi digital harus menjadi prioritas. Dalam forum-forum seperti ASEAN, G20, hingga WTO, Indonesia harus mendorong kesetaraan perlakuan dalam transaksi digital, termasuk mekanisme penyelesaian sengketa yang adil dan perlindungan terhadap UMKM lokal.
ASEAN dapat menjadi titik tolak. Saat ini, ASEAN telah memiliki Framework Agreement on E-Commerce (2019) yang mengatur prinsip-prinsip umum, namun belum mengikat secara operasional. Indonesia perlu mendorong pembentukan ASEAN Digital Trade Dispute Resolution System dan harmonisasi perlindungan konsumen lintas negara.
Pada saat yang sama, reformasi hukum nasional juga tak bisa ditunda. Revisi UU ITE dan penyusunan UU Perlindungan Data Pribadi (yang baru disahkan tahun 2022) harus diikuti dengan penguatan lembaga pengawas digital economy yang mandiri dan adaptif.
Ekonomi Digital Tanpa Keadilan adalah Kolonialisme Baru
Pertumbuhan ekonomi digital harus inklusif dan adil. Jika tidak, yang tumbuh hanyalah dominasi segelintir perusahaan besar dengan pola monopoli yang memperkecil ruang hidup pelaku kecil. Indonesia perlu belajar dari Uni Eropa yang berani menerapkan Digital Markets Act dan Digital Services Act untuk membatasi dominasi platform besar dan memastikan transparansi algoritma.
Sebagaimana dikatakan oleh Joseph Stiglitz, peraih Nobel Ekonomi, “Market fundamentalism, when applied to digital platforms, leads to the concentration of power and the erosion of democracy.” Maka, pasar digital yang dibiarkan tanpa regulasi progresif akan menciptakan bentuk kolonialisme baru — kolonialisme algoritma.
Di tengah perang pasar global, Indonesia tidak boleh bersikap pasif. Perdagangan elektronik bukan sekadar tren ekonomi, tapi arena baru perebutan kedaulatan dan keadilan. Negara harus hadir dengan visi digital yang kuat: sebagai pengatur yang progresif, pelindung konsumen, fasilitator pelaku lokal, dan aktor diplomasi global.
Ekonomi digital harus menjadi ladang kemakmuran bersama, bukan hanya keuntungan segelintir. Dalam dunia yang kian tanpa batas, justru batas hukum dan batas keadilanlah yang harus ditegakkan.

 Desi Sommaliagustina
Desi Sommaliagustina