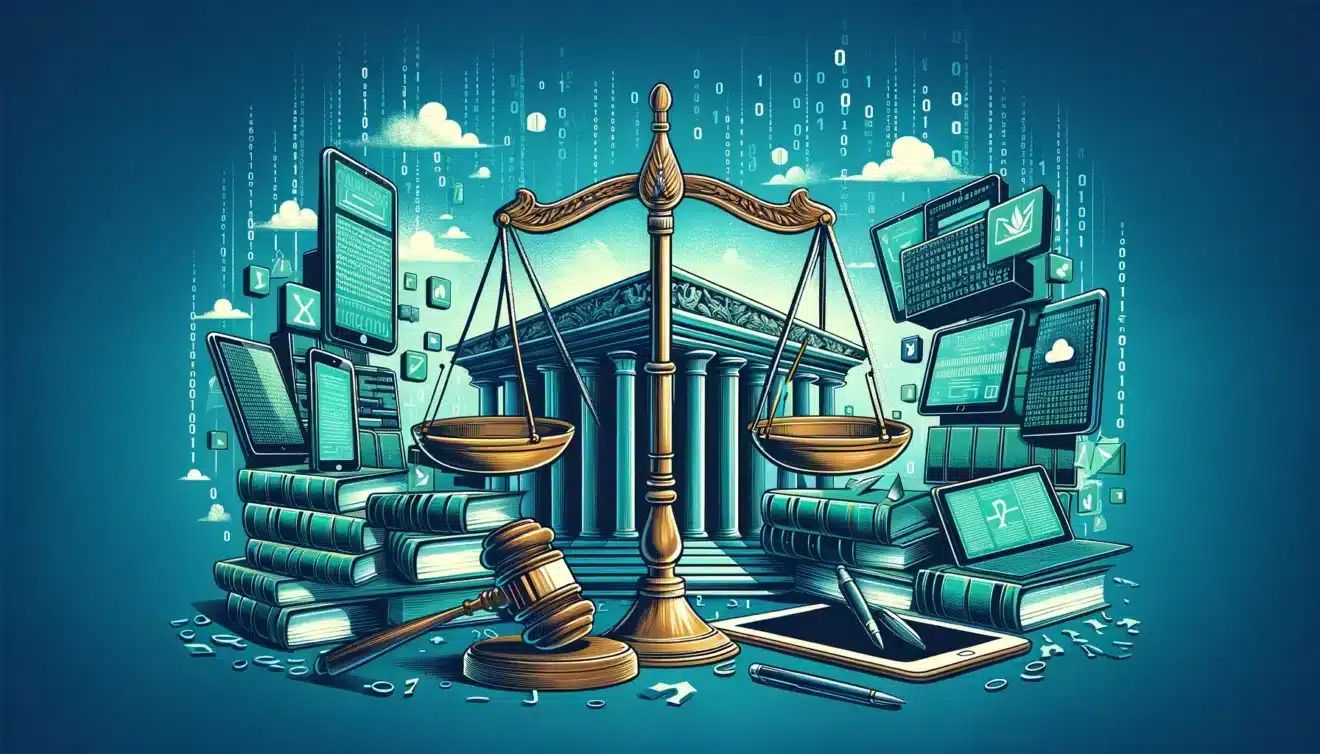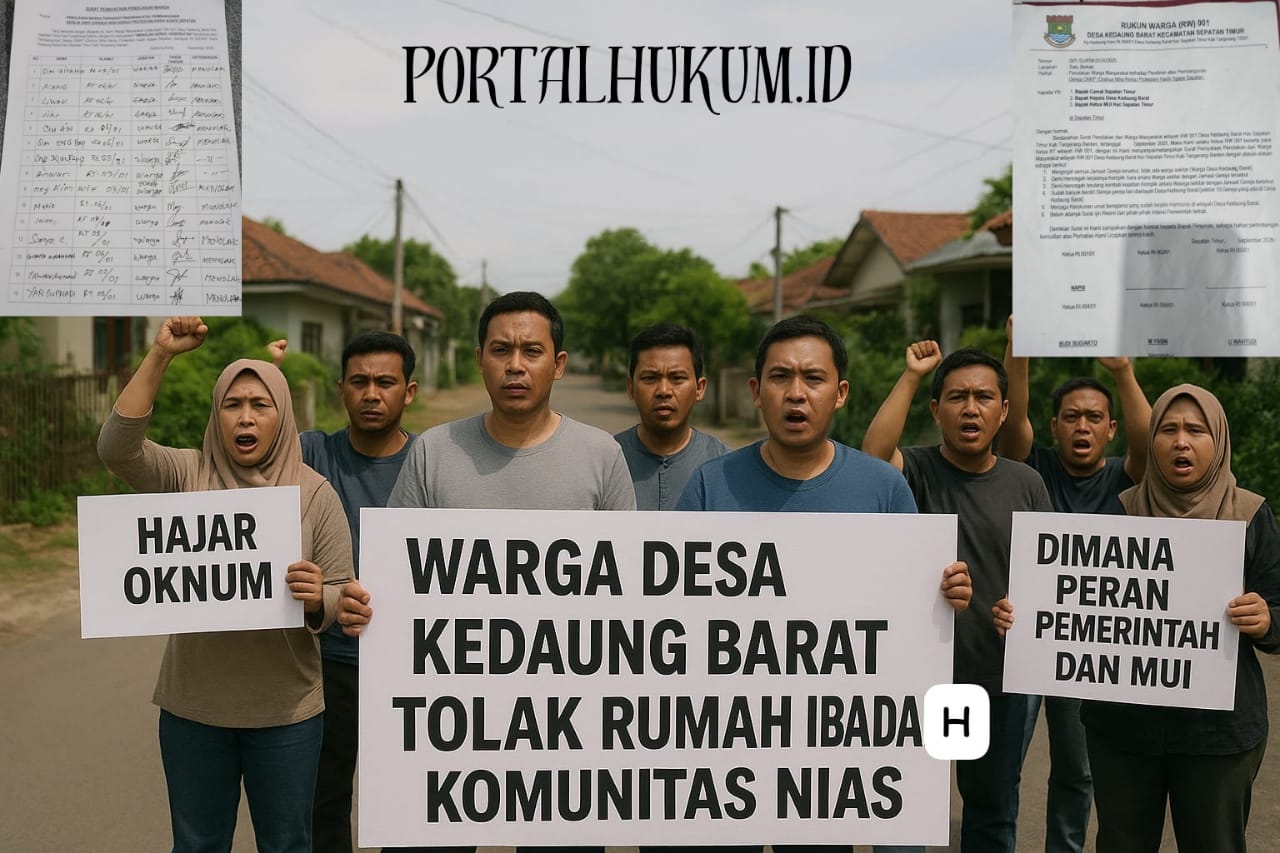Dunia pendidikan Indonesia tengah berada di titik persimpangan yang rumit. Antara semangat mencerdaskan kehidupan bangsa dan keharusan menegakkan hukum, dunia pendidikan kini menghadapi tantangan multidimensi: dari ruang kelas hingga ruang sidang. Fenomena hukum yang melingkupi sekolah, guru, bahkan siswa, mencerminkan pergeseran besar dalam cara kita memahami makna mendidik dan dididik.
Kasus terbaru di SMAN Cimarga, Lebak, Banten, menjadi contoh nyata. Seorang kepala sekolah dilaporkan ke polisi setelah menampar murid yang ketahuan merokok di lingkungan sekolah. Publik pun terbelah dua: sebagian mendukung langkah kepala sekolah sebagai bentuk pendisiplinan moral, sebagian lain mengecamnya sebagai pelanggaran terhadap Undang-Undang Perlindungan Anak. Dalam situasi ini, pendidikan tampak gamang: menegakkan disiplin dianggap salah, tetapi membiarkan perilaku menyimpang pun tak bisa dibenarkan.
Kasus di Lebak bukan satu-satunya. Beberapa tahun terakhir, banyak pendidik tersandung masalah hukum karena tindakan yang dianggap melanggar batas. Padahal, di masa lalu, teguran keras atau hukuman ringan adalah bagian dari proses pembentukan karakter. Namun, kini paradigma itu berubah. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan Permendikbudristek Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Satuan Pendidikan menegaskan: kekerasan fisik, verbal, maupun psikis terhadap siswa tidak dapat ditoleransi dalam bentuk apa pun.
Tujuan regulasi ini sebenarnya mulia—melindungi anak dari kekerasan di lingkungan pendidikan. Namun, di sisi lain, muncul problematika baru: batas antara mendisiplinkan dan melakukan kekerasan menjadi kabur. Banyak guru akhirnya memilih bersikap pasif, takut mengambil tindakan tegas karena khawatir berhadapan dengan hukum. Ruang pendidikan pun kehilangan ketegasan moralnya.
Krisis Otoritas Guru
Kondisi ini memperlihatkan krisis otoritas guru yang semakin dalam. Dulu, guru adalah figur moral, teladan yang dihormati. Kini, otoritas itu digerus oleh arus digitalisasi dan perubahan sosial. Teguran guru bisa direkam, dipotong konteksnya, lalu diunggah ke media sosial dan menjadi “bahan pengadilan publik”. Tak jarang, sebelum hukum bicara, dunia maya sudah menjatuhkan vonis.
Ironisnya, perlindungan hukum bagi guru masih belum seimbang. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 memang menjamin perlindungan profesi guru, tetapi implementasinya lemah. Banyak tenaga pendidik tidak paham bagaimana menghadapi laporan hukum, tidak tahu hak-hak mereka saat menjadi terlapor, atau bahkan tidak memiliki pendamping hukum yang memadai. Akibatnya, niat mendidik justru bisa berbalik menjadi jerat pidana.
Masalah hukum dalam pendidikan tak hanya terjadi di ruang kelas. Pada level kebijakan, pendidikan juga kerap tersandera oleh tarik-menarik politik. Setiap pergantian menteri hampir selalu diikuti perubahan kurikulum: dari KTSP, Kurikulum 2013, hingga kini Kurikulum Merdeka. Perubahan cepat ini seringkali tidak disertai kesiapan infrastruktur, pelatihan guru, atau konsistensi evaluasi.
Kurikulum seolah menjadi alat politik, bukan instrumen pembelajaran. Akibatnya, sekolah dan guru dipaksa menyesuaikan diri dengan sistem baru yang belum matang. Regulasi pendidikan yang seharusnya memihak peserta didik justru sering menjadi alat legitimasi kekuasaan birokrasi.
Fenomena penyimpangan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di beberapa daerah juga menunjukkan bahwa pendidikan telah masuk dalam pusaran hukum korupsi. Alih-alih meningkatkan mutu pendidikan, dana tersebut justru menjadi sumber masalah baru yang menodai integritas dunia pendidikan.
Pendidikan, Hukum, dan Etika
Pusaran hukum pendidikan tidak hanya berbicara soal regulasi, tetapi juga keadilan akses. Di banyak daerah, ribuan sekolah rusak parah, guru honorer belum mendapat kepastian status, dan fasilitas belajar minim. Namun di sisi lain, proyek-proyek digitalisasi sekolah bernilai miliaran rupiah terus digulirkan tanpa evaluasi transparan.
Pasal 31 UUD 1945 secara jelas menyebutkan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan. Namun, hak itu masih bersifat simbolik di banyak daerah. Ketika anak-anak di pelosok harus menyeberangi sungai untuk sekolah, sementara pejabat pendidikan sibuk berkasus di KPK, kita patut bertanya: di manakah keadilan pendidikan itu berada?
Hukum seharusnya melindungi nilai-nilai pendidikan, bukan membelenggunya. Pendidikan tanpa etika akan kehilangan arah, dan hukum tanpa nilai kemanusiaan akan menjadi kaku dan menakutkan. Di sinilah pentingnya keseimbangan antara ketiganya.
Guru perlu memahami bahwa mendidik bukan berarti berhak melakukan kekerasan, namun juga tidak boleh kehilangan kewibawaan. Sebaliknya, negara harus hadir memberikan perlindungan hukum yang adil bagi para pendidik yang bertindak berdasarkan etika profesi. Aparat penegak hukum pun mesti memahami konteks pendidikan sebelum mengambil langkah hukum yang bisa merusak iklim belajar.
Permendikbudristek Nomor 46 Tahun 2023 sebenarnya sudah mencoba menjembatani hal ini dengan konsep restorative justice di lingkungan pendidikan. Pendekatan ini memungkinkan penyelesaian kasus kekerasan atau pelanggaran di sekolah dilakukan secara edukatif dan dialogis, bukan semata represif. Prinsip ini layak diperkuat agar pendidikan tidak menjadi korban dari ketakutan hukum yang berlebihan.
Pendidikan yang ideal adalah pendidikan yang menumbuhkan keadilan, bukan ketakutan. Dalam konteks hukum, sekolah seharusnya menjadi tempat pertama bagi generasi muda belajar tentang kejujuran, tanggung jawab, dan moral publik. Hukum perlu dipahami sebagai sarana pembelajaran etis, bukan ancaman.
Ketika guru takut mendidik karena khawatir dilaporkan, ketika kepala sekolah lebih sibuk mengurus perkara hukum daripada mengurus murid, maka yang sebenarnya rusak bukan hanya sistem pendidikan, tetapi juga nurani kebangsaan.
Sudah saatnya pemerintah, lembaga hukum, dan masyarakat bersama-sama menegakkan keseimbangan antara disiplin, kemanusiaan, dan keadilan. Sebab, tanpa keadilan dalam pendidikan, hukum akan kehilangan jiwa, dan tanpa hukum yang beretika, pendidikan hanya akan menjadi formalitas.
Di tengah pusaran hukum yang melingkupi dunia pendidikan, marilah kita kembali pada hakikatnya: mendidik adalah tindakan moral, bukan sekadar tugas administratif. Pendidikan bukan ruang ketakutan, melainkan tempat di mana hukum, akal, dan hati nurani berjalan beriringan demi masa depan bangsa.

 Desi Sommaliagustina
Desi Sommaliagustina