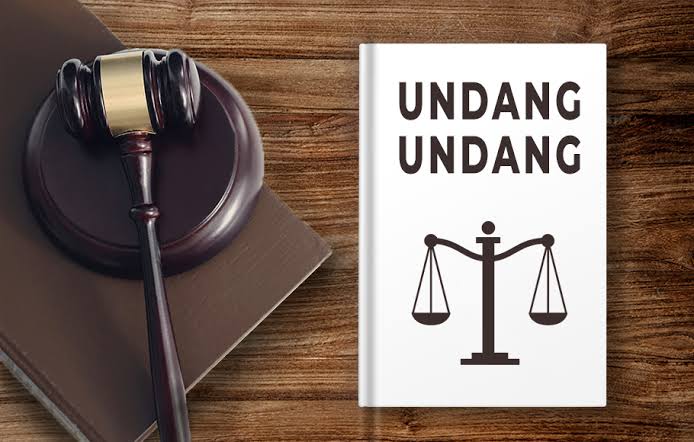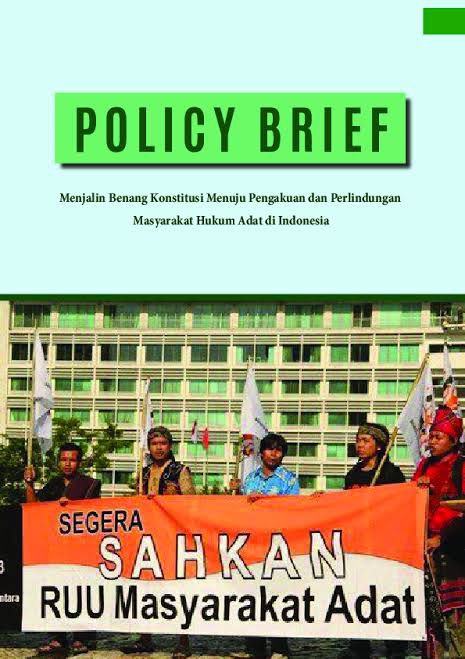Program makan bergizi gratis yang digadang-gadang sebagai program unggulan kebijakan sosial kini berada di ujung tanduk. Janji manis yang semula dimaknai sebagai bentuk keberpihakan pada anak-anak dari keluarga kurang mampu, justru mulai bertransformasi menjadi proyek bermasalah yang menyisakan lebih banyak tanya daripada jawab.
Jika tujuan program ini adalah menciptakan generasi sehat dan cerdas, realitas di lapangan justru menunjukkan hal sebaliknya: anak-anak menolak makanan, vendor menjerit karena belum dibayar, dan sejumlah siswa harus dilarikan ke Puskesmas akibat dugaan keracunan. Pertanyaannya sederhana: mau dibawa ke mana program ini?
Secara normatif, tidak ada yang salah dari gagasan makan bergizi gratis. Pasal 28C UUD 1945 menyatakan bahwa setiap warga negara berhak mengembangkan dirinya melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya. Dalam konteks ini, asupan gizi yang memadai adalah hak dasar setiap anak.
Kebijakan publik bukan sekadar niat. Ia adalah soal desain, eksekusi, dan evaluasi yang berkelanjutan. Di banyak daerah, sekolah-sekolah justru mengeluhkan rendahnya kualitas makanan. Menu yang tidak sesuai dengan selera lokal, penyimpanan yang tidak higienis, dan pengolahan yang terburu-buru membuat siswa enggan menyentuhnya. Bukankah makanan sehat seharusnya juga menggugah selera?
Program ini juga menunjukkan kelemahan sistemik dalam kontrak dan pembiayaan. Banyak penyedia jasa katering lokal yang belum menerima pembayaran selama berbulan-bulan. Mereka yang semula diharapkan menjadi roda penggerak ekonomi rakyat, justru terjebak dalam arus kas yang kolaps. Ironisnya, negara sebagai pihak yang mengatur kontrak justru luput memberi kepastian.
Padahal, dalam prinsip dasar hukum kontrak, pacta sunt servanda (janji harus ditepati) bukanlah jargon, melainkan pilar kepercayaan. Ketika pemerintah gagal membayar tepat waktu, itu bukan hanya soal utang, tetapi bentuk pelanggaran terhadap kepercayaan publik.
Selain itu, kasus keracunan massal di sejumlah sekolah menambah daftar kegagalan program ini. Dari hasil investigasi dinas kesehatan, penyebabnya adalah makanan yang sudah terkontaminasi bakteri. Ini bukan sekadar human error, tetapi bukti lemahnya kontrol kualitas dan pengawasan di lapangan.
Anak-anak yang semestinya dilindungi, justru menjadi korban dari ambisi kebijakan yang terburu-buru. Bukankah asas kehati-hatian adalah prinsip penting dalam setiap kebijakan yang menyangkut keselamatan publik?
Banyak pihak menduga bahwa program ini lebih diarahkan untuk pencitraan politik ketimbang tujuan substansial. Janji populis ini, tanpa didukung kesiapan struktur pelaksana, justru menjadi bumerang. Ketika kritik mulai bermunculan, respons pemerintah pun cenderung defensif. Tidak ada evaluasi terbuka, apalagi perbaikan sistematis.
Hal ini menunjukkan masalah yang lebih dalam: negara enggan mengakui kegagalannya. Padahal, dalam demokrasi yang sehat, kegagalan bukanlah aib, tetapi peluang untuk membenahi diri.
Apa yang harus dilakukan?
Pertama, pemerintah harus melakukan audit menyeluruh terhadap pelaksanaan program makan bergizi gratis—dari pemilihan vendor, distribusi makanan, hingga mekanisme pengawasan. Audit ini harus melibatkan lembaga independen dan partisipasi masyarakat.
Kedua, perbaikan tata kelola harus menjadi prioritas. Pemerintah perlu menjamin bahwa kontrak dengan penyedia jasa dipenuhi dengan tertib administrasi, termasuk pembayaran yang tepat waktu.
Ketiga, desain menu makanan harus disesuaikan dengan kearifan lokal dan preferensi daerah, bukan seragam nasional yang serba dipaksakan. Keterlibatan ahli gizi daerah dan sekolah sangat diperlukan.
Keempat, jangan memaksakan perluasan program bila evaluasi belum tuntas. Lebih baik memperkuat kualitas di wilayah terbatas daripada mengorbankan kesehatan anak secara nasional.
Dalam segala kekacauan ini, kita harus ingat bahwa subjek utama dari program ini adalah anak-anak. Mereka bukan alat politik, bukan komoditas pencitraan, dan bukan bahan percobaan kebijakan. Mereka berhak mendapatkan asupan bergizi dalam kondisi layak, aman, dan menyenangkan.
Ketika negara gagal menyediakan itu, dan enggan mengakui kegagalannya, maka yang dipertaruhkan bukan hanya kesehatan anak—tetapi moralitas penguasa. Dan satu hal yang sering hilang dalam politik dan hukum kita hari ini: keberanian untuk jujur. Negara harus segera memperbaikinya, sebelum melanjutkan program ini lebih lanjut. Kalau tidak bisa, lebih baik dihentikan saja!

 Desi Sommaliagustina
Desi Sommaliagustina