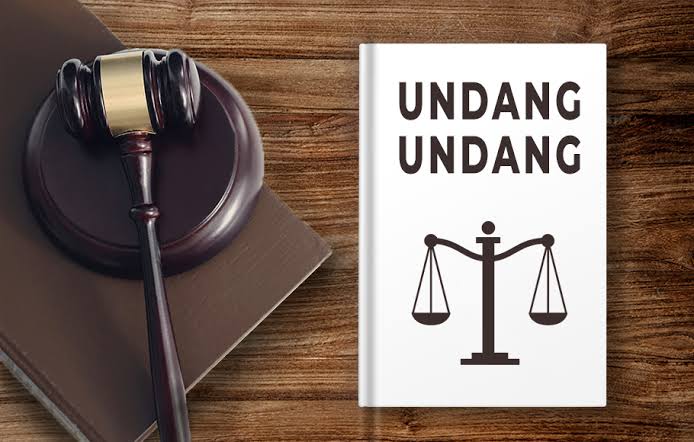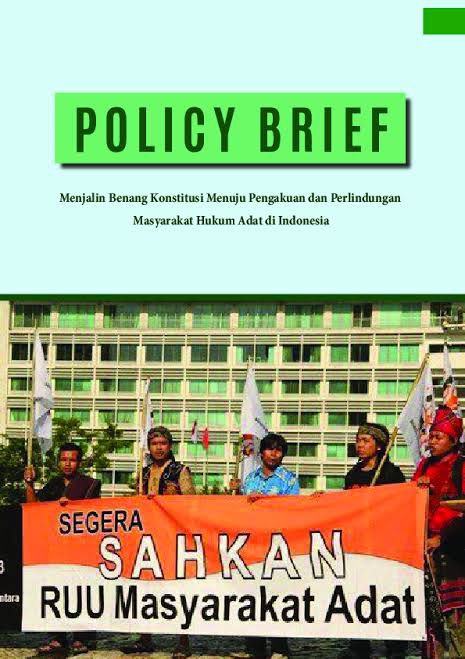Mahkamah Konstitusi kembali mencatatkan peran krusialnya dalam membatasi potensi penyalahgunaan kekuasaan melalui tafsir hukum yang multitafsir. Melalui Putusan Nomor 115/PUU-XXII/2024, Mahkamah menegaskan bahwa frasa “kerusuhan” dalam Pasal 28 ayat (3) dan Pasal 45A ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai sebagai kerusuhan yang terjadi di ruang fisik.
Putusan ini bukan sekadar interpretasi yuridis biasa, melainkan koreksi konstitusional terhadap praktik penegakan hukum yang selama ini rawan digunakan untuk membungkam ekspresi warga di ruang digital. Bagi masyarakat sipil, putusan ini menandai sebuah kemenangan penting dalam upaya menjamin hak atas kebebasan berekspresi di era siber.
Pasal 28 ayat (3) UU ITE versi terbaru menyebutkan bahwa: “Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan SARA yang menyebabkan kerusuhan dalam masyarakat.”
Secara semantik, frasa “menyebabkan kerusuhan dalam masyarakat” ini menjadi problematik karena memberikan keleluasaan interpretasi kepada aparat penegak hukum. Berbagai kasus membuktikan bahwa “keributan” di media sosial—yang semestinya dibaca sebagai bagian dari dinamika demokratis—kerap diartikan sebagai “kerusuhan” yang membahayakan ketertiban umum. Maka tak heran, kritik, lelucon politik, hingga ekspresi kemarahan yang sah secara konstitusional, justru dilabeli sebagai tindakan kriminal.
Mahkamah dalam putusannya dengan tepat membatasi ruang lingkup “kerusuhan” semata-mata pada peristiwa di ruang fisik. Artinya, perdebatan sengit, polemik tajam, hingga kegaduhan viral di media sosial tidak dapat serta-merta dimaknai sebagai delik pidana.
Hak Konstitusional, Keadaban Digital dan Implikasi Hukum
Secara konstitusional, Pasal 28E ayat (3) UUD 1945 menjamin hak setiap orang untuk menyampaikan pendapat. Pasal 28F UUD 1945 pun mengafirmasi hak setiap warga negara untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi. Ruang digital menjadi arena aktualisasi kedua hak tersebut dalam praktiknya hari ini.
Namun sayangnya, UU ITE telah lama menjadi pisau bermata dua—di satu sisi menjawab kebutuhan hukum dunia siber, namun di sisi lain, kerap menjadi alat kriminalisasi ekspresi warga. Salah satu contoh ekstrem adalah bagaimana unggahan atau cuitan yang memancing polemik, bisa dengan mudah ditarik ke ranah hukum dengan dalih “kerusuhan”. Dalam praktik penegakan hukum, tafsir atas “kerusuhan” kerap bergeser menjadi tafsir subjektif yang merefleksikan sensitivitas kekuasaan, bukan ancaman objektif terhadap ketertiban umum.
Putusan MK ini menempatkan kembali hukum dalam kerangka demokratis. Hukum bukanlah alat represi, melainkan pelindung kebebasan yang bertanggung jawab. Dengan menegaskan bahwa kerusuhan harus diartikan sebagai gangguan ketertiban di ruang fisik, MK mencegah kriminalisasi atas diskursus digital yang sejatinya merupakan napas demokrasi.
Putusan ini tentu memiliki implikasi besar terhadap praktik penegakan hukum. Aparat kepolisian dan kejaksaan tidak lagi memiliki dasar untuk menjerat ekspresi di media sosial sebagai delik “kerusuhan”. Kegaduhan digital, bahkan jika dianggap mengganggu, tetap harus dibaca dalam konteks ekspresi sosial, bukan sebagai ancaman pidana.
Lebih lanjut, putusan ini seharusnya mendorong pembuat undang-undang untuk segera mengevaluasi dan merevisi ketentuan-ketentuan bermasalah dalam UU ITE. Terlalu banyak pasal karet yang potensial digunakan secara diskriminatif—dari Pasal 27 ayat (3) tentang pencemaran nama baik, Pasal 28 ayat (2) tentang ujaran kebencian, hingga Pasal 36 tentang kerugian materiil.
Perlu ditegaskan bahwa tidak semua ekspresi yang menyinggung, mengganggu, atau menimbulkan kontroversi merupakan tindak pidana. Dalam sistem demokrasi, toleransi terhadap perbedaan, termasuk terhadap ekspresi yang keras sekalipun, adalah keharusan. Penegakan hukum harus dilakukan dengan mengedepankan prinsip proporsionalitas dan non-diskriminasi, bukan berdasarkan perasaan tersinggung penguasa atau institusi.
Mendorong Literasi Hukum dan Digital
Namun demikian, ruang digital tetap bukan wilayah tanpa batas. Perlindungan terhadap hak asasi orang lain, ketertiban umum, dan keamanan nasional tetap harus menjadi pertimbangan. Oleh sebab itu, literasi hukum dan digital menjadi penting. Warga negara harus memahami batas ekspresi yang bertanggung jawab, sementara negara wajib menjamin bahwa batas tersebut tidak berubah menjadi jerat yang menakutkan.
Kebisingan digital adalah harga dari kebebasan. Demokrasi tidak menghendaki keseragaman, melainkan perbedaan yang dikelola secara dewasa. Maka, kritik, satir, dan ekspresi emosi di ruang maya tidak boleh dibaca sebagai kerusuhan yang layak dipidana, melainkan sebagai alarm sosial yang menuntut perhatian.
Putusan MK ini harus dibaca sebagai koreksi terhadap pendekatan legalistik yang otoriter. Negara tak bisa memaksa ruang publik menjadi sunyi hanya karena penguasa tidak nyaman dengan kritik. Kebebasan berbicara bukanlah hadiah dari negara, melainkan hak bawaan yang dijamin konstitusi.
Dengan menafsirkan “kerusuhan” secara ketat, MK menegaskan bahwa hukum tidak boleh menjadi alat ketakutan di ruang digital. Hukum harus hadir sebagai penjaga nalar publik, bukan sebagai sensor negara. Putusan ini bukan hanya tentang UU ITE, tapi tentang arah demokrasi kita hari ini.

 Desi Sommaliagustina
Desi Sommaliagustina