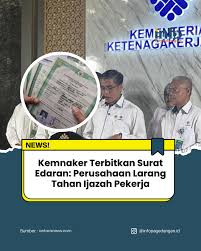Alih-alih menyederhanakan, berbagai platform digital pendidikan tinggi justru membebani dosen dan mahasiswa dengan beban administratif yang tidak manusiawi. Nama-nama seperti SISTER, SINTA, BIMA, hingga SIMBELMAWA yang semestinya menjadi alat bantu kerja akademik, kini berubah menjadi mesin penghisap waktu, tenaga, dan energi intelektual sivitas akademika.
Digitalisasi seharusnya menjadi jalan untuk mempercepat proses, memudahkan akses, dan memperbaiki mutu. Namun dalam praktiknya, ia telah menjadi sumber kelelahan kolektif. Misalnya, mewajibkan dosen untuk terus memperbarui data kepegawaian, SK jabatan, hingga portofolio pelatihan yang kadang tidak relevan. Sedikit saja kesalahan unggah file, maka hak dosen—termasuk tunjangan profesi dapat tertunda. Ini tidak hanya menciptakan ketidakpastian hukum, tapi juga ketidakadilan struktural.
Menciptakan strata keilmuan berbasis angka, bukan nilai kebermanfaatan. Dosen yang menulis rutin di media massa, membuat modul pelatihan masyarakat, atau menyusun naskah akademik untuk DPRD, bisa dinilai “tidak produktif” karena kontribusinya tak terbaca oleh algoritma SINTA. Ini memunculkan bias epistemik dan menghambat keanekaragaman metode produksi ilmu.
Lebih dari itu, sistem platfrom digital juga kerap mempersulit pengusulan riset karena lebih fokus pada kelengkapan administratif daripada kualitas ide. Banyak dosen yang ide penelitiannya ditolak hanya karena file PDF terlalu besar atau format tabel tak sesuai template hingga status dosen yang izin belajar tidak bisa mengusulkan penelitian.
Sedangkan untuk platform yang menampung kreativitas mahasiswa itu sendiri, justru mematikan kreativitas itu sendiri. Proposal yang inovatif bisa tersingkir karena kesalahan unggah atau kekurangan satu lampiran. Dosen pembimbing pun harus mengejar sistem, bukan membimbing gagasan.
Kritik Regulatif: Dimana Hukum Berdiri?
Ketika negara mendigitalisasi pendidikan tinggi, maka ia wajib tunduk pada asas-asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik (good governance). Pasal 10 UU Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menegaskan asas proporsionalitas, efektivitas, dan efisiensi sebagai prinsip yang tak boleh diabaikan. Namun, platform-platform digital justru melanggar prinsip tersebut.
Pasal 13 ayat (2) UU Pendidikan Tinggi (UU No. 12/2012) menegaskan hak dosen untuk menjalankan tridharma secara otonom. Tetapi, dengan beban sistem digital yang timpang, kebebasan akademik berubah jadi kewajiban administratif.
Tak hanya itu, Pasal 8 ayat (1) UU yang sama menjamin kemerdekaan akademik dan kebebasan mimbar ilmiah. Apakah kemerdekaan itu masih ada jika setiap langkah dosen harus dilaporkan, diverifikasi, dan dikodefikasi melalui sistem yang tidak mempercayai kapabilitas intelektual mereka?
Dalam kacamata hukum administrasi, situasi ini bisa disebut sebagai “abuse of discretion”, yakni penyalahgunaan diskresi oleh lembaga pendidikan tinggi yang memaksa dosen dan mahasiswa mengikuti sistem tanpa ruang untuk memperjuangkan logika akademik mereka sendiri.
Digitalisasi ini merupakan gejala dari manajemen pendidikan tinggi yang rakus kontrol, tapi miskin visi. Kampus dituntut memenuhi target kinerja dari kementerian yang dikalkulasi dalam angka unggahan, bukan kualitas pemikiran.
Situasi ini menciptakan “manajemen by spreadsheet”—di mana indikator kinerja hanya dilihat dari laporan dan statistik, bukan dampak terhadap masyarakat atau pemajuan ilmu. Tak heran, hasil riset yang menumpuk tak pernah jadi kebijakan publik. Publikasi menjamur, tapi perubahan sosial stagnan. Ini diperparah oleh birokratisasi kampus yang masih feodal. Dalam banyak kasus, pemimpin kampus lebih takut “salah unggah” daripada salah mendidik.
Negara-negara lain telah berhasil merancang sistem digital pendidikan tinggi yang human-centered—berpusat pada manusia, bukan data semata. Di Finlandia, digitalisasi pendidikan tinggi bersifat adaptive dan hanya menuntut input satu kali yang akan tersinkron otomatis antar sistem. Seorang dosen tidak perlu mengisi data yang sama berkali-kali di tempat berbeda. Sistem terintegrasi dengan prinsip kepercayaan dan pemangkasan birokrasi.
Untuk di Jerman sendiri, evaluasi kinerja dosen bukan hanya dari publikasi ilmiah, tetapi juga dari keterlibatannya dalam kebijakan publik dan kontribusi ke masyarakat. Sistem digital mereka tidak mendikte jenis karya, tapi memfasilitasi dokumentasi multi-platform.
Sedangkan di Kanada, mahasiswa memiliki sistem e-portfolio yang merekam perjalanan pembelajaran mereka tanpa harus mengunggah ulang dokumen yang sama. Validasi dilakukan berbasis akun institusi, bukan file per file.
Mengapa Indonesia Tak Bisa Mengikuti? Apa yang Harus Dilakukan?
Pertama, audit menyeluruh terhadap seluruh platform digital pendidikan tinggi. Harus ada evaluasi eksternal yang melibatkan sivitas akademika, bukan hanya birokrat.
Kedua, integrasi dan interoperabilitas sistem harus menjadi prioritas. Tidak boleh ada lagi pengisian data berulang-ulang. Data dari PDDikti, SISTER, dan BIMA harus saling terhubung secara real time.
Ketiga, redesain sistem digital berbasis prinsip “trust and facilitation”, bukan “suspicion and control”. Dosen dan mahasiswa bukan pelaku kriminal yang harus terus membuktikan eksistensinya.
Keempat, ubah indikator kinerja dari kuantitas ke kualitas. Ukur keberhasilan bukan dari jumlah unggahan, tapi dari sejauh mana kegiatan akademik menyentuh masyarakat.
Kelima, libatkan perancang sistem informasi dari kalangan akademisi dan praktisi pendidikan, bukan hanya vendor teknologi. Teknologi pendidikan harus dibangun dengan semangat pedagogis, bukan algoritma bisnis.
Jika kampus terus dipaksa menjadi pabrik pelaporan, maka kita tak sedang membangun bangsa, melainkan mencetak operator. Dosen akan kehilangan makna mengajar, mahasiswa kehilangan semangat berpikir, dan ilmu kehilangan orientasi sosialnya.
Pendidikan adalah usaha sadar untuk memanusiakan manusia. Maka, digitalisasi pendidikan tinggi Indonesia hanya akan bermakna jika ia mampu memanusiakan dosen dan mahasiswa, bukan menjadikan mereka budak sistem yang mereka tidak pahami dan tidak bisa lawan.
Sudah saatnya kita bertanya: Apakah sistem digital kita melayani pendidikan, atau pendidikan yang melayani sistem digital itu?

 Desi Sommaliagustina
Desi Sommaliagustina