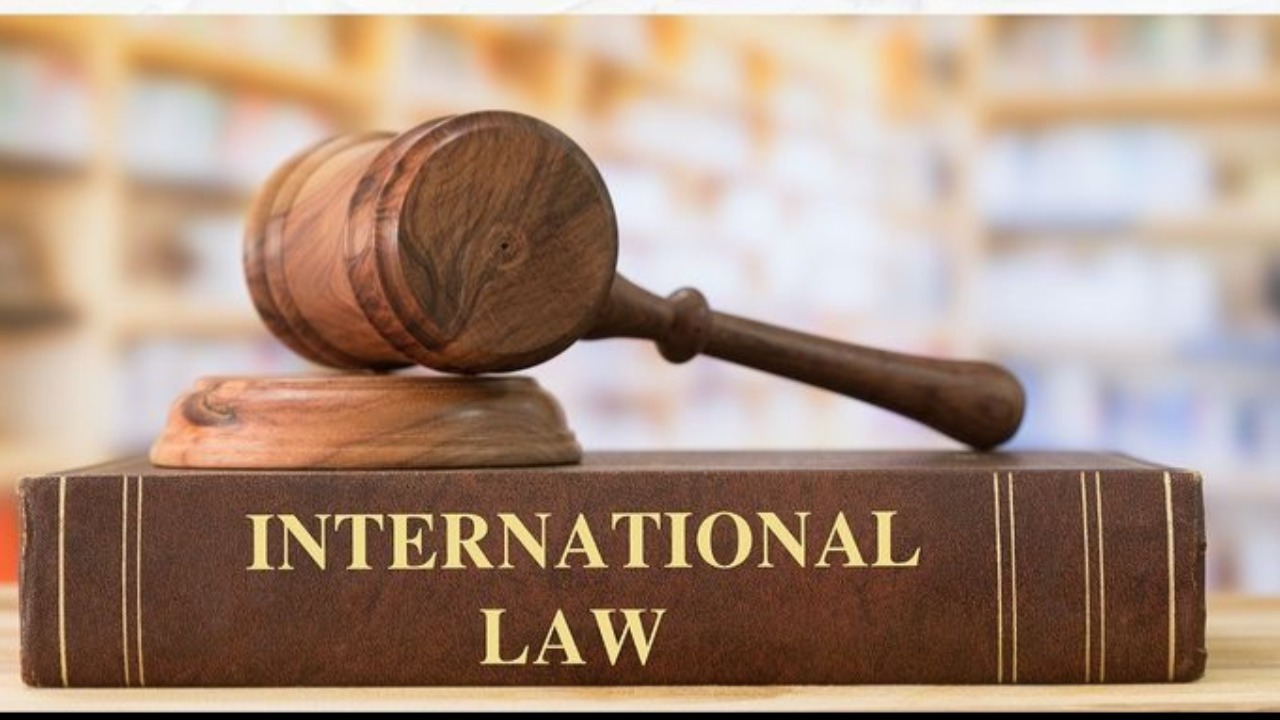Dalam beberapa dekade terakhir, dunia menyaksikan tragedi kemanusiaan yang menyayat hati: genosida di Rwanda, konflik di Suriah, dan pelanggaran HAM berat di Myanmar. Namun pertanyaannya tetap sama: kapan negara lain boleh campur tangan? Apakah tindakan intervensi merupakan bentuk kepedulian atau justru pelanggaran terhadap kedaulatan?
Intervensi kemanusiaan secara umum merupakan tindakan yang dilakukan untuk mencegah atau menghentikan pelanggaran berat terhadap hak asasi manusia (HAM) di suatu negara, dengan menggunakan berbagai bentuk kekuatan, baik secara diplomatik maupun militer. Tindakan ini dapat dilaksanakan, baik dengan seizin negara yang bersangkutan maupun tanpa persetujuan, terutama jika negara tersebut tengah mengalami konflik internal. Ketika terjadi pelanggaran HAM berat yang mengancam keselamatan manusia, masyarakat internasional dinilai memiliki legitimasi untuk melakukan intervensi guna melindungi korban. Pelanggaran berat terhadap HAM mencakup berbagai jenis, seperti kejahatan terhadap kemanusiaan, genosida, dan kejahatan perang. Konsep kejahatan terhadap kemanusiaan mulai dikenal dan diakui sebagai bagian dari hukum internasional yang berlaku secara positif setelah berakhirnya Perang Dunia II, melalui Charter of the International Military Tribunal (IMTN) di Nuremberg pada tahun 1946. Pengaturan lebih lanjut kemudian muncul dalam Charter of the International Military Tribunal for the Far East (IMTFE) atau Piagam Tokyo pada tahun 1948. Setelah itu, pengadilan internasional untuk kasus-kasus serupa didirikan, seperti International Criminal Tribunal for the former Yugoslavia (ICTY) pada 1993 dan International Criminal Tribunal for Rwanda (ICTR) pada 1994. Puncaknya, pembentukan Mahkamah Pidana Internasional (ICC) disahkan melalui Statuta Roma pada tahun 2002, yang secara resmi menjadi instrumen hukum permanen untuk mengadili kejahatan internasional paling serius.
Berdasarkan Pasal 39 Piagam PBB, Dewan Keamanan memiliki kewenangan untuk menentukan apakah suatu situasi tertentu merupakan ancaman terhadap perdamaian dan keamanan internasional. Jika ancaman itu diakui, Dewan Keamanan dapat mengeluarkan resolusi yang mengizinkan tindakan termasuk intervensi militer guna memulihkan perdamaian, seperti yang terjadi dalam intervensi terhadap rezim Gaddafi di Libya pada tahun 2011.
Selain itu, intervensi dapat dibenarkan apabila dilakukan atas permintaan dari pemerintah yang sah di negara yang bersangkutan. Dalam kondisi krisis domestik, seperti konflik bersenjata atau pemberontakan, sebuah pemerintahan yang sah secara hukum internasional berhak meminta bantuan dari negara lain untuk menjaga stabilitas nasional dan keamanan publik. Dalam hal ini, intervensi tidak dianggap sebagai pelanggaran kedaulatan, sebab dilandasi oleh permintaan resmi negara yang berdaulat.
Bentuk pembenaran lainnya ditemukan dalam Pasal 51 Piagam PBB, yang memberikan hak kepada negara untuk membela diri, baik secara individual maupun kolektif, jika mengalami serangan bersenjata. Dalam konteks ini, intervensi dapat terjadi sebagai bagian dari aksi pertahanan diri oleh satu negara atau kelompok negara terhadap ancaman yang membahayakan eksistensi mereka. Intervensi kolektif dalam menghadapi kelompok teroris internasional, seperti yang dilakukan oleh koalisi negara-negara dalam melawan ISIS, merupakan contoh implementasi prinsip pembelaan diri ini.
Yang paling kontroversial namun sering dibahas dalam diskursus hukum internasional adalah intervensi kemanusiaan. Jenis intervensi ini dilakukan untuk mencegah atau menghentikan pelanggaran hak asasi manusia yang sangat berat seperti genosida, pembersihan etnis, dan kejahatan perang. Meskipun tidak secara eksplisit diatur dalam Piagam PBB, intervensi kemanusiaan mendapat dasar moral dari prinsip Responsibility to Protect (R2P), yang disepakati oleh negara-negara anggota PBB dalam KTT Dunia tahun 2005. Intervensi ini bisa dilakukan bahkan tanpa persetujuan dari negara yang bersangkutan, jika negara tersebut terbukti gagal melindungi rakyatnya sendiri dari kekejaman sistematis. Namun demikian, legitimasi intervensi kemanusiaan harus benar-benar diuji, sebab tindakan semacam ini rawan disalahgunakan untuk kepentingan politik atau ekspansi kekuasaan negara lain.
Dengan demikian, meskipun intervensi pada dasarnya dilarang, hukum internasional tetap membuka ruang bagi tindakan tersebut dalam kondisi-kondisi tertentu yang dianggap sah secara hukum dan dibenarkan secara moral. Keseimbangan antara menjaga kedaulatan negara dan melindungi hak asasi manusia menjadi tantangan utama dalam menentukan kapan intervensi benar-benar diperlukan.
Intervensi kemanusiaan sering dianggap sebagai pengecualian moral atas larangan intervensi. Namun legalitasnya masih menjadi perdebatan. Sebagian sarjana menyatakan bahwa melindungi hak asasi manusia adalah tanggung jawab global, sementara yang lain menilai tindakan tersebut dapat disalahgunakan untuk kepentingan politik.
Salah satu contoh yang sering dikutip dalam perdebatan mengenai legalitas dan moralitas intervensi adalah keterlibatan NATO di Kosovo pada tahun 1999. Intervensi ini dilakukan tanpa adanya mandat resmi dari Dewan Keamanan PBB, yang dalam banyak kasus menjadi syarat utama untuk legalitas suatu tindakan militer internasional. Namun, NATO berdalih bahwa operasi militer tersebut dilakukan atas dasar kemanusiaan, untuk menghentikan kekejaman dan pembersihan etnis yang dilakukan oleh rezim Serbia terhadap etnis Albania di wilayah Kosovo. Meskipun tidak memiliki dasar hukum formal dari PBB, banyak kalangan memandang bahwa tindakan tersebut dapat dibenarkan secara moral karena mampu menghentikan kekerasan sistematis yang mengancam ribuan nyawa warga sipil.
Sebaliknya, kegagalan komunitas internasional dalam merespons genosida di Rwanda tahun 1994 menjadi gambaran nyata dari dampak buruk ketidaktegasan dalam mengambil keputusan intervensi. Selama sekitar 100 hari, lebih dari 800.000 orang – mayoritas dari etnis Tutsi – dibantai oleh milisi ekstremis Hutu, sementara dunia internasional hampir sepenuhnya pasif. PBB sendiri telah mengurangi jumlah pasukan penjaga perdamaian di Rwanda pada saat eskalasi kekerasan meningkat. Ketidaksiapan, ketakutan akan risiko politik, dan perdebatan berkepanjangan mengenai legalitas intervensi justru menyebabkan tragedi kemanusiaan yang seharusnya bisa dicegah. Dua kasus ini menunjukkan kontras yang tajam: ketika intervensi dilakukan tanpa mandat tetapi menyelamatkan nyawa, dan ketika kegagalan bertindak justru mengakibatkan penderitaan massal. Kedua peristiwa ini menjadi bahan refleksi penting tentang pentingnya keberanian, kecepatan, dan komitmen komunitas internasional dalam merespons krisis kemanusiaan.
Intervensi dalam konteks hukum internasional adalah suatu tindakan yang sangat kompleks karena berada di antara dua nilai fundamental yang sama-sama penting, yaitu kedaulatan negara dan perlindungan terhadap hak asasi manusia. Di satu sisi, prinsip kedaulatan merupakan landasan utama dalam hubungan antarnegara. Setiap negara memiliki hak eksklusif untuk mengatur urusan domestiknya tanpa campur tangan pihak luar. Prinsip ini tercantum jelas dalam Piagam PBB dan menjadi norma dasar dalam sistem internasional.
Namun, di sisi lain, ada kenyataan pahit bahwa tidak semua negara menggunakan kedaulatannya untuk melindungi rakyatnya. Dalam beberapa kasus, justru negara atau pemerintah yang sah menjadi pelaku pelanggaran HAM berat terhadap warganya sendiri. Dalam situasi seperti ini, dunia internasional dihadapkan pada dilema moral: apakah harus diam demi menghormati kedaulatan, atau bertindak demi menyelamatkan nyawa manusia?
Di sinilah pentingnya menjaga keseimbangan. Intervensi tidak boleh dilakukan secara gegabah hanya dengan dalih kemanusiaan, karena berisiko menimbulkan ketidakstabilan baru, penyalahgunaan kekuasaan, atau bahkan imperialisme terselubung. Sebaliknya, membiarkan kejahatan terhadap kemanusiaan berlangsung tanpa respons internasional adalah bentuk kelalaian yang sama bahayanya. Oleh karena itu, hukum internasional dituntut untuk terus berkembang, tidak hanya dalam aspek teknis legalitas, tetapi juga dalam dimensi moralitas dan keadilan.
Hukum internasional masa kini perlu bersifat responsif terhadap realitas global yang dinamis. Ia harus mampu menjamin bahwa intervensi dilakukan dengan dasar hukum yang kuat, mekanisme yang transparan, serta tujuan yang benar-benar berorientasi pada perlindungan manusia, bukan kepentingan politik semata. Dengan begitu, intervensi bisa menjadi instrumen yang tidak hanya sah secara hukum, tetapi juga adil dan manusiawi dalam pelaksanaannya.