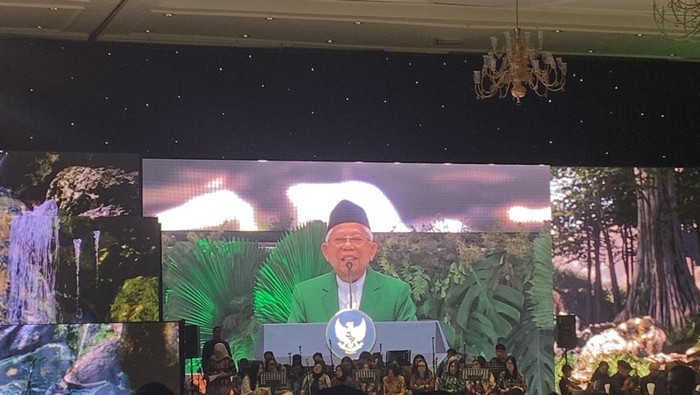Pendahuluan
Intervensi suatu negara dengan negara lain demi alasan kemanusiaan merupakan salah satu isu paling kompleks dan kontroversial dalam hukum internasional kontemporer. Di satu sisi, tindakan intervensi dianggap sah dan mendesak ketika terjadi pelanggaran berat terhadap hak asasi manusia, seperti genosida, kejahatan perang, atau pembersihan etnis, yang mengancam keselamatan warga negara atau komunitas tertentu di wilayah konflik terutama melihat kewajiban suatu negara dalam menjaga hak asasi manusia terutama warga negaranya di daerah konflik. Dalam konteks ini, intervensi kemanusiaan memiliki legitimasi moral yang kuat sebagai upaya menjaga martabat manusia dan negara dengan melindungi nyawa manusia. Namun, di sisi lain, prinsip kedaulatan negara dan larangan intervensi yang diatur secara tegas dalam Piagam Perserikatan Bangsa – Bangsa (PBB) menuntut agar setiap tindakan intervensi mendapat izin dari Dewan Keamanan PBB (DK PBB) dapat menghalangi suatu negara melindungi warga negaranya di daerah konflik atau suatu negara menjaga moralitas kemanusiaan. Hal ini menimbulkan dilema besar bagi negara-negara yang memiliki kewajiban melindungi warga negaranya yang berada di wilayah konflik, terutama ketika proses perizinan dari DK PBB terhambat oleh kepentingan politik dan veto negara anggota tetap di PBB. Tulisan ini akan mengkaji kontradiksi antara kebutuhan kemanusiaan untuk bertindak cepat demi melindungi warga negara dengan kepatuhan terhadap legalitas internasional dan bagaimana jika terhambat oleh izin DK – PBB, serta bagaimana negara dapat bersikap dan mengambil keputusan ketika izin DK PBB tidak diperoleh dalam situasi darurat kemanusiaan.
Konflik Antara Kewajiban Moral Dan Terbatasnya Hukum Internasional Dalam Intervensi Kemanusiaan
Intervensi dengan alasan kemanusiaan merupakan bentuk tindakan yang secara moral dipandang mulia karena bertujuan melindungi individu atau kelompok yang menjadi korban pelanggaran berat hak asasi manusia, mengingat setiap orang berhak untuk hidup dan tanpa disiksa. Namun, di balik niat kemanusiaan tersebut, tersimpan ketegangan mendasar antara kwajiban memenuhi legitimasi moral dan legalitas hukum internasional. Dilihat dari sisi legitimasi moral, negara memiliki tanggung jawab untuk bertindak ketika menghadapi
kejahatan kemanusiaan seperti genosida, pembersihan etnis, dan kejahatan terhadap kemanusiaan baik di dalam negaranya atau yang terjadi di luar negaranya. Fakta menyebutkan gagalnya komunitas internasional terhadap pencegahan tragedi di Rwanda (1994) dan Srebrenica (1995) menjadi history pahit bahwa diamnya dunia bisa berarti membiarkan kekejaman terus berlangsung dan tentunya melanggar nurani kemanusiaan. History kelam tersebut yang menjadi pijakan bahwasannya intervensi atas kemanusiaan dibutuhkan bahkan diwajibkan. Akan tetapi, dilihat menurut legalitas hukum internasional khususnya Piagam PBB Pasal 2 ayat (4) menegaskan secara tegas larangan terhadap penggunaan kekerasan antarnegara (Non – Intervensi), kecuali dalam hal membela diri atau mendapat mandat dari Dewan Keamanan PBB.
Lantas bolehkah suatu negara atau aktor lain melakukan intervensi tanpa izin resmi demi kemanusiaan? dari sisi moralitas dirasa boleh. Namun, secara legalitas masih membutuhkan pertimbangan yang kompleks. Ketika Dewan Keamanan PBB gagal memberikan otorisasi karena faktor – faktor yang mempengaruhi, misalnya perbedaan kepentingan politik, terutama veto dari anggota tetap, maka memicu negara terkait menghalalkan intervensi dengan alasan kemanusiaan. Hal ini menciptakan ruang abu-abu antara norma hukum internasional dan kebutuhan mendesak untuk melindungi nyawa manusia. Contoh paling kontroversial adalah intervensi NATO di Kosovo tahun 1999 yang dilakukan tanpa mandat PBB namun diklaim sebagai tindakan “legitim but not legal” dan memicu pro kontra dari berbagai negara. Dilema ini menunjukkan bahwa dalam praktiknya, hukum internasional belum sepenuhnya mampu menjawab dan memenuhi kebutuhan mendesak yang bersifat moral, terutama ketika struktur otoritasnya tersandera oleh kepentingan politik global (veto). Maka, muncul tantangan besar bagi komunitas internasional untuk memperjelas standar intervensi kemanusiaan agar dapat menjembatani konflik antara legalitas dan legitimasi, tanpa mengabaikan prinsip-prinsip hukum internasional maupun tuntutan moral universal serta pentingnya komitmen dalam menjaga kemanusiaan internasional.
Ketegangan Antara Kebutuhan Tindakan Kemanusiaan Segera Dan Kepatuhan Pada Aturan Hukum Internasional Berdampak Terhadap Stabilitas Internasional
Beberapa kasus internasional telah menjadi bukti akan adanya dilema moralitas dan legalitas. Dilema tersebut, seperti intervensi NATO di Kosovo (1999) tanpa mandat PBB, yang secara legal dipertanyakan namun secara moral mendapat dukungan luas dari beberapa pihak yang menganggap bahwa kemanusiaan di atas segalanya. Sebaliknya, konflik Suriah menjadi
momok terhadap eksistensi organisasi perdamaian internasional, bagaimana DK PBB gagal bertindak akibat kepentingan politik berupa hak veto, meski kekejaman terhadap warga sipil terjadi terus-menerus. Ketegangan antara legalitas dan legitimasi tidak memiliki titik temu dengan membuka spekulasi – spekulasi lainnya, namun membuka ruang refleksi: apakah sistem internasional lebih berpihak pada stabilitas politik atau pada perlindungan nyawa manusia? Rahasia umum, Dalam banyak kasus, respons internasional lebih mencerminkan kepentingan geopolitik dibanding nilai-nilai kemanusiaan yang semestinya menjadi dasar hukum internasional itu sendiri.
Perserikatan Bangsa – bangsa (PBB), dalam hal ini Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa – Bangsa (DK PBB) dinilai telah gagal secara mencolok dan tragis dalam menjalankan mandat utamanya untuk menjaga perdamaian dan keamanan internasional, baik terutama dalam merespons krisis kemanusiaan besar yang terjadi di berbagai belahan dunia hingga berlarut – larut. Tidak dapat dipungkiri fakto penyebab kegagalan ini sebagian besar disebabkan oleh faktor internal yang sangat problematik, khususnya keberadaan hak veto yang dimiliki oleh lima anggota tetap (Amerika Serikat, Rusia, Tiongkok, Prancis, dan Inggris). Hak istimewa ini tentunya telah disalah gunakan untuk melindungi kepentingan geopolitik sempit masing-masing negara, mengorbankan kepentingan kemanusiaan global yang menjadi tujuan utama dari suatu negara hingga organisasi internasional berbasis kemanusiaan, seperti PBB. Contoh nyata gagal PBB dapat dilihat dari berulangnya blokade resolusi yang mengutuk pelanggaran hak asasi manusia atau mengupayakan intervensi dalam konflik brutal seperti di Suriah, Palestina, dan Myanmar. bukannya bertindak untuk melindungi korban pelanggaran kemanusiaan, DK – PBB justru sering kali gagal bergerak karena adanya veto dari satu atau lebih negara yang memiliki kepentingan geopolitik di wilayah konflik tersebut. Ketika satu negara menggunakan veto untuk membungkam suara mayoritas global demi kepentingan politik atau aliansi strategis dengan berargumentasi hasil interpretasi subjektif suatu negara yang berkepentingan, DK – PBB kehilangan legitimasi moral dan operasionalnya, hingga menjadi alat melanggengkan kepentingan sempit suatu negara besar dalam tubuh PBB. Hal ini bukan hanya meruntuhkan kepercayaan masyarakat internasional terhadap lembaga multilateral, tetapi juga memperparah penderitaan jutaan manusia yang menjadi korban kekerasan, genosida, dan penindasan sehingga wajar eksistensi PBB dalam perlindungan hak asasi manusia dan sebagai agen perdamaian dipertanyakan. Apabila struktur yang cacat ini terus dibiarkan tanpa reformasi mendasar, dunia akan menghadapi peningkatan konflik bersenjata, instabilitas regional, dan kemunduran tatanan
internasional berbasis hukum yang menyebabkan tergoyangnya stabilitas internasional. Negara-negara akan semakin cenderung mengambil tindakan sepihak dengan alasan kemanusiaan serta menjaga harga diri negara tersebut serta memicu perlombaan senjata dan meningkatnya intervensi tanpa mandat global yang sah, yang pada akhirnya melemahkan fondasi perdamaian dunia dan menciptakan kekacauan geopolitik jangka panjang.
Lemah dan lambatnya DK – PBB dalam merespons pelanggaran besar terhadap hak asasi manusia secara cepat, tegas, dan merata adalah cerminan dari krisis struktural yang akut. Hak veto yang dimiliki oleh lima negara besar yang mendominasi dalam tubuh PBB bukan hanya menjadi simbol ketimpangan kekuasaan dalam sistem internasional, tetapi telah menjelma menjadi senjata politik yang membunuh fungsi utama DK PBB itu sendiri. Alih- alih menjadi pelindung perdamaian dunia layaknya super hero yang muncul di tengah porak- porandanya kemanusiaan dan perdamaian internasional, justru sering menjadi panggung kepentingan negara-negara besar yang berlindung di balik hak veto untuk membungkam kecaman terhadap sekutu atau diri mereka sendiri. Lembaga internasional yang diharapkan terakhir yang seharusnya menjadi garda terdepan melindungi kemanusiaan berubah menjadi saksi pasif seperti bisu dan tuli dari tragedi global dari pembantaian di Suriah, penindasan di Palestina, hingga krisis kemanusiaan di Myanmar dan Sudan.
Di sisi lain, Tindakan sepihak dan pragmatis suatu negara yang mengklaim bertindak atas nama kemanusiaan, hingga melanggar prinsip proporsionalitas dan legalitas internasional, patut dikritik dengan keras sebagai bentuk hipokrisi politik dan ancaman serius terhadap tatanan dunia yang berbasis hukum. Ketika sebuah negara melancarkan serangan militer yang tidak seimbang dan semena – mena, menjatuhkan korban sipil dalam jumlah besar tanpa adanya pemilah secara bijak atau melakukan pendudukan tanpa dasar hukum yang sah, lalu membenarkannya dengan retorika “intervensi kemanusiaan”, maka tindakan tersebut bukan hanya mencederai nilai-nilai kemanusiaan sejati, tetapi juga melemahkan dan menghianati prinsip dasar hukum humaniter internasional. Ini menciptakan preseden berbahaya dalam dunia hubungan internasional, di mana negara-negara merasa bebas untuk bertindak agresif atas dasar interpretasi sepihak terhadap moralitas, tanpa pertanggungjawaban dan di luar kerangka hukum internasional yang telah disepakati, seperti Piagam PBB, Konvensi Jenewa, dan hukum perang. Jika praktik semacam ini dilanggengkan, dunia akan memasuki fase destabilisasi serius, bagaimana norma – norma internasional akan kehilangan otoritasnya, lembaga multilateral akan lumpuh, dan semakin banyak negara yang memilih pendekatan
ambisi kekuasaan daripada dialog diplomatik. Akibatnya, kekerasan dan kerusakan akan meluas, konflik akan semakin brutal, dan rakyat sipil tak berdosa akan selalu menjadi korban utama dan hasil akan kembali pada logika rimba, di mana kekuatan menentukan kebenaran, bukan keadilan atau hukum. Ini adalah kemunduran peradaban dan ancaman nyata bagi perdamaian global jangka panjang.
Dalam dewasa ini, menghadapi realitas pahit dunia internasional saat ini, tidak dapat disangkal bahwa baik negara-negara yang bertindak sepihak dengan dalih kemanusiaan, maupun organisasi internasional seperti PBB, justru menjadi bagian dari permasalahan besar yang mengancam kredibilitas dan stabilitas tatanan global yang telah dibangun berabad – abad. Negara-negara yang melakukan intervensi dengan menggunakan kekuatan militer tanpa mandat hukum internasional yang sah dan tanpa mempertimbangkan prinsip proporsionalitas, justru menjadi aktor utama menyalahgunakan nilai-nilai kemanusiaan sebagai tameng untuk melanggengkan kepentingan geopolitik dan hegemoni regional. Klaim intervensi demi menyelamatkan warga sipil menjadi alat pembenar untuk agresi, pelanggaran wilayah kedaulatan atau tidak mengindahkan asas kedaulatan dan penghancuran infrastruktur sipil, yang justru memperburuk penderitaan rakyat yang seharusnya mereka lindungi. Ini bukan lagi sekadar penyimpangan, tetapi bentuk nyata manipulasi moral yang menciptakan ketidakpercayaan global terhadap setiap retorika kemanusiaan yang keluar dari negara-negara kuat.
Sinergi Moralitas dan Legalitas dalam Stabilitas Tatanan Internasional terhadap Kepentingan Kemanusiaan dan Intervensi Global
Dalam menjaga stabilitas tatanan internasional, sesuai harapan dunia internasional sinergi antara moralitas kemanusiaan dan legalitas hukum internasional menjadi fondasi yang tidak dapat dipisahkan, terutama dalam konteks intervensi atas nama kemanusiaan, Ia harus berjalan beriringan secara koridor masing – masing. Moralitas tanpa memperhatikan legalitas rawan disalahgunakan sebagai pembenaran tindakan sepihak yang destruktif, sementara legalitas tanpa mempertimbangkan moralitas berisiko menjadi alat pembenaran bagi kelambanan dan ke tidak pedulian terhadap penderitaan manusia. Oleh karena itu, setiap negara harus menumbuhkan kesadaran akan esensi dan eksistensinya sebagai aktor utama hukum yang berkewajiban dan memiliki rasa bertanggungjawab menaati norma internasional dan bertindak dalam kerangka yang sah, bukan berdasarkan kepentingan sepihak yang dibungkus retorika moral. Di sisi lain, PBB, sebagai representasi kolektif masyarakat dunia,
memiliki tanggung jawab utama dan besar terhadap moral untuk bertindak adil, konsisten, dan berani dalam menegakkan nilai-nilai kemanusiaan, serta tidak boleh tunduk pada kepentingan politik anggota-anggota kuatnya. Kesadaran bersama ini menjadi kunci untuk mewujudkan keadilan substantif, kepastian hukum tanpa adanya diskriminatif, serta kemanfaatan hukum internasional yang berpihak pada perlindungan umat manusia. Tanpa harmonisasi antara moralitas dan legalitas, hukum internasional hanya akan menjadi simbol kosong yang gagal dan sekedar penghias dalam memberikan perlindungan nyata bagi korban kekerasan dan ketidakadilan di seluruh dunia.
Dalam menangani dilema ini tidak cukup dengan reformasi normatif atau seruan moral belaka. ketegasan terhadap pembatasan atau bahkan penghapusan hak veto dalam situasi pelanggaran serius terhadap hak asasi manusia, pembentukan badan independen yang dapat memverifikasi legalitas dan legitimasi setiap tindakan militer atas nama kemanusiaan hingga pengawasan secara komprehensif serta penegakan sanksi yang adil terhadap negara manapun yang terbukti menyalahgunakan intervensi kemanusiaan. Selama tidak ada inisisi ataupun inisiatif untuk mendobrak tatanan lama, maka dunia akan terus berada dalam lingkaran hipokrisi dan ketidakadilan, di mana hukum tunduk pada kekuasaan, dan kemanusiaan hanya menjadi simbol kosong di panggung diplomasi.
Kesimpulan
Dalam dunia yang kompelsitas ini, intervensi dengan landasan moralitas kemanusiaan muncul sebagai respon mendesak atas tragedi kemanusiaan yang tak kunjung tertangani. Akan tetapi di sisi lain, seringkali terkekang oleh prinsip legalitas formal, seperti asas non- intervensi dan kedaulatan negara yang dilindungi Piagam PBB. Ketika negara bertindak secara sepihak dengan mengabaikan legalitas disebabkan dampak dari anggapan gagalnya esensi dan eksestensi PBB maka yang terjadi adalah kekosongan hukum, kegagalan perlindungan, serta keruntuhan tatanan dunia berbasis norma.
Realitas pahit ini menuntut adanya kesadaran kolektif dan reformasi fundamental, negara harus menyadari tanggung jawabnya terhadap legalitas dan moralitas, apalagi menjadikan dalih kemanusiaan sebagai alat pembenaran politik atau ekspansi kekuasaan. Sementara PBB, khususnya DK PBB, harus segera direstrukturisasi secara komprehensif termasuk membatasi atau menghapus hak veto dalam kasus pelanggaran berat terhadap hak asasi manusia. kesadaran pentingnya menciptakan dan menjaga sinergi antara moralitas dan
legalitas, serta membangun sistem yang adil, dan tidak diskriminatif, dapat memastikan bahwa intervensi kemanusiaan dilakukan bukan untuk kekuasaan, tetapi benar-benar untuk melindungi hak asasi manusia. Sampai kapan manusia akan menjadi korban dari sistem global yang penuh ketimpangan dan manipulatif ini?