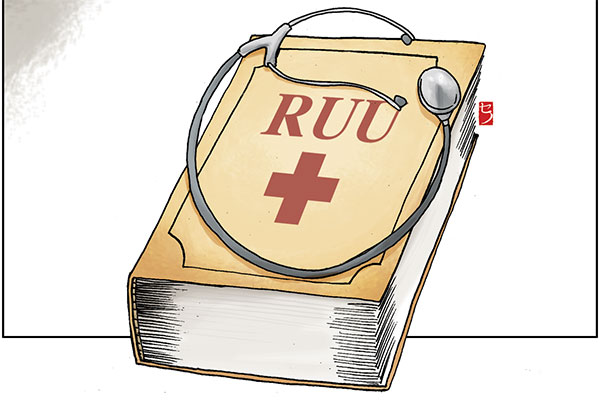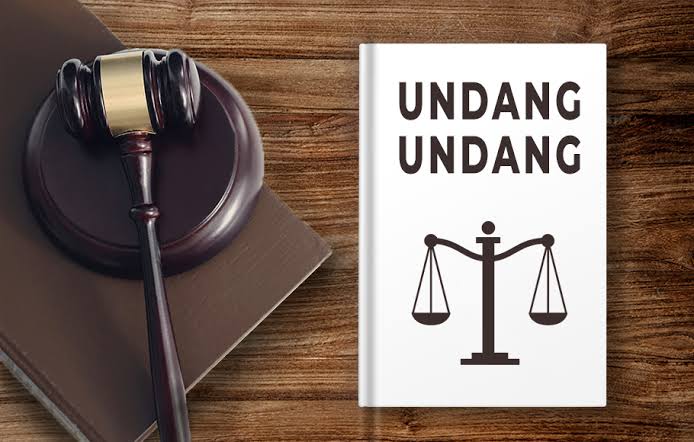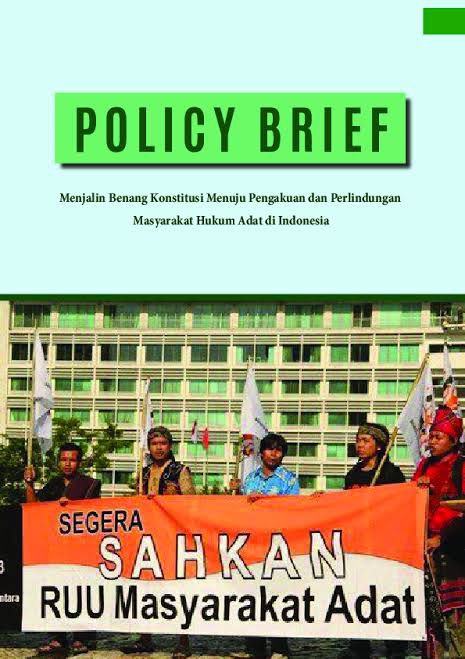Dalam beberapa tahun terakhir, perceraian bukan lagi topik yang tabu. Ia bahkan menjelma menjadi konten, komoditas, dan konsumsi harian media sosial. Kisah rumah tangga yang retak karena kehadiran orang ketiga tersebar luas, tidak hanya di kalangan selebritas, tetapi juga tokoh publik, pejabat negara, hingga figur keagamaan. Yang lebih mencemaskan, perselingkuhan tak lagi dilihat sebagai aib, melainkan godaan yang dapat “dimaklumi”, bahkan dirayakan sebagai hak pribadi untuk bahagia.
Pertanyaannya sederhana namun mendesak: ketika godaan menjadi pembenaran, dan perceraian tak lagi dianggap sebagai kegagalan, di manakah kita menempatkan hukum dan moral publik?
Ketika Cinta Menjadi Alibi
Pergeseran persepsi terhadap perselingkuhan sangat terasa. Dalam banyak narasi publik, pelaku kerap membungkus tindakannya dengan dalih “jatuh cinta”, “tidak menemukan kebahagiaan dalam rumah tangga”, atau “tidak cocok secara emosional dengan pasangan sahnya”. Alibi-alibi ini, meskipun personal, tak bisa berdiri sendiri tanpa mengabaikan fakta hukum: bahwa setiap perkawinan yang sah secara hukum membawa implikasi tanggung jawab, tidak hanya terhadap pasangan dan anak, tetapi juga terhadap tatanan sosial.
Di satu sisi, hak setiap orang untuk mencari kebahagiaan memang diakui. Namun dalam ruang hukum dan etika publik, kebebasan itu memiliki batas. Menyebabkan penderitaan emosional pada pasangan sah, atau merusak struktur keluarga yang sah secara hukum, adalah pelanggaran terhadap kontrak sosial yang dilindungi hukum.
Secara normatif, Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (yang telah diperbarui melalui UU Nomor 16 Tahun 2019) mengatur bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di hadapan sidang pengadilan, dengan alasan-alasan sah, salah satunya adalah zina atau perselingkuhan. Akan tetapi, implementasi pasal ini menghadapi tantangan serius, terutama dalam hal pembuktian.
Dalam praktik peradilan, gugatan cerai lebih sering diajukan dengan alasan “pertengkaran terus-menerus” atau “sudah tidak ada keharmonisan”, karena lebih mudah dibuktikan daripada perselingkuhan. Pembuktian perselingkuhan kerap memerlukan bukti elektronik, foto, saksi, hingga laporan pihak ketiga, yang belum tentu dimiliki atau tersedia secara sah.
Celakanya, tidak ada ketentuan kompensasi hukum secara otomatis bagi pasangan sah yang menjadi korban perselingkuhan. Perlindungan hukum masih bersifat reaktif, dan hanya bisa dilakukan melalui gugatan perdata terpisah—yang tidak semua korban mampu atau mau lakukan. Akibatnya, pelaku perselingkuhan dapat melenggang bebas, bahkan secara hukum bisa menikah kembali tanpa beban.
KUHP Baru: Aduan atau Kekosongan?
Harapan terhadap perlindungan hukum dari jeratan perselingkuhan juga dipertaruhkan dalam KUHP baru (UU No. 1 Tahun 2023), yang akan berlaku efektif mulai 2026. Dalam KUHP ini, perzinahan tetap dikriminalisasi, tetapi hanya bisa diproses jika ada aduan dari pasangan sah, anak, atau orang tua pelaku. Artinya, negara hanya akan turun tangan jika korban sendiri mengadu. Ini menegaskan bahwa hukum kita cenderung memilih pendekatan privat terhadap isu yang berdampak sosial luas.
Model delik aduan ini berisiko menimbulkan kekosongan perlindungan hukum, terutama jika korban berada dalam posisi ketergantungan ekonomi atau tekanan sosial sehingga tidak dapat mengadu. Dalam banyak kasus, perempuan menjadi pihak yang paling dirugikan: mereka tidak hanya dikhianati, tetapi juga tidak memperoleh keadilan hukum.
Perceraian akibat perselingkuhan bukan hanya drama keluarga. Ia adalah krisis sosial. Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa dalam lima tahun terakhir, lebih dari 25% kasus perceraian disebabkan oleh perselingkuhan. Ini bukan angka kecil. Di balik statistik itu, ada anak-anak yang kehilangan struktur keluarga, perempuan yang terluka secara psikis dan finansial, serta masyarakat yang lambat laun menjadi permisif terhadap pelanggaran komitmen.
Ketika publik lebih tertarik pada cerita siapa yang selingkuh dengan siapa, daripada menuntut tanggung jawab moral dan hukum pelaku, maka telah terjadi erosi kesadaran kolektif. Norma sosial yang seharusnya menjadi pagar moral kini kehilangan daya. Perselingkuhan tak lagi mengundang rasa malu, tetapi mendapat panggung.
Selebriti yang pernah berselingkuh masih dipuja. Tokoh publik yang diketahui memiliki hubungan gelap tetap dipercaya. Bahkan ada figur politik yang perceraiannya justru mendongkrak popularitas. Apa yang sedang kita alami?
Ketimpangan Gender dalam Perlindungan
Perempuan dalam posisi istri masih menjadi kelompok yang paling rentan dalam skenario ini. Mereka sering kali berada dalam situasi dilematis: bertahan dalam relasi toksik demi anak dan status, atau menggugat cerai dan menghadapi stigma sebagai “istri gagal”. Sementara pelaku, terutama jika laki-laki, lebih mudah diterima kembali secara sosial.
Di ranah hukum pun, perempuan sering mengalami reviktimisasi. Saat menggugat cerai dengan alasan perselingkuhan, mereka harus membuktikan, menanggung biaya hukum, dan menghadapi tekanan dari keluarga maupun masyarakat. Belum lagi jika mereka tidak bekerja atau bergantung ekonomi pada pasangan. Maka tak heran, banyak korban perselingkuhan memilih diam—karena negara dan masyarakat tak hadir di pihak mereka.
Masalah ini tak bisa diselesaikan hanya dengan menambal pasal-pasal hukum. Diperlukan perbaikan menyeluruh dalam pendekatan hukum keluarga, termasuk perlindungan psikososial, skema ganti rugi atas pelanggaran janji perkawinan, dan dukungan terhadap korban perselingkuhan—baik istri maupun suami.
Lebih dari itu, pendidikan karakter dan literasi etika rumah tangga perlu masuk ke dalam sistem pendidikan dan ruang publik. Kesetiaan bukanlah nilai yang kuno. Ia adalah prasyarat terbentuknya kepercayaan. Dan kepercayaan adalah fondasi dasar masyarakat yang sehat.
Jika hukum terlalu lambat menyesuaikan diri dan masyarakat terlalu cepat menormalisasi penyimpangan, maka kita akan kehilangan pijakan moral. Pernikahan akan kehilangan makna hukum. Perselingkuhan akan terus menggoda—dan tidak lagi dianggap salah.

 Desi Sommaliagustina
Desi Sommaliagustina